Tauhid al-Asma wa ash-Shifat adalah beriman dan yakin terhadap setiap nama dan sifat Allah, yang Allah sendiri sifatkan bagi Diri-Nya di dalam al-Qur’an dan yang disifatkan oleh rasul-Nya di dalam hadits-hadits yang shahih, secara hakiki tanpa tahrîf, takyîf, ta’thîl, tamtsîl dan tanpa tafwîdh.
Tahrîf adalah merubah lafadz atau makna sebuah nama atau sifat Allah Ta’ala kepada makna yang bukan makna sebenarnya.
Takyîf adalah menggambarkan (visualisasi) sifat-sifat Allah, atau mempertanyakan kaifiyyat (substansi) dari sifat tersebut.
Ta’thîl adalah menolak dan mengingkari sebagian atau seluruh nama-nama atau sifat-sifat Rabb Yang Maha Mulia.
Sementara tamtsîl (atau kadang diistilahkan dengan tasybîh) adalah menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk ciptaan-Nya.
Adapun tafwîdh adalah menyerahkan makna nama atau sifat tersebut kepada Allah subhanahu wa ta’ala. Menurut para ulama Salaf Ahlussunnah wal Jama’ah, tafwîdh hanya pada al-kayf (hal, keadaan), tidak pada maknanya.
Contoh untuk memahami kaedah ini adalah firman Allah : “Ar-Rahman (Tuhan Yang Maha Pemurah) yang ber-istiwâ’ (bersemayam) diatas ‘Arsy”. [terjemah QS. 20 ayat 5]
Sikap yang benar bagi seorang mukmin terhadap ayat ini adalah :
1. Beriman bahwa salah satu sifat Allah ‘azza wa jalla adalah istiwâ’ (bersemayam) diatas ‘Arsy.
2. Beriman bahwa manusia mengetahui makna dari kata tersebut, karena demikianlah Allah menyampaikan kata itu kepada manusia. Sangat mustahil bila Allah mengabarkan sesuatu yang tidak dipahami oleh para hamba-Nya.
Beriman bahwa tidak seorang pun yang tahu hakikat/ substansi dari sifat tersebut, namun hanya Allah saja yang mengetahuinya.
4. Beriman bahwa seluruh nama dan sifat Allah adalah “husnâ” (sangat baik dan indah) sesuai dengan Kebesaran dan Keagungan-Nya, dan tidak satu pun makhluk yang semisal dengan-Nya.
5. Tidak melakukan tahrîf atau men-takwîl (menafsirkan) kata “istawâ” dengan pengertian yang tidak bersesuaian dengan pengertian asal dari kata tersebut, misalnya dengan mengatakan maksud dari kata itu adalah “berkuasa” (istilâ’) dan bukan “bersemayam” (istiwâ’).
6. Tidak melakukan takyîf terhadap sifat tersebut, yaitu dengan memvisualisasikan (menggambarkan) atau mempraktekkan atau mempertanyakan substansi dari sifat itu.
7. Tidak melakukan ta’thîl, yaitu dengan menafikan atau mengingkari keberadaan sifat tersebut bagi Allah Ta’ala.
8. Tidak melakukan tamtsîl / tasybîh, yaitu dengan menyerupakan sifat Allah tersebut dengan sifat salah satu dari makhluk ciptaan-Nya. Kalau saja sesama makhluk memiliki perbedaan sifat yang sangat nyata walaupun sama dalam nama, maka bagaimana mungkin membandingkan sifat antara makhluk yang lemah dengan al-Khâliq (Sang Pencipta) Yang Maha Sempurna.
9. Tidak melakukan tafwîdh terhadap makna sifat tersebut, yaitu dengan menyatakan bahwa tidak seorang pun yang mengetahui makna dari sifat “istiwâ’”, hanya Allah saja yang mengetahui makna dari sifat tersebut.
Demikianlah sikap yang benar bagi seorang muslim berkenaan dengan ayat tersebut, dan demikianlah aqidah yang benar dalam masalah ini.
Kaedah-kaedah yang disebutkan berkenaan dengan sifat istiwâ’ diatas berlaku pula untuk seluruh sifat-sifat Allah yang lainnya seperti al-Kalâm (berbicara, QS. 4 : 164), ar-Rahmah (kasih sayang, QS. 6:54), ar-Ridho’ (kerelaan, QS. 98:8), al-Ghadab (murka, QS. 4:93) dan lain-lain.
Aqidah Imam asy-Syafi’i rahimahullah
Imam asy-Syafi’i rahimahullah pernah ditanya tentang sifat-sifat Allah dan bagaimana keimanan beliau terhadap sifat tersebut, maka beliau menjawab :
“Allah Ta’ala memiliki nama-nama dan sifat-sifat, yang telah disebutkan dalam Kitab-Nya dan dikabarkan nabi-Nya kepada umatnya. Tidak ada keleluasaan bagi seorang pun dari para hamba Allah yang telah sampai padanya hujjah (dalil) untuk menolaknya karena al-Quran telah turun menjelaskannya dan telah shahih dari Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam perkataan tentangnya dengan apa yang diriwayatkan orang-orang terpercaya dari beliau.
Jika orang tersebut menyelisihinya setelah sampainya hujjah, maka dia kafir. Adapun sebelum sampainya hujjah, maka dia memiliki uzur karena kejahilannya. Karena ilmu tentang hal itu tidak mungkin dicapai dengan akal, tidak pula dengan penglihatan dan pemikiran semata. Seorang pun tidak boleh dikafirkan dengan kejahilan kecuali setelah sampai berita kepadanya. Dia menetapkan sifat-sifat tersebut dan menolak tasybih sebagaimana Allah telah meniadakan tasybih dari Diri-Nya. Allah berfirman:
’Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dan Dia-lah Yang Maha Mendengar lagi Maha Melihat’.”
(Ijtimâ’ al-Juyûsy al-Islâmiyyah, Ibnul Qayyim. Kutipan ayat adalah terjemahan QS. 42:11)
Demikianlah aqidah Imam asy-Syafi’i. Semoga Allah merahmati beliau. Amin…







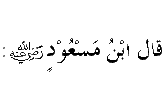

0 tanggapan:
Posting Komentar