Sepekan ini, banyak orang membicarakan tentang peirstiwa teror yang terjadi di Paris, Perancis.
Beberapa
orang bersenjata menyerang kantor sebuah surat kabar yang dikenal suka
membuat karikatur provokatif dan mengejek banyak kalangan, termasuk
mengejek Islam dan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam. Serangan itu menewaskan 12 orang, termasuk redaktur surat kabar tersebut dan dua kartunis.
Sebenarnya
penulis tidak terlalu suka menghabiskan waktu untuk membahas urusan
seperti ini. Prinsip aqidah kita sangat jelas; bahwa siapa yang mencaci
Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam, maka tidak ada yang
layak baginya kecuali hukuman mati. Tapi tentu saja menindak sebuah
tindak kejahatan haruslah dengan aturan yang benar, baik secara syar’i
maupun dalam hukum pidana di negara manapun. Di zaman kelemahan seperti
ini tidak banyak yang bisa dilakukan, tapi paling tidak, komitmennya
seorang muslim terhadap aturan-aturan Syari’at dan selalu mendahulukan
hukum Allah diatas sikap kebencian dan kemarahan adalah sebuah
“kemenangan” ketika banyak kalangan dari umat ini tidak memahami
agamanya, atau punya pemahaman namun tidak mampu mengamalkannya secara
benar.
Tulisan
kecil ini kami buat semata-mata karena kesedihan kami atas kelakuan
sebagian orang yang tiba-tiba menjadi “mufti” di media sosial dengan
“membajak” perkataan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah rahimahullahu dalam kitabnya “ash-Shârim al-Maslûl ‘alâ Syâtim ar- Rasûl”.
Padahal kami yakin, orang yang mengutip perkataan itu pun tidak pernah
membaca buku tersebut dan hanya “copas” sana sini tanpa memahami
persoalan dari pembahasan yang sebenarnya.
Benar bahwa Syaikhul Islam, dan para ulama kaum muslimin, berfatwa tentang halalnya darah orang yang mencaci Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam,
baik dia seorang musllim atau kafir. Jika dia seorang muslim, maka dia
murtad dengan perbuatan tersebut dan berhak dihukum mati. Dengan sedikit
perbedaan di kalangan ulama tentang orang yang sempat bertaubat dari
perbuatannya itu. Syaikhul Islam cenderung kepada pendapat yang
mengatakan bahwa si pelaku tetap dihukum mati karena cacian tersebut
walaupun dia telah bertaubat dari perbuatannya.
Pembahasan
ini tentu saja membutuhkan pembahasan yang lebih dari apa yang kami
sebutkan. Tapi tulisan kami bukan untuk membahas masalah tersebut. Kami
hanya ingin “meluruskan” kekeliruan sebagian orang yang membenarkan
tindakan pembunuhan yang dilakukan oleh para pelaku teror di Paris.
Seakan-akan tindakan itu sudah sesuai dengan aturan Syari’at, dan
parahnya mereka menukilkan pendalilan yang disebutkan Syaikhul Islam
dalam kasus pembunuhan Ka’ab bin al-Asyraf dan kisah seorang shahabat
yang membunuh budaknya karena mencaci Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam dan kisah-kisah yang semacamnya.
Kisah pembunuhan Ka’ab bin al-Asyraf disebutkan dalam hadits shahih yang diriwayatkan al-Bukhary dan Muslim[1]. Dalam kisah itu, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam
meminta dari para shahabat siapa diantara mereka yang sanggup membunuh
Ka’ab. Permintaan itu disanggupi Muhammad bin Maslamah dan beberapa
orang lainnya. Ringkasnya, Muhammad bin Maslamah dan kawan-kawannya
akhirnya bisa membunuh Ka’ab setelah mereka menampakkan padanya jaminan
keamanan.
Kisah ini
tidak cocok untuk diterapkan pada kasus penghinaan yang terjadi di
Paris. Kisah pembunuhan Ka’ab terjadi dalam lingkup wewenang Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam
sebagai pemimpin Madinah dan juga orang-orang Yahudi Madinah sesuai
dengan konsekuensi perjanjian damai antara kaum muslimin dengan Yahudi
di Madinah. Ka’ab berada dalam jaminan keamanan sesuai dengan
konsekuensi perjanjian damai (al-‘ahd) dan jaminan tersebut gugur karena dia telah menghina dan mencaci Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam.
Dan lagi pula, peristiwa itu tidak berpengaruh buruk bagi Islam dan
kaum muslimin, berbeda dengan peristiwa yang terjadi di Paris dan banyak
kasus lainnya di zaman modern ini.
Dalil
lainnya yang dijadikan argumen pembenaran tindakan teror tersebut adalah
kisah seorang buta yang membunuh budak perempuannya karena budak itu
untuk kedua kalinya mencaci Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam.
Hadits ini shahih, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dalam as-Sunan.[2]
Yang
nampak, wanita tersebut adalah seorang yang kafir. Karena seorang muslim
tidak akan mungkin berani melakukannya. Andai pun dia seorang muslimah,
dia murtad dengan perbuatannya tersebut dan tuannya tidak berhak untuk
tetap melindunginya dari hukuman.
Orang-orang
yang berdalil dengan hadits ini menyebutkannya begitu saja tanpa ada
penjelasan tambahan sehingga seakan-akan Syaikhul Islam membenarkan
perbuatan shahabat itu secara mutlak.
Tapi, marilah kita menyimak penjelasan ini :
Setelah
menyebutkan persoalan itu, Syaikhul Islam berkata, “Tetap dikatakan :
Hukuman had tidak dilaksanakan kecuali oleh imam (penguasa) atau
wakilnya.”[3]
Kemudian bagaimana bisa shahabat itu bertindak sendiri tanpa izin Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam kemudian beliau akhirnya membenarkan tindakannya tersebut? Beliau menjelaskan kemungkinannya dari beberapa sisi, diantaranya;
- Seorang
tuan boleh melaksanakan hukuman had terhadap budaknya seperti had zina
atau meminum minuman keras. Ulama berselisih tentang boleh tidaknya
hukuman dalam bentuk membunuh atau memotong anggota tubuh bagi tuan
terhadap budaknya. Dalil-dalil shahih menguatkan pendapat yang
membolehkannya.
- Paling
banter perbuatan shahabat itu adalah bentuk penyelisihan terhadap imam
(penguasa), dan imam boleh memaafkannya atas perbuatannya yang
melangkahi wewenang imam.
- Jika perbuatan ini disebut sebagai hukuman had, maka ini adalah pembunuhan terhadap kafir harbi yang boleh dilakukan siapapun.
- Perbuatan ini seperti ini pernah terjadi di masa Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam, seperti kisah Umar yang membunuh seorang munafik tanpa izin Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam karena ia tidak ridha dengan hukum beliau, kemudian turunlah ayat yang membenarkan hal itu.
Apa maknanya penjelasan beliau tersebut?
Syaikhul
Islam tidak pernah membolehkan perbuatan itu secara mutlak! Beliau tetap
berpegang dengan hukum asal bahwa tidak ada yang berwenang menindak
orang-orang yang berada dalam jaminan keamanan tersebut kecuali imam
atau wakilnya.
Kalau
perbuatan itu boleh dilakukan secara mutlak sebagaimana pendalilan yang
mereka gunakan dalam kasus teror di Paris, niscaya Syaikhul Islam tidak
akan memberi uzur kepada shahabat buta yang membunuh budaknya itu dan
akan mengatakan perbuatan itu boleh tanpa harus menyebutkan permasalahan
dan bantahannya.
Syaikhul
Islam seorang ulama yang paling mengetahui tentang perselisihan ulama,
dan beliau tidak menukil dalam masalah ini pendapat yang membolehkannya
secara mutlak dari seorang pun mereka. Yang seperti ini sudah cukup
memberi penjelasan bahwa urusan besar seperti ini adalah wewenang
penguasa, bukan hak individu-individu tertentu dari kaum muslimin.
Hal ini
dengan catatan penting yang wajib dipahami, bahwa kasus pembunuhan itu
terjadi dalam wilayah negara Islam yang berdaulat, dalam wewenang
penguasa muslim.
Adapun orang-orang kafir Quraisy yang mencaci Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam di luar Madinah, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam
tidak pernah mengutus satu orang pun untuk mengeksekusi mereka di
negeri mereka, baik itu dalam masa perang apalagi setelah terjalinnya
kesepakatan damai di Hudaibiyah.
Demikian
juga tidak ada seorang pun dari para shahabat yang melakukan perbuatan
teror seperti itu di negeri-negeri yang tidak dikuasai oleh kaum muslimin.
Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam
memerintahkan shahabat-shahabatnya untuk menghukum orang-orang yang
menghina dan mencaci pribadi beliau sebagai seorang rasul ketika beliau
menduduki Makkah pada peristiwa Penaklukan Makkah di bulan Ramadhan
tahun 8 H.
Itu semua terjadi ketika kaum muslimin memiliki kekuatan dan memiliki negara berdaulat yang diisegani oleh musuh-musuhnya.
Orang-orang yang melakukan teror di Paris, atas nama siapa mereka bertindak di zaman kelemahan dan kekalahan seperti ini?
Kalau
mereka melakukannya karena kemarahan dan kebencian, maka jangan pernah
mengatasnamakan Islam, karena Islam tidak pernah mengajarkannya.
Mungkin
akan ada yang mengatakan bahwa Perancis sejak dulu dikenal dengan
kebebasan persnya yang suka menghina Islam dan Rasul Islam. Dan dalam
aksi solidaritas oleh para pemimpin dunia dan puluhan ribu orang di
Paris setelah kejadian tersebut, hadir pula Perdana Menteri Israel yang
telah membantai saudara-saudara muslim kita di Palestina. Ini
menunjukkan standar ganda Barat yang begitu peduli dengan kematian 12
orang (total yang terbunuh hingga akhir peristiwa adalah 17 orang, 12
orang tersebut tewas dalam penyerangan di surat kabar Charlie Hebdo), tapi menutup mata terhadap kebrutalan Israel!
Kami
katakan, itulah Barat dan para pemimpin kafir… Semua tahu watak mereka…
Setelah itu apa? Apakah dengan dalih itu kemudian kita boleh
mencampakkan ajaran Islam yang hak atas nama kemarahan dan dendam?
Kami
menuliskan ini bukan untuk membela orang-orang kafir. Tulisan ini
semata-mata hanya ingin mengajak Anda untuk berpikir jernih; sejauh mana
komitmen kita terhadap agama kita?
Kita
berjuang memperjuangkan agama ini bukan semata-mata untuk balas dendam
atau marah-marah. Kita ingin memperjuangkan nilai. Kalau orang-orang
kafir itu berlaku zalim dan tidak adil terhadap Islam dan umatnya,
setidaknya kita semua paham bahwa Islam tidak pernah mengajarkan bahwa
kejahatan harus dibalas dengan kejahatan yang sama.
Marilah
kita kembali mengkaji agama Allah ini dengan bimbingan para ulama
Sunnah, tanpa dikotori oleh pendapat akal atau sikap emosional. Sangat
berbahaya seseorang ketika berani mengutip perkataan seorang ulama,
apalagi perkataan Allah dan rasulNya, sementara mereka tidak memaksudkan
seperti apa yang kita inginkan dan pahami dari kutipan tersebut.
Semoga Allah memaafkan kita dan membalas orang-orang kafir dengan balasan yang setimpal. Amin.
(oleh : Ust. Taufiq Rahman, LC)
—————————
Footnotes :
[1] Shahîh al-Bukhâry (no. 2510) dan Shahîh Muslim (Kitâb al Jihâd wa as Sair)
[2] Sunan Abî Dâwûd (no. 4361), dishahihkan al-Albani dalam Shahîh Sunan Abî Dâwûd
[3] Silahkan rujuk ke ash-Shârim al-Maslûl hal. 285-286







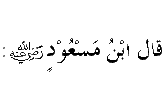

0 tanggapan:
Posting Komentar