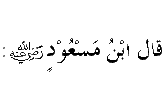29 November 2015
Pembicaraan Seorang Wanita dengan Lelaki yang Bukan Mahram
Apa hukumnya pembicaraan seorang wanita dengan pemilik toko pakaian atau
penjahit? Kami berharap kata-kata nasehat yang baik untuk kaum wanita.
Jawab :
Pembicaraan seorang wanita dengan pemilik
toko, yaitu pembicaraan yang sebatas hajat dan tidak ada fitnah padanya,
tidaklah mengapa. Sejak dahulu para wanita berbicara kepada kaum
laki-laki dalam berbagai keperluan dan urusan pada batasan-batasan yang
dibutuhkan.
Adapun jika pembicaraan itu disertai dengan tawa, candaan dan
suara-suara yang mengundang fitnah, maka hal itu haram, tidak boleh
dilakukan. Allah subhanahu wa ta’ala berfirman kepada istri-istri nabi-Nya shallallahu ‘alaihi wa aalihi wasallam, -radhiyallahu ‘anhunna,
وَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَع الَذِيْ فىْ قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوْفًا
“Maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara sehingga
berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya, dan ucapkanlah
perkataan yang baik.” (QS. Al-Ahzab ayat 32).
Makna “perkataan yang baik” adalah apa yang dianggap baik oleh
manusia dalam batasan keperluan. Adapun yang lebih dari itu, yaitu
dengan tertawa, bercanda, suara yang mengundang fitnah dan lain-lainnya,
atau dengan membuka wajahnya, menyingkap kedua lengan atau kedua
telapak tangannya; semua ini adalah perkara-perkara yang haram, mungkar
dan termasuk sebab-sebab yang membawa kepada fitnah, serta membawa
kepada jatuhnya (seseorang) kepada perbuatan keji (zina).
Wajib bagi seorang wanita muslimah yang takut kepada Allah ‘azza wa jalla untuk
bertakwa kepada Allah, dan jangan pernah berbicara kepada laki-laki
dengan ucapan yang membangkitkan keinginan (buruk) mereka terhadap
dirinya, yang menjadikan fitnah bagi hati-hati mereka, serta (wajib)
menjauhi perkara ini. Jika dia memiliki keperluan untuk pergi ke toko
atau suatu tempat yang padanya ada laki-laki, maka hendaknya dia
berhijab, menutup diri dan beradab dengan adab-adab Islam. Jika dia
berbicara kepada laki-laki, maka berbicaralah dengan pembicaraan yang
baik yang tidak ada padanya fitnah dan keraguan.
(Syaikh Shalih bin Fauzan bin Abdullah al-Fauzan, hafidzhahullahu)
—————————
Sumber : Al-Muntaqa min Fatawa asy-Syaikh Shalih bin Fauzan, III/156-157
25 November 2015
Atas Nama “Mashlahat Dakwah”
Diantara
tipuan syaitan terhadap sebagian aktivis dakwah adalah pelegalan hal-hal
yang menyimpang dari prinsip dasar keyakinan agama mereka atas nama
mashlahat dan kepentingan dakwah!
Atas nama
mashlahat dakwah, gambar dan foto tokoh yang dibanggakan dalam suatu
jama’ah boleh dipajang dengan berbagai macam gaya dan bentuknya. Padahal
banyak para ustadznya dan kader dakwah sejatinya yang masih menganggap
tabu persoalan foto, tapi anehnya sepertinya tidak ada masalah jika
berkait dengan kepentingan pencitraan lembaga dan tokohnya.
Atas nama
kepentingan dakwah, dibenarkan berkawan dan bermesraan dengan siapa saja
selama dia masih muslim tanpa peduli bagaimana prinsip dasar aqidah dan
manhajnya.
Atas nama
dakwah, para aktivis wanitanya diharuskan keluar rumah untuk ikut andil
dalam memperjuangkan “dakwah” (baca : jamaah/lembaga/organisasi)
walaupun itu harus mengorbankan rumahnya[1]. Kami tidak berbicara
tentang wanita yang keluar untuk belajar dan menuntut ilmu syar’i dalam
batas-batas yang diperlukan dan tidak menyita waktu dan tenaganya. Yang
kami bicarakan adalah eksploitasi para akhawat untuk bekerja
mati-matian demi kepentingan rekrutmen kader untuk mencapai jumlah
tertentu demi kebanggaan dan ketenaran!
Atas nama
kemashlahatan dakwah, majelis ilmu tidak lagi dianggap penting dan
efektif kalau tidak bisa mengumpulkan banyak massa yang akan direkrut
menjadi kadernya.
Atas nama
kepentingan dakwah pula kualitas kader tidak lagi menjadi perhatian
penting karena semuanya diharuskan sibuk untuk memperbanyak jumlah.
Atas nama
dakwah, ketulusan dalam berjuang harus ternoda oleh semangat untuk
pencitraan lembaga dan para ustadznya agar dikenal di kalangan
masyarakat. Lagi-lagi untuk sebuah kepentingan.
Atas nama
kepentingan dakwah, para kader diarahkan untuk bepartisipasi dalam
pemilihan kepala daerah dengan mendukung calon tertentu. Tidak ada yang
salah jika tujuannya memang benar untuk kemashlahatan Islam dan kaum
muslimin. Tapi kalau dukungan itu dengan imbalan pemberian “bantuan
materi” si calon?! Kami jadi ragu, jangan-jangan dukungan itu hanya
untuk mashlahat jamaah si pendukung calon tersebut.
Agama ini adalah agama rabbânî
yang Allah telah menjadikan tujuannya adalah sebaik-baik tujuan. Dan
Dia menjadikan sarana untuk mewujudkan tujuan tersebut sebagai sarana
yang mulia dan terhormat.
Allah tidak akan mungkin menjadikan kemenangan dakwah ini tegak diatas manhaj yang bukan berasal dari manhaj dakwah Nabi ﷺ.
Penggunaan wasilah dan sarana apa saja yang menyelisihi manhaj rabbânî
yang telah digariskan oleh Rasulullah ﷺ dalam dakwah beliau adalah
bentuk penyimpangan dari jalan kebenaran dan pelecehan terhadapnya.
Bahkan, walaupun sebagian wasilah itu bisa mendatangkan sedikit manfaat
menarik dalam pandangan para pengikut dakwah tersebut.
Para ulama
kita dahulu telah menetapkan sebuah kaedah penting, bahwa “akhir umat
ini tidak akan pernah baik kecuali dengan perkara yang telah menjadikan
baik generasi awalnya”.
Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani rahimahullahu ditanya, “Apakah wajib mendapatkan sebagian mashlahat, baik yang bersifat wajib kifa’i atau ‘aini, jika jalan menuju kepada mashlahat tersebut terdapat perkara-perkara yang menyimpang dan diharamkan?”
Beliau rahimahullahu menjawab,
“Tidak boleh! Karena tidak ada dalam Islam kaedah yang mengatakan ‘tujuan membolehkan segala cara’.
Bahkan Islam telah menyebutkan lebih dari satu dalil dalam Kitab-Nya
dan sunnah nabiNya – ﷺ – bahwa rezki yang telah Allah tetapkan untuk
seseorang, tidak boleh seorang muslim mencari jalan untuk mendapatkannya
dengan jalan yang diharamkan. Sebagaimana disebutkan dalam hadits
(riwayat) al-Hakim dan lainnya dari sabda Nabi ﷺ,
إِنَّ مَا عِنْدَ الله لَا يُنَالُ بِالحَرَامِ
‘Apa yang berada di sisi Allah tidak boleh didapatkan dengan cara yang haram.’
Rezki yang
berasal dari Allah, yang dia itu tidak seperti kedudukan shalat dan
yang semacamnya dari kewajiban-kewajiban yang fardhu ‘ain, rezki itu
diusahakan seorang muslim semata-mata untuk memelihara dirinya dari
meminta-minta kepada manusia. Andai ia mencukupkan diri dengan rezki
yang halal dan tidak berusaha yang selain itu, ia tidak dianggap sebagai
orang yang lalai, karena mencari rezki sebagaimana yang kami sebutkan
semata-mata agar seorang manusia bisa menjaga dirinya dari meminta-minta
kepada manusia.
Jika saja
usaha untuk mendapatkan rezki itu tidak boleh dengan cara yang haram
dengan dalil hadits yang sudah dikenal, yaitu sabdanya, ‘Apa yang di sisi Allah tidak boleh diusahakan dengan cara yang haram’;
maka lebih pantas lagi, dan lebih layak lagi bahwasannya tidak
dibolehkan seorang muslim, bahkan seluruh muslim, dan bahkan sebuah
jamaah Islam, yang ingin mendakwahi manusia untuk mengamalkan Kitab
Allah dan sunnah Rasulullah ﷺ; sangat layak bagi mereka untuk tidak
menghalalkan sebagian perkara yang diharamkan untuk mewujudkan sebagian
dari tujuan-tujuan mereka. Karena hal itu kebalikan dari firman Allah tabâraka wa ta’âlâ seperti,
وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ
‘Barangsiapa
yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan
keluar, dan memberinya rezki dari arah yang tiada disangka-sangkanya.’ (QS. Ath-Thalaq ayat 2 & 3).
Itu dari satu sisi.
Di sisi lain, kita berbeda dari seluruh jamaah-jamaah dan kelompok-kelompok. Kita bukanlah kelompok (hizb),
dan kita bukanlah koalisi (gabungan beberapa kelompok)… Kita adalah
kaum muslimin, dan kita berusaha untuk berjalan dalam Islam kita ini di
atas manhaj para Salafush shalih kita, radhiyallâhu ‘anhum ‘ajma’în.
Setiap
kita mengetahui dengan pasti bahwa mereka suatu waktu dahulu tidak
pernah terlintas dalam benak mereka, apalagi untuk mewujudkan itu dalam
kehidupan mereka, bahwa mereka akan menghalalkan sebagian perkara haram
demi untuk mewujudkan sebagian tujuan-tujuan islami… Bagaimana bisa (itu
dilegalkan)?! Sementara ayat tadi mengatakan,
وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ
‘Barangsiapa
yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan
keluar, dan memberinya rezki dari arah yang tiada disangka-sangkanya.’ (QS. Ath-Thalaq ayat 2 & 3).
Lisan
orang yang mengucapkan bolehnya melakukan sebagian pelanggaran untuk
mewujudkan sebagian tujuan-tujuan syar’i; ucapan mereka itu bertolak
belakang dengan ayat tersebut. Yaitu ucapan mereka bahwa ‘siapa yang
bertakwa kepada Allah di masa kini, yang ingin menerapkan hukum-hukum
Allah seluruhnya, maka dakwahnya akan sangat terbatas dan sempit.
Karenanya telah menjadi keharusan untuk melanggar sebagian perkara yang
tidak diizinkan Rasul sehingga kita bisa melebarkan dakwah ini!’
Saya
katakan, di sana ada peringatan yang mengingatkan tentang adanya
keburukan yang berbahaya jika para pengemban dakwah kebenaran tidak
memperbaiki urusan mereka sebelum dia menjadi semakin runyam. Yaitu kami
mendengar dari waktu ke waktu bahwa mereka selalu saja melakukan
pelanggaran-pelanggaran yang banyak dalam jalan yang mereka sebut
sebagai penyebaran dakwah!”[2]
Penggunaan
istilah “mashlahat dakwah” pada saat ini dalam banyak kasus adalah
pemutar balikan fakta untuk kepentingan tertentu dari orang-orang yang
menggunakannya. Seorang da’i dalam pergerakan Islam besar di abad ini
pernah memperingatkan bahaya dari penggunaan istilah tersebut. Beliau
berkata, semoga Allah mengampuni dan merahmatinya, “(Ungkapan) mashlahat
dakwah telah berubah menjadi berhala yang dipuja oleh para pengikut
dakwah dan mereka mulai melupakan manhaj dakwah yang prinsip. Wajib bagi
para pengikut dakwah untuk istiqamah diatas jalan dakwah tersebut dan
benar-benar teliti menempuh jalan itu, tanpa harus menoleh kepada
hasil-hasil yang terkadang mengganggu pikiran mereka bahwa padanya ada
bahaya yang akan mengancam dakwah dan para pengikutnya… Satu-satunya
bahaya yang wajib mereka khawatirkan adalah bahaya penyimpangan dari
manhaj dikarenakan oleh salah satu dari sebab-sebab, baik penyimpangan
itu banyak atau sedikit. Allah lebih tahu dari mereka persoalan
mashlahat dan mereka tidak dibebankan untuk hal itu. Mereka hanya
dibebankan satu perkara, yaitu jangan sekali-kali menyimpang dari
manhaj, jangan sekali-kali melenceng dari jalan ini!”[3]
Kami tidak
pernah mengingkari istilah mashlahat dakwah. Yang kami ingkari adalah
penggunaan istilah itu untuk kepentingan yang selain kepentingan Islam
dan kaum muslimin. Tidak boleh memanfaatkan istilah “mashlahat dakwah”
untuk kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok yang sempit.
Sehingga digambarkan kepada para pengikutnya bahwa kepentingan pribadi
dan kelompoknya itulah dia mashlahat dan kepentingan dakwah atau
sebaliknya. Sebagaimana juga tidak boleh menghalalkan segala cara untuk
mencapai tujuan-tujuan dakwah yang mulia.
Kita
telah berkomitmen terhadap diri-diri kita bahwa kita tidak akan
melakukan perkara yang diharamkan, tidak akan meninggalkan apa yang
diwajibkan, dan tidak akan melakukan bid’ah demi untuk mashlahat dakwah!
Karena Allah subhanahu wa ta’ala telah memerintahkan kita untuk istiqamah![4]
Allah Ta’ala berfirman,
فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ
“Maka tetaplah pada jalan yang lurus menuju kepadaNya dan mohonlah ampun kepadaNya.” (QS. Fushshilat ayat 6).
Dan Dia berfirman mengajak kepada sikap istiqamah,
إِنَّ
الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ
عَلَيْهِمُ الْمَلائِكَةُ أَلاَّ تَخَافُوا وَلا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا
بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ، نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي
الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي
أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، نُزُلا مِّنْ غَفُورٍ
رَّحِيمٍ
“Sesungguhnya
orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah dan mereka
meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka
(dengan mengatakan), ‘Janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu
bersedih, dan bergembiralah kamu dengan (memperoleh) surga yang telah
dijanjikan Allah kepadamu’. Kamilah pelindung-pelindungmu dalam
kehidupan dunia dan di akhirat; di dalamnya kamu memperoleh apa yang
kamu inginkan dan memperoleh (pula) di dalamnya apa yang kamu minta.
Sebagai hidangan (bagimu) dari Tuhan Yang Maha Pengampun lagi Maha
Penyayang.” (QS. Fushshilat ayat 30-32).
—————————
Footnotes :
[1]
Para ulama membolehkan seorang wanita yang memilliki kapasitas ilmu
syar’i untuk keluar rumah berdakwah di kalangan wanita, mengajarkan
mereka urusan agamanya. Tapi dengan syarat hal itu dilakukan dengan izin
suami dan tidak mengabaikan urusan rumah, suami dan anak-anak. Anehnya
di zaman ini, seorang muslimah baru saja mengenal Islam, dan waktu,
tenaga dan pikirannya dieksploitasi habis-habisan untuk mengurus dan
memperjuangkan kepentingan lembaga yang mereka sebut “dakwah”!!
[2] Rekaman no. 401 dari Silsilah al-Hudâ wa an-Nûr
[3] Afrâh ar-Rûh, Sayyid Quthb rahimahullahu
[4] Al-Makhraj min al-Fitnah, Syaikh Muqbil bin Hadi al-Wadi’i rahimahullahu
21 November 2015
Haram Menyentuh Tubuh Wanita dalam Ruqyah
Diantara
fenomena umum yang mulai nampak dalam metode pengobatan ruqyah adalah
ketika si peruqyah menyentuh pasien wanitanya dengan dalih untuk
mengusir jin. Perbuatan seperti ini haram karena wanita adalah aurat dan
melihat aurat diharamkan dalam Islam, dan lebih diharamkan lagi jika
sampai menyentuh aurat tersebut.
Dan hukum itu berlaku umum baik si peruqyah menyentuhnya dengan kaos tangan atau tanpanya.
Para ulama
di Al-Lajnah ad-Dâimah li al-Buhûts al-‘Ilmiyyah wa al-Iftâ’ (Lembaga
Riset Ilmiah dan Fatwa Kerajaan Arab Saudi) ditanya tentang hukum
menyentuh badan wanita, baik tangannya, dahinya atau lehernya secara
langsung tanpa alas, dengan dalih untuk menekan dan mempersempit jin
yang ada padanya, terutama bahwa sentuhan yang seperti itu juga terjadi
dari para dokter di rumah sakit?
Mereka
menjawab, “Tidak boleh bagi peruqyah menyentuh sesuatu pun dari badan
wanita yang diruqyahnya, karena itu akan mendatangkan fitnah. Dia cukup
membaca tanpa harus menyentuh. Terdapat perbedaan antara pekerjaan
peruqyah dengan dokter. Karena dokter terkadang tidak memungkinkan
baginya melakukan tindakan medis kecuali dengan memegang tempat yang
akan diobati. Ini berbeda dengan seorang peruqyah karena yang dia
lakukan –yaitu membaca dan meniup- tidak mengharuskan adanya sentuhan.”
(Fatawa al-Lajnah ad-Daimah, I/90-91).
Berkata
Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin rahimahullahu, “Saya ingatkan
saudara-saudara saya yang meruqyah dengan bacaan dari perbuatan
meletakkan tangan-tangan mereka di badan wanita, baik secara langsung
atau dengan menggunakan alas. Jika Allah menghendaki kebaikan dari
bacaan mereka, maka itu akan terjadi tanpa harus memegang.” (Fatâwâ Nûr
‘ala ad-Darb, II/22, asy-Syamilah).
Maka
selayaknya seorang peruqyah bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar
takwa dengan menjaga komitmennya terhadap perintah-perintah Allah dan
larangan-laranganNya. Waspadalah terhadap makar syaitan untuk
menjerumuskan manusia kepada fitnah dengan berbagai macam cara. Bahkan
dari jalan yang dianggap baik dalam pandangan seorang manusia, tapi
dengannya ia terjerumus kepada fitnah dalam agama dan dunianya. Jangan
sampai pengobatan syar’i itu terkotori oleh perkara-perkara mungkar yang
diharamkan Allah dengan menyingkap aurat dan menyentuh apa yang Dia
larang dan haramkan.
Wa billâhi at-taufîq.
16 November 2015
Pembunuhan dan Peledakan di Negeri-negeri Kafir
Pertanyaan untuk Syaikh Shalih bin Fauzan al-Fauzan hafidzhahullahu :
Semoga
Allah melimpahkan kebaikan kepada Anda. Apakah pembunuhan dan aksi
peledakan pada fasilitas pemerintah di negara-negara kafir adalah sebuah
keharusan dan termasuk jihad?
Beliau menjawab :
Pembunuhan
dan perusakan adalah tindakan yang tidak dibolehkan, karena itu akan
mendatangkan keburukan bagi kaum muslimin, pembunuhan dan pengusiran.
Rasul ﷺ ketika beliau di Makkah sebelum hijrah, beliau diperintahkan untuk menahan diri.
أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّواْ أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ وَآتُواْ الزَّكَاةَ
“Tidakkah
kamu perhatikan orang-orang yang dikatakan kepada mereka : Tahanlah
tanganmu (dari berperang), dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat.” (QS. An-Nisa’ ayat 77).
Beliau
diperintahkan menahan diri untuk tidak memerangi orang-orang kafir
karena beliau belum memiliki kemampuan untuk memerangi mereka.
Kalau
seandainya mereka (kaum muslimin) membunuh seorang kafir, niscaya
orang-orang kafir akan memerangi mereka sampai tidak tersisa seorang
pun, menghabisi mereka hingga tidak tersisa seorang pun. Karena orang
kafir lebih kuat dari kaum muslimin dan kaum muslimin berada dalam
kekuasaan mereka. Pembunuhan orang kafir akan berakibat pada pembunuhan
orang-orang muslim yang hidup di negeri tersebut, sebagaimana yang
kalian saksikan dan dengarkan sekarang. Yang seperti ini bukanlah bagian
dari dakwah, dan bukan pula termasuk jihad fi sabilillah.
Demikian
pula perusakan dan peledakan, itu hanya akan membawa keburukan kepada
kaum muslimin sebagaimana yang telah terjadi. Dan ketika Rasul ﷺ telah
berhijrah, dan beliau memiliki tentara dan orang-orang yang membelanya,
maka saat itulah beliau diperintahkan berjihad terhadap orang-orang
kafir.
Apakah
Rasul ﷺ dan para shahabat ketika mereka dahulu berada di Makkah, apakah
mereka melakukan tindakan-tindakan teror itu? Sekali-kali tidak! Bahkan
mereka dilarang melakukannya.
Apakah
mereka menghancurkan harta benda milik orang-orang kafir ketika mereka
berada di Makkah? Sekali-kali tidak! Mereka dilarang melakukannya, dan
hanya diperintahkan untuk berdakwah dan menyampaikan.
Adapun peperangan, itu hanya terjadi di Madinah ketika Islam telah memiliki sebuah negara.”
(Fatâwâ al A-immah fî an Nawâzil al Mudalhamah, hal. 41-42)
08 November 2015
Mihrab Masjid dalam Pandangan Ulama Salaf
Sangat umum di kalangan kaum muslimin,
ketika membangun masjid, maka mereka akan membuatkan cekungan di bagian
depan masjid, atau ruangan khusus sebagai tempat berdiri imam yang
disebut mihrab. Mereka mengira bahwa apa yang mereka lakukan itu sesuai
dengan apa yang dimaksudkan ayat,
فَخَرَجَ عَلىَ قَوْمِهِ مِنَ المِحْرَابِ
“Maka ia keluar dari mihrab menuju kaumnya.” (QS. Maryam ayat 11).
Pandangan seperti ini adalah pandangan yang keliru. Karena mihrab
dalam bahasa Arab bermakna tempat shalat. Sedangkan dinding yang
melengkung atau menjorok ke depan di bagian kiblat masjid tidak disebut
sebagai mihrab. Ini adalah perkara baru yang terjadi di kaum muslimin
dengan meniru kebiasaan dan tradisi orang-orang di luar mereka dari kalangan Ahli Kitab.
Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu berkata, “Masjid Rasulullah ﷺ tidak memiliki mihrab.”[1]
Manshur bin al-Mu’tamir mengatakan bahwa Ibrahim an-Nakha’i membenci shalat di tempat yang cekung (yang dikhususkan) untuk imam.[2]
Sufyan ats-Tsauri rahimahullahu mengatakan, “Kami tidak menyukainya.”[3]
Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu mengatakan,
“Makruh hukumnya bersujud dalam mihrab karena itu menyerupai apa yang
dilakukan Ahlul Kitab. Mereka mengkhususkan tempat untuk imamnya.”[4]
Al-Qârry berkata, “Mihrab adalah perkara baru setelah (masa) Rasulullah ﷺ. Karenanya, para as-Salaf ash-Shalih tidak menyukai membuat mihrab.”[5]
Dengan penjelasan ini, alangkah baiknya
jika kaum muslimin tidak lagi membiasakan membuat mihrab di
masjid-masjid yang mereka bangun. Kalau mihrab itu sudah terlanjur ada, maka
sebaiknya tidak digunakan untuk shalat. Imam bisa shalat dengan posisi
yang agak mundur di luar mihrab dan tidak berada dalam mihrab tersebut.
Kami juga mengingatkan para pemuda yang
bersemangat ingin mengamalkan sunnah, hendaknya mereka bijak menyikapi
fenomena seperti ini dan jangan membuat polemik baru di masyarakat.
Hukum mihrab ini makruh dan tidak sampai pada keharaman. Para Salaf
telah melihat mihrab di masjid-masjid mereka dan tidak pernah dinukil
bahwa mereka memerintahkan untuk menghancurkan mihrab tersebut. Mereka
tetap shalat di masjid itu atau memimpin shalat, tetapi tanpa
menggunakan mihrabnya. Demikianlah yang disebutkan dari perbuatan Imam
al-Hasan al-Bashri rahimahullahu.
Wallahu a'lam.
(Sumber : Tis’ûn Khatha’an fî al Masâjid, Syaikh Wahid bin Abdissalam Bali)
----------------------
Footnotes :
[1] Fathul Bâry, syarah hadits no. 497
[2] Mushannaf Abdirrazzâq (II/413)
[3] Mushannaf Abdirrazzâq (II/413)
[4] Iqtidhâ’ ash Shirât al Mustaqîm (I/351)
[5] ‘Aun al Ma’bûd, syarah hadits no. 485
[2] Mushannaf Abdirrazzâq (II/413)
[3] Mushannaf Abdirrazzâq (II/413)
[4] Iqtidhâ’ ash Shirât al Mustaqîm (I/351)
[5] ‘Aun al Ma’bûd, syarah hadits no. 485
05 November 2015
Menghadiahkan Bacaan Quran untuk Mayit
Para ulama berbeda pendapat dalam persoalan menghadiahkan pahala bacaan Al-Quran kepada orang yang sudah meninggal, apakah
sampai pahalanya atau tidak?
Pendapat yang terpilih dari dua pendapat
ulama, bahwa “hadiah” bacaan tersebut tidaklah sampai kepada si mayit.
Dalilnya adalah firman Allah Ta’ala,
وَأَنْ لَيْسَ لِلإِنْسَانِ إِلا مَا سَعَى
“Dan tidak ada (pahala) bagi manusia kecuali apa yang diusahakannya.” (QS. An-Najm: 39).
Juga berdasarkan sabda Nabi ﷺ ,
إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية وعلم ينتفع به وولد صالح يدعو له
“Jika seorang anak Adam meninggal,
maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara; shadaqah jariyah, ilmu
yang bermanfaat atau anak saleh yang mendoakannya.” (HR. Muslim).
Imam Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah berkata dalam tafsirnya mengenai firman Allah dalam surat An-Najm ayat 39, “Berdasarkan ayat ini, Imam Syafi’i dan pengikutnya mengambil
kesimpulan hukum bahwa bacaan (Al-Qur’an) tidak sampai jika pahalanya
dihadiahkan kepada mayit, karena itu bukan amal dan jerih payahnya. Oleh
karenanya, Rasulullah ﷺ tidak
menganjurkan dan tidak mengajak umatnya untuk itu dan tidak pula memberi
petunjuk baik secara jelas atau isyarat. Tidak pula hal itu dinukil
dari seorang pun dari para shahabat radhiyallahu 'anhum. Jika hal
itu suatu kebaikan, pasti mereka akan mendahului kita (dalam perkara itu). Dalam masalah ibadah, hendaknya membatasi dengan perkara yang
telah dikhususkan oleh dalil, tidak diperkenankan mengalihkannya dengan
berbagai macam qiyas dan logika. Adapun doa dan shadaqah, hal itu telah
disepakati sampainya pahalanya (kepada mayat) karena dengan tegas dinyatakan dalam
syariat.” (Tafsir Ibnu Katsir, IV/258).
Syaikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu
pernah ditanya tentang menghadiahkan bacaan Al-Qur’an dan shadaqah
untuk ibu, baik (beliau dalam kondisi) hidup atau mati? Beliau menjawab:
“Kalau bacaan Al-Qur’an, para ulama
berbeda pendapat, apakah pahala sampai kepada mayit? Para ulama berbeda
dalam dua pendapat. Yang terkuat adalah (pahala itu) tidak sampai karena
tidak ada dalilnya. Dan karena Rasulullah ﷺ
tidak pernah melakukannya terhadap orang-orang yang telah wafat dari
kalangan umat Islam seperti puteri-puteri beliau yang telah wafat saat
beliau ﷺ masih hidup. Sepengetahuan kami, hal itu tidak pernah dilakukan para shahabat radhiyallahu ‘anhum.
Yang lebih utama bagi orang mukmin adalah meninggalkan hal itu dan
tidak membacanya untuk mayit maupun untuk yang masih hidup. Begitu juga
tidak melakukan shalat untuk mereka, dan juga amalan sunnah dengan
berpuasa untuk mereka. Karena semuanya itu tidak ada dalilnya.
Asal dari ibadah adalah tauqifi (hanya membatasi pada dalil) yang ada perintahnya dari Allah subhanahu wa ta’ala atau rasul-Nya ﷺ dalam syari’atnya. Sementara sedekah, hal itu bermanfaat bagi yang hidup maupun mati dengan kesepakatan (ijma’)
umat Islam. Begitu juga dengan doa, bermanfaat bagi yang hidup maupun
mati dengan kesepakatan umat Islam. Orang yang masih hidup, tidak
diragukan lagi bahwa sedekah dan doa bermanfaat baginya. Orang yang
berdoa sementara kedua orang tuanya masih hidup, keduanya bisa mengambil
manfaat dengan doanya tersebut, begitu juga dengan sedekah akan
bermanfaat ketika keduanya masih hidup.
Menunaikan haji untuknya kalau mereka
lemah karena sudah tua atau sakit yang tidak mungkin sembuh, juga
bermanfaat baginya. Karena telah ada ketetapan dari beliau ﷺ ,
bahwa seorang wanita bertanya, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah
telah mewajibkan haji, sementara ayahku sudah tua, tidak
mampu melakukan perjalanan. Apakah saya (boleh) menunaikan haji
untuknya?” Beliau ﷺ menjawab, “Tunaikanlah haji untuknya.”
Kemudian, ada juga orang lain yang
datang kepada Nabi ﷺ dan berkata, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya ayahku
sudah tua, tidak mampu menunaikan haji dan (naik) kendaraan. Apakah
(boleh) saya menunaikan haji dan umrah untuknya?” Beliau menjawab, “Tunaikan haji untuk ayahmu dan lakukanlah umrah.”
Ini adalah dalil bahwa menghajikan
mayit atau orang yang masih hidup tapi lemah karena usianya atau wanita
lemah karena sudah tua renta adalah boleh. Demikianlah, sedekah, doa,
haji atau umrah untuk mayit dan orang yang sudah tidak mampu, semuanya
ini bermanfaat baginya menurut pendapat seluruh ahli ilmu. Begitu juga
puasa untuk mayit, kalau dia mempunyai kewajiban puasa baik karena
nadzar, kaffarah atau puasa Ramadhan, berdasarkan keumuman
sabda beliau ﷺ , “Barangsiapa yang meninggal dunia dan mempunyai beban puasa, maka walinya yang (menggantikan) puasanya.” (hadits Muttafaq ‘alaih).
Begitu pula hadits-hadits lain yang
semakna. Akan tetapi barangsiapa yang terlambat puasa Ramadhan karena
alasan yang dibenarkan agama seperti sakit, bepergian kemudian meninggal
dunia sebelum ada kesempatan mengqadha’nya, maka tidak (perlu)
digantikan puasanya, juga tidak perlu memberikan makanan, karena dia memiliki
udzur yang syar’i.” (Majmu’ Fatawa Wa Maqalat Syaikh Ibn Baz, IV/348)
Demikianlah penjelasan dari sebagian ulama, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi ﷺ dan para shahabatnya, radhiyallahu ‘anhum.
Wallahu a'lam.
03 November 2015
Al-Qira’at
Al-Quran adalah wahyu yang diturunkan. Diterima oleh Rasulullah ﷺ dari Jibril, dari Rabb Yang Maha Mulia, Allah subhanahu wa ta'ala.
Al-Quran ini tidak diambil setelah beliau ﷺ kecuali dengan metode talaqqi (periwayatan secara langsung). Nabi ﷺ telah membacakan kepada para Shahabat yang mulia beberapa qira’ah (bacaan) yang berbeda-beda, yang beliau mengambilnya langsung dari Jibril 'alaihissalam. Qira’ah-qira’ah ini diambil dan diriwayatkan oleh manusia –setelah generasi Shahabat- secara turun temurun dari generasi ke generasi, hingga akhirnya terkumpul dan terbatas pada nama beberapa orang yang mereka adalah silsilah periwayatan yang bersambung dalam talaqqi dan penyampaiannya (al-adâ’). Sedikit pun mereka tidak memiliki wewenang dalam menambah sesuatu atau mengurangi, karena semua qira’ah ini turun dari sisi Allah Ta’ala.
Berikut adalah sedikit penjelasan tentang epuluh qira'ah yang diterima dan diakui tersebut :
Al-Quran ini tidak diambil setelah beliau ﷺ kecuali dengan metode talaqqi (periwayatan secara langsung). Nabi ﷺ telah membacakan kepada para Shahabat yang mulia beberapa qira’ah (bacaan) yang berbeda-beda, yang beliau mengambilnya langsung dari Jibril 'alaihissalam. Qira’ah-qira’ah ini diambil dan diriwayatkan oleh manusia –setelah generasi Shahabat- secara turun temurun dari generasi ke generasi, hingga akhirnya terkumpul dan terbatas pada nama beberapa orang yang mereka adalah silsilah periwayatan yang bersambung dalam talaqqi dan penyampaiannya (al-adâ’). Sedikit pun mereka tidak memiliki wewenang dalam menambah sesuatu atau mengurangi, karena semua qira’ah ini turun dari sisi Allah Ta’ala.
Para ulama telah menetapkan beberapa syarat bagi diterimanya suatu qira’ah dalam periwayatan, yaitu,
- Tulisannya (rasm) sesuai dengan rasm Mushaf Utsmani, yaitu mushaf yang ditulis oleh komite yang dibentuk oleh Khalifah Utsman radhiyallahu ‘anhu untuk menyalin kembali mushaf al-Quran
- Selaras dengan kaedah-kaedah bahasa Arab
- Sanad/jalan periwayatannya adalah mutawatir, diriwayatkan oleh jamaah yang berjumlah banyak, dari jamaah yang sepertinya, yang mustahil mereka akan bersepakat dalam kedustaan
Berikut adalah sedikit penjelasan tentang epuluh qira'ah yang diterima dan diakui tersebut :
Pertama :
Qira’ah yang disepakati bahwa riwayatnya kuat dan mutawatir.
Yang telah disepakati dalam masalah ini yaitu 7 qira’ah yang dikenal
sebagai al Qirâ-ât as Sab’. Ketujuh qira’ah tersebut adalah yang dinisbatkan kepada para imam berikut,
- Nafi', yaitu Nafi' bin Abdirrahman bin Abi Nu’aim al-Laitsi (w. 169 H), imam penduduk Madinah. Ia mengambil qira’ah dari Abu Ja’far al-Qârri, dari 70 orang ahli Madinah. Dan dari Nafi', qira'ahnya diambil oleh Qâlûn (Isa bin Minâ bin Wardan al-Madani, wafat tahun 220 H) dan Warasy (Utsman bin Sa'id bin Abdullah al-Mishri, imam ahli qira'ah Mesir di masanya, wafat tahun 197 H)
- Ibnu Katsir, yaitu Abdullah bin Katsir ad-Dâri al-Makki (w. 120 H), imam para qurra’ (penghafal al-Quran) di Makkah. Ia mengambil bacaannya dari al-Mughirah bin Syihab dari Utsman bin ‘Affan.
- Abu 'Amr bin al-Alâ', Zabban bin al-'Ala' bin 'Ammar at-Tamimi al-Bashri (w. 154 H), imam dalam bahasa dan adab dan juga salah seorang imam qira'ah sab'ah. Ia meriwayatkan bacaannya dari Mujahid dan Sa’id bin Jubair (keduanya murid Ibnu Abbas)
- Ibnu ‘Amir (Abdullah bin ‘Amir al-Yahshabi, Abu Imran, wafat tahun 118 H), imam para qurra’ di Syam. Bertahun-tahun ia mengimami kaum muslimin di al-Jami al-Umawi, Damaskus, dan Khalifah Umar bin Abdil Aziz bermakmum di belakangnya. Ia mengambil qira’ahnya dari al-Mughirah bin Syihab dari Utsman.
- ‘Ashim bin Abi an-Nujud al-Kufi al-Asadi (w. 127 H), yang mengambil qira’ah dari Ibnu Mas’ud, imam ahli qira'ah di Kufah. Darinya qira’ah itu diambil oleh Hafsh bin Sulaiman (qari' penduduk Kufah dan murid 'Ashim yang paling mengenal qira'ah 'Ashim, wafat 180 H), Syu'bah bin 'Ayyasy al-Asadi (193 H) dan lainnya.
- Hamzah bin Habib al-Kufi (w. 156 H). Ia sempat menjumpai masa kehidupan beberapa shahabat, dan barangkali saja ia pernah melihat mereka. Diantara tokoh yang mengambil qira'ah darinya adalah Khallad bin Khalid asy-Syaibani (seorang yang tsiqah dan imam dalam qira'ah dan) dan Khalaf bin Hisyam al-Asadi al-Baghdadi (w. 229 H) yang mengambil qira'ah dari Salim bin Isa dan Abdurrahman bin Hammad, dari Hamzah. Khalaf telah memilih untuk dirinya sebuah qira'ah yang ia riwayatkan secara tersendiri, sehingga ia dianggap bagian dari sepuluh qira'ah yang diakui.
- Al-Kisa’i, yaitu Ali bin Hamzah al-Kisa’i an-Nahwi al-Kufi (w. 189 H), imam dalam bahasa dan nahwu, dan salah satu imam ahli qira'ah. Telah meriwayatkan darinya jumlah yang sangat banyak.
Kedua :
Qira’ah yang diperselisihkan tentang status mutawatirnya, yaitu tiga qira’ah
yang menyempurnakan qira’ah yang tujuh diatas menjadi sepuluh. Ketiganya
adalah,
- Abu Ja’far al-Madani, Yazîd bin al-Qa’qâ’ al-Makhzumi al-Qârri (w. 130 H), imam ahli Madinah dalam qira'ah
- Ya’qub al-Bashri, Abu Muhammad Ya’qub bin Ishaq al-Hadhrami al-Bashri (w. 205 H), pakar qira'ah kota Bashrah
- Khalaf al-Baghdadi, Abu Muhammad Khalaf bin Hisyam bin Tsa’lab bin Khalaf (w. 229 H), yang telah disebutkan biografinya
Seperti yang
telah dijelaskan, pendapat yang benar dan terpilih bahwa
qira’ah-qira’ah ini juga mutawatir dan diamalkan. Para ulama ushul, para fuqaha' dan lain-lain telah bersepakat bahwa tidak ada qira'ah yang mutawatir yang lebih dari sepuluh qira'ah ini.
Kesimpulannya, tujuh qira'ah adalah mutawatir dengan kesepakatan para ulama, tiga qira'ah adalah qira'ah yang benar dan diterima menurut pendapat yang kuat dan terpilih, sementara empat bacaan yang selebihnya adalah qira'ah yang syâdzdzah menurut kesepakatan ulama. Keempat qira'ah itu adalah riwayat para imam berikut ini,
- Muhammad bin Abdirrahman bin Muhaishin al-Makki (w. 123 H)
- Yahya bin al-Mubarak al-Yazidi (w. 202 H)
- Al-Hasan bin Abil Hasan Yasar al-Bashri (w. 115 H), dan
- Sulaiman bin Mihran al-A'masy al-Kufi (w. 148 H)
Wallahu a'lam.