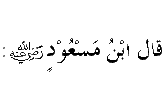29 Mei 2016
Bai’at Al-Aqabah Pertama
Pada musim
haji tahun 11 setelah kenabian, Nabi ﷺ berkumpul di ‘Aqabah bersama
enam orang dari penduduk Yatsrib, yang semuanya berasal dari suku
Khazraj. Mereka adalah Abu Umamah As’ad bin Zurarah, ‘Auf bin al-Harits
bin Rifa’ah (dikenal dengan nama ‘Auf bin ‘Afra’), Rafi’ bin Malik,
Quthbah bin ‘Amir, ‘Uqbah bin ‘Amir dan Jabir bin Abdillah bin Ri’ab.
Nabi ﷺ mengajak mereka kepada Islam dan mereka semuanya masuk Islam.
Mereka
kemudian kembali ke Yatsrib dan mengajak kaumnya kepada Islam. Maka
tersebarlah Islam di Yatsrib sehingga tidak tersisa satu rumah di
Yatsrib melainkan dakwah Islam telah masuk kepadanya.
Pada musim
haji tahun berikutnya, datanglah 12 orang, sepuluh dari Khazraj, dan
dua lainnya berasal dari suku Aus. Sepuluh orang Khazraj tersebut lima
diantaranya adalah kelompok yang datang pada tahun sebelumnya kecuali
Jabir bin Abdillah bin Ri’ab, sementara lima lainnya adalah Mu’adz bin
al-Harits (saudara ‘Auf bin al-Harits) Dzakwan bin Abdil Qais, ‘Ubadah
bin ash-Shamit, Yazid bin Tsa’labah dan al-‘Abbas bin ‘Ubadah bin
Nadhlah. Dan dua orang yang berasal dari Aus adalah Abul Haitsam bin
at-Taihan serta ‘Uwaim bin Sa’idah.
Dzakwan
tetap berdiam di Makkah hingga kemudian ia ikut berhijrah ke Madinah,
sehingga ia dikenal sebagai seorang Anshar yang ikut berhijrah (muhâjirî anshârî).
Dua belas Anshar inilah yang berbai’at kepada Nabi ﷺ dan bai’at tersebut dikenal sebagai bai’ah al-‘aqabah al ûlâ (bai’at Aqabah pertama).
Adapun isi
dari bai’at adalah apa yang diriwayatkan al-Bukhary dari Ubadah bin
ash-Shamit bahwa Nabi ﷺ bersabda kepada kelompok orang-orang tersebut, “Marilah
berbai’at kepadaku untuk tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatupun,
tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak-anak kalian, tidak
mendatangkan kedustaan yang kalian ada-adakan diantara kedua tangan dan
kaki kalian dan tidak membangkang kepadaku dalam perkara yang ma’ruf.
Siapa diantara kalian yang setia (dengan perjanjian ini) maka dia berhak
mendapatkan pahala dari Allah, dan siapa yang melakukan sesuatu darinya
dan Allah menutupi aibnya maka urusannya dikembalikan kepada Allah;
jika Dia berkehendak Dia akan menyiksanya dan jika Dia berkehendak maka
Dia akan memaafkannya.” (terjemah HR. Al-Bukhary dan Muslim).
Namun isi bai’at ini diingkari oleh Ibnu Hajar rahimahullahu.
Ia menguatkan bahwa isi bai’at ini adalah bai’at yang lain dan terjadi
setelah penaklukan Makkah, bukan terjadi di malam peristiwa Aqabah yang
pertama.
Ibnu Hajar
mengatakan bahwa isi bai’at pada malam Aqabah adalah apa yang
diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq dan lain-lain bahwa Nabi ﷺ bersabda kepada
kaum Anshar yang hadir pada saat itu, “Aku membai’at kalian agar kalian melindungiku dari perkara yang kalian akan melindungi istri-istri dan anak-anak kalian darinya.”;
maka mereka pun membai’at beliau diatas perkara tersebut dan juga
beliau dan sahabat-sahabatnya akan berhijrah ke negeri mereka.
Dan dalam
riwayat Ahmad dan ath-Thabrani disebutkan perkataan Ubadah kepada Abu
Hurairah, “Wahai Abu Hurairah, engkau belum bersama kami saat kami
membai’at Rasulullah ﷺ untuk taat dan mendengar dalam keadaan semangat
atau malas, untuk menyuruh kepada yang ma’ruf dan melarang dari
kemungkaran, untuk mengucapkan kebenaran tanpa takut -semata-mata karena
Allah- dari celaan orang yang suka mencela, dan untuk membela Rasulullah ﷺ
jika ia datang kepada kami di Yatsrib serta melindungi beliau dari
perkara yang kami akan melindungi istri-istri dan anak-anak kami darinya
dan untuk kami pahala surga. Itulah bai’at Rasulullah ﷺ yang kami
membai’atnya diatas perkara tersebut.” (silahkan rujuk Fathul Bari, I/84-85, cet. As-Salafiyyah).
Setelah
pembai’atan itu, Nabi ﷺ mengutus bersama mereka Mush’ab bin ‘Umair
al-‘Abdari dan menyuruhnya untuk membacakan al-Quran kepada mereka dan
mengajarkan Islam. Di Yatsrib, Mush’ab tinggal di rumah As’ad bin
Zurarah, radhiyallahu ‘anhum.
Wallahu a’lam.
(Sumber : As-Sirah An-Nabawiyyah Ash-Shahihah oleh Dr. Akram Al-Umari, Raudhah Al-Anwar fi Sirah An-Nabiyy Al-Mukhtar oleh Al-Mubarakfuri dan Waqafat Tarbawiyyah ma'a As-Sirah An-Nabawiyyah oleh Ahmad Farid)
20 Mei 2016
Peristiwa Isra’ & Mi’raj
Setelah
perjalanan yang menyakitkan di Tha’if, terjadilah peristiwa Isra’ &
Mi’raj sebagai salah satu mu’jizat dari Allah. Hal ini juga sebagai
hiburan untuk Rasulullah ﷺ setelah peristiwa Tha'if dan kematian dua orang yang sangat disayanginya, Abu Thalib dan Khadijah.
Allah Ta’ala berfirman,
سُبْحَانَ
الَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى
الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ
آيَاتِنَا ۚ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ
“Maha
suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya pada suatu malam dari
al-Masjid al-Haram ke al-Masjid al-Aqsha yang telah Kami berkahi
sekelilingnya agar Kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda
(kebesaran) Kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha Mendengar lagi Maha
Melihat.” (QS. Al-Isra’ ayat 1).
Dalam kitab ash-Shahîhain dari Anas ia berkata : Abu Dzarr menceritakan dari Rasulullah ﷺ, beliau berkata (artinya), “Terbuka
atap rumahku sementara aku berada di Makkah. Turunlah Jibril, ia
membedah dadaku kemudian mencucinya dengan air Zamzam. Kemudian Jibril
datang dengan sebuah bejana emas yang penuh dengan hikmah dan iman, dan
ia menuangkannya dalam dadaku kemudian menautkannya kembali. Kemudian ia
mengambil tanganku dan membawaku naik ke langit dunia…”
Riwayat-riwayat shahih lainnya menyebutkan bahwa Rasulullah ﷺ
berada di Masjid Al-Haram, atau di Al-Hathim atau Al-Hijr di Ka’bah
ketika dibedah dadanya dan dicuci hatinya.
Mungkin mengumpulkan
riwayat-riwayat tersebut bahwa beliau pada awalnya berada di rumahnya
kemudian Jibril membawanya ke Masjid Al-Haram.
Tujuan
dari pembedahan itu sendiri adalah untuk mengisi hati beliau dengan
keimanan dan hikmah sebagai persiapan perjalanan beliau bersama Jibril.
Selesai pembedahan dada oleh dua Malaikat, Rasulullah ﷺ diperjalankan menuju Baitul Maqdis di Al-Quds (Yerussalem) dengan mengendarai Burâq[1], dimana beliau shalat bersama para nabi dan beliau menyebutkan sifat-sifat mereka.[2]
Kemudian
beliau dibawa naik menuju langit ketujuh dengan melewati langit-langit
yang enam, dan berjumpa dengan para nabi; Adam, Yusuf, Idris, Isa,
Yahya, Harun, Musa dan Ibrahim.
Beliau
telah mendengarkan goresan pena para Malaikat, dan diwajibkan atasnya
shalat sebanyak 50 kali dan kemudian diringankan menjadi 5 shalat dalam
sehari.[3]
Beliau menyebutkan sifat Sidratul Muntahâ; buahnya sebesar bejana air dan daun-daunnya seperti telinga-telinga gajah.[4]
Beliau menyebutkan sifat Al-Bait Al-Ma’mûr di langit ketujuh dan para Malaikat yang memasukinya.[5]
Beliau juga menyebutkan tentang sungai Al-Kautsar di Surga, kedua tepinya terdapat kubah-kubah mutiara yang lapang dan tanahnya terbuat dari kesturi yang sangat harum.[6]
Rasulullah ﷺ ditanya jika beliau melihat Rabb-nya? Beliau berkata (artinya), “Cahaya… Bagaimana aku bisa melihat-Nya?!”[7]
Beliau
juga menyebutkan apa yang dilihatnya dari sungai-sungai surgawi. Empat
sungai; dua tersembunyi di dalam Surga, dan dua lainnya nampak dan
keduanya adalah sungai Nil dan Eufrat.[8]
Beliau juga menjelaskan bahwa ia melihat Jibril 'alaihissalam dalam rupa aslinya dan Jibril memiliki enam ratus sayap.[9]
Saat Mi’raj, beliau melihat siksa orang-orang yang suka menggunjing (ghibah) manusia. Mereka memiliki kuku-kuku dari tembaga yang dengannya mereka mencakar wajah-wajah dan dada-dada mereka.[10]
Sebelum
dinaikkan ke langit, Jibril membawakan gelas yang berisi arak dan gelas
yang berisi susu serta gelas yang berisi madu. Beliau mengambil susu dan
Jibril berkata, “Dia adalah fitrah.”[11]
Berita-berita
ini ketika disampaikan kepada kaumnya, beliau dibenarkan oleh
orang-orang mukmin dan didustakan oleh orang-orang musyrik. Rasulullah ﷺ bersabda (yang artinya), “Sungguh
aku melihat diriku di Al-Hijr sementara Quraisy menanyaiku tentang
perjalananku itu. Quraisy bertanya beberapa hal tentang Baitul Maqdis
yang aku tidak mengetahuinya. Aku pun diliputi oleh kesusahan yang tidak
pernah aku rasakan sebelumnya.”
Beliau berkata (artinya), “Maka
Allah mengangkatnya untukku hingga aku bisa melihatnya. Mereka tidak
bertanya padaku tentang sesuatu melainkan aku sampaikan pada mereka
beritanya.”[12]
Quraisy bingung dan keheranan, akan tetapi mereka terpaksa harus mengakui kebenaran perkataannya tentang Masjid Baitul Maqdis.[13]
Peristiwa ini di satu sisi merupakan hiburan dan ketenangan untuk Rasulullah ﷺ, dan di sisi lain dia adalah fitnah bagi orang-orang kafir yang semakin bertambah kesombongan dan pembangkangannya.
Peristiwa ini terjadi dalam kenyataan dan kesadaran, yang dijalani oleh Rasullullah ﷺ
dengan ruh dan jasadnya. Terjadi hanya sekali saja selama hidupnya, dan
peristiwa isra’ dan mi’raj juga dilakukan dalam satu malam. Demikian
pendapat yang paling kuat dari jumhur ulama Islam.
Wallahu a’lam.
(Disadur dari kitab yang sangat bagus dalam sirah, As-Sîrah An-Nabawiyyah Ash-Shahîhah oleh Dr. Akram Dhiya’ Al-Umari)
———————————–
Footnotes :
[1] Burâq adalah hewan putih yang lebih besar dari keledai dan lebih kecil dari baghal yang disebutkan oleh Nabi ﷺ bahwa dia menjejakkan kakinya saat melompat sejauh pandangan matanya.
[2] HR. Al-Bukhary dan Muslim
[3] HR. Al-Bukhary dan Muslim, kumpulan dari riwayat keduanya
[4] HR. Ahmad dengan sanad yang shahih
[5] HR. Muslim
[6] HR. Al-Bukhary
[7] HR. Muslim
[8] HR. Al-Bukhary
[9] HR. Al-Bukhary dan Muslim. Dan kejadian itulah yang diisyaratkan firman Allah dalam surat An-Najm ayat 9-18
[10] HR. Ahmad dan Abu Dawud dengan sanad yang shahih, dishahihkan Al-Albani
[11] HR. Al-Bukhary dan Muslim
[12] HR. Al-Bukhary dan Muslim
[13] HR. Ahmad dengan sanad yang shahih, dishahihkan oleh As-Suyuthi dan Al-Haitsami
14 Mei 2016
Pengertian Ayat dan Surat
Ayat (Al-Âyah)
Al-âyah adalah sekelompok dari kata-kata yang memiliki permulaan dan potongan yang berada dalam surat-surat al-Quran al-Karim.
Tidak ada jalan untuk mengetahui permulaan dan akhir ayat kecuali dengan ketentuan Syari’at (tauqîfî).
Tidak ada padanya lowongan untuk qiyas atau pendapat, dengan dalil
sederhana bahwa para ulama menganggap ( المص ) dalam surat al-A’raf
sebagai satu ayat, sementara yang sepertinya dalam surat ar-Ra’ad ( المر
) tidak dianggap sebagai satu ayat.
Karena
itu, para ulama berselisih tentang jumlah ayat-ayat al-Quran, walaupun
mereka bersepakat bahwa ayat al-Quran berjumlah lebih dari 6.000 ayat.
Pendapat yang kuat (rajih) -wallahu a'lam- bahwa ayat-ayat al-Quran berjumlah 6.236 ayat.
Adapun urutan ayat dan penempatannya dalam suatu surat maka hal itu adalah perkara tauqîfî. Nabi ﷺ telah menetapkannya sesuai dengan petunjuk Jibril ‘alaihissalam.
Surat (As-Sûrah)
Yaitu satu kumpulan yang berdiri sendiri dari ayat-ayat al-Quran, yang memiliki permulaan dan pengakhiran.
Para ulama berselisih tentang urutan surat-surat al-Quran apakah hal itu tauqîfî dengan dalil atau tauqîfî dengan ijtihad?[1].
Terlepas dari perselisihan itu, yang wajib adalah menghormati
urutan-urutan tersebut dalam penulisan mushaf al-Quran. Karena para
Shahabat radhiyallahu ‘anhum telah ber-ijma’ (bersepakat) tentang hal itu, dan menyelisihinya hanya akan membawa kepada fitnah.
Adapun dalam tilawah (bacaan), maka memelihara urutan tersebut bersifat sunnah (dianjurkan) dan tidak wajib.
——————
[1] Silahkan rujuk ke Manâhil al ‘Irfân, I/hal. 244 dan yang selanjutnya.
09 Mei 2016
Syirik dalam Menyembelih
Menyembelih pada asalnya terbagi kepada 4 bentuk;
1. Menyembelih hewan yang halal dikonsumsi untuk taqarrub (mendekatkan diri) kepada Allah Ta’ala dan mengagungkanNya, seperti qurban pada Idul Adha (al udhhiyah) dan saat haji tamattu’ dan qiran (diistilahkan dengan al hadyu).
Seperti juga menyembelih untuk bersedekah dengan dagingnya kepada
orang-orang fakir. Yang seperti ini disyari’atkan dan termasuk dalam
ibadah.
2.
Menyembelih hewan yang halal dikonsumsi untuk tamu, atau untuk walimah
pernikahan dan yang semacamnya. Yang seperti ini diperintahkan entah
dalam bentuk perintah wajib atau bersifat anjuran.
3.
Menyembelih hewan yang halal dikonsumsi untuk diperdagangkan dengan
menjual dagingnya, atau untuk dimakan, atau sebagai wujud kegembiraan
saat menempati rumah baru dan yang semacamnya. Yang seperti ini hukum
asalnya adalah mubah.
4.
Menyembelih untuk mendekatkan diri kepada makhluk, mengagungkannya dan
merendahkan diri kepadanya. Yang seperti ini adalah ibadah, seperti yang
sudah dijelaskan, dan tidak boleh bertaqarrub dengannya kepada selain
Allah Ta’ala. Siapa yang menyembelih dalam rangka untuk bertaqarrub
kepada makhluk dan mengagungkannya, maka ia telah terjatuh kepada syirik
akbar, sembelihannya haram dan tidak boleh dimakan. Sama saja makhluk
tersebut adalah seorang manusia, atau jin, atau dari kalangan malaikat,
atau berbentuk sebuah kubur dan lain-lain.
Allah Ta’ala berfirman,
قُلْ إنَّ صَلاَتِيْ وَنُسُكِيْ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِيْ لِلهِ رَبِّ العَالَمِيْنَ لاَ شَرِيْكَ لَهُ
“Katakanlah : Sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Rabb semesta alam, tiada sekutu bagiNya.” (QS. Al-An’am ayat 162-163).
Berkata para ulama tafsir : “Nusuk adalah sembelihan.”
Dan firmanNya,
فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ
“Maka dirikanlah shalat karena Rabb-mu dan berqurbanlah.” (QS. Al-Kautsar ayat 2).
Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ‘anhu ia berkata : Bersabda Rasulullah ﷺ,
لعن الله من ذبح لغير الله
“Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah.” (HR. Muslim).
Berkata Imam an-Nawawi asy-Syafi’i rahimahullahu dalam Syarh Shahih Muslim
(XIII/141) bahwa siapa yang menyembelih untuk selain Allah,
perbuatannya itu adalah haram. Kemudian ia berkata, “Disebutkan hal itu
oleh asy-Syafi’i, dan disepakati oleh sahabat-sahabat kami. Jika dia
memaksudkan bersama sembelihan itu pengagungan terhadap orang yang
disembelihkan untuknya yang selain Allah Ta’ala dan beribadah untuknya,
maka yang demikian itu adalah kekafiran. Jika yang menyembelih itu
muslim sebelum itu, maka dia menjadi murtad dengan sembelihan tersebut.”
Wallahul musta’an.
(Sumber : Tahdzîb Tashîl al Aqîdah al Islâmiyyah)
08 Mei 2016
Sya’ban, antara Sunnah dan Bid’ah
Sya’ban
adalah salah satu bulan ibadah, menjelang datangnya bulan yang agung,
yaitu bulan Ramadhan. Sayangnya, banyak diantara kaum muslimin yang
mengabaikan sunnah-sunnah yang shahih berkait dengan ibadah di bulan
Sya’ban, dan justru terjatuh dalam perkara-perkara bid’ah yang tercela.
Apa yang Dilakukan Nabi ﷺ di Bulan Sya’ban?
Dari Usamah bin Zaid radhiyallahu ‘anhu,
ia berkata : Saya berkata : “Wahai Rasulullah, saya tidak melihatmu
berpuasa pada salah satu dari bulan-bulan yang ada sebagaimana puasamu
di bulan Sya’ban?”
Beliau ﷺ menjawab,
ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم
“Itu
adalah bulan yang manusia lalai darinya, antara Rajab dan Ramadhan.
Bulan yang padanya amal-amal diangkat kepada Rabb semesta alam. Dan aku
suka jika amalku diangkat dan aku dalam keadaan berpuasa.” (HR. An-Nasa’i).
Dari Aisyah radhiyallahu ‘anha, ia berkata, “Nabi ﷺ
tidak pernah berpuasa yang lebih banyak daripada (puasa di bulan)
Sya’ban. Beliau berpuasa (di bulan) Sya’ban seluruhnya.” (HR.
Al-Bukhary).
Keutamaan Malam Pertengahan (Nishfu) Sya’ban
Dari Abu Musa al-Asy’ari radhiyallahu ‘anhu, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,
إن الله ليطلع في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن
“Sesungguhnya
Allah melihat pada malam pertengahan Sya’ban, maka Dia mengampuni semua
hambaNya kecuali orang yang musyrik dan suka memusuhi.” (HR. Ibnu Majah, dishahihkan al-Albani dalam ash-Shahihah no. 1144).
Hadits tersebut hanya menyebutkan keutamaan malam itu tanpa menganjurkan sebuah ibadah tertentu yang dikhususkan pada malam dan hari pertengahan bulan Sya'ban. Tidak ada satu dalil pun yang shahih berkenaan dengan anjuran beribadah pada malam dan hari itu.
Bid’ah-bid’ah yang Masyhur di Bulan Sya’ban
1. Shalat al-Bara’ah, yaitu shalat yang dikhususkan pada malam Nishfu Sya’ban sebanyak 100 raka’at.
2. Shalat 6 raka’at yang diniatkan untuk menolak bala’, panjang umur dan tercukupi dari meminta-minta kepada manusia.
3. Membaca surat Yasin dan berdoa dengan doa khusus pada malam tersebut.
4. Keyakinan sebagian mereka bahwa malam Nishfu Sya’ban adalah Lailatul Qadr.
Sejarah Terjadinya Bid’ah Tersebut
Berkata
al-Maqdisi, “Yang pertama terjadi di kami pada tahun 448 H, ketika
datang kepada kami di Baitul Maqdis seorang laki-laki dari Nablus yang
dikenal sebagai Ibnu Abi al-Humaira’, dan ia seorang yang bagus
bacaannya. Ia melakukan shalat di Masjid al-Aqsha pada malam Nishfu
Sya’ban, dan bermakmum di belakangnya seorang laki-laki. Kemudian
bertambah orang yang ketiga, keempat… Dan tidaklah dia mengkhatamkannya
hingga dia telah berkumpul bersama jamaah yang banyak…” (Al-Ba’its ‘ala Inkar al-Bida’ wa al-Hawadits, 124-125).
Berkata
an-Najm al-Ghaithi, “Sungguh, hal itu telah diingkari banyak ulama dari
penduduk Hejaz diantaranya Atha’, Ibnu Abi Mulaikah, para fuqaha’
Madinah dan sahabat-sahabat Malik. Mereka berkata : Semua itu adalah
bid’ah!” (As-Sunan wa al-Mubtada’at, asy-Syuqairi, hal. 145).
04 Mei 2016
Adab Meminjam Buku
Meminjamkan buku termasuk salah satu sarana untuk menyebarkan ilmu. Namun perlu diperhatikan beberapa adab berikut ini,
- Berterima kasih kepada orang yang meminjamkan buku dan mendoakan kebaikan untuknya
- Tidak boleh buku itu berada di tangan peminjam dalam waktu yang lama tanpa ada hajat yang penting [1]
- Buku yang dipinjam adalah buku yang bermanfaat dan tidak berbahaya
- Wajib bagi peminjam untuk segera mengembalikan buku yang dipinjamnya [2]
- Tidak boleh memperbaiki/memperbagus sesuatu dari buku yang dipinjam tanpa izin pemiliknya. Demikian juga tidak boleh menuliskan sesuatu padanya kecuali jika diketahui bahwa pemiliknya ridha dengan hal tersebut
- Tidak boleh meminjamkan lagi buku itu ke orang lain tanpa seizin pemiliknya
- Peminjam harus memeriksa buku pinjamannya sebelum membawanya dan sebelum mengembalikannya untuk memastikan bahwa buku dalam keadaan baik
(Sumber : Muntaqâ al Âdâb asy Syar’iyyah, Mâjid bin Su’ûd Âlu ‘Ausyan)
———————————
Footnotes :
[1] Disebutkan dalam biografi al-Khatib al-Baghdadi rahimahullahu
bahwa seseorang memintanya untuk meminjamkannya sebuah buku. Al-Khatib
berkata padanya, “Engkau memiliki waktu 3 hari.” Orang itu berkata,
“Waktu itu tidak cukup.” Al-Khatib berkata, “Aku telah menghitung
lembaran-lembarannya. Jika engkau ingin menyalinnya maka 3 hari cukup.
Jika engkau ingin membacanya maka 3 hari cukup. Jika engkau ingin lebih
dari itu, maka saya lebih berhak dengan buku saya ini.”
[2] Dahulu sebagian Salaf tidak meminjamkan buku kecuali dengan jaminan. Abu Hafsh Umar bin Utsman al-Janazi pernah bersyair,
إذا أعرت كتاباً فخذ # على ذلك رهناً وخلّ الحياء
فإنك لم تتهمْ مستعيرًا # ولكــــــن لتذكر منه الأداء
Jika engkau meminjamkan buku, maka ambillah # untuk hal itu jaminan dan tinggalkan rasa malu
Karena sungguh engkau tidak menuduh orang yang meminjam # akan tetapi mengingatkannya untuk menunaikan amanah
01 Mei 2016
Mereka tidak Mengkafirkan Kaum Muslimin
Diantara
prinsip dasar aqidah as-Salaf ash-Shalih, Ahlussunnah wal Jama’ah, bahwa
mereka tidak mengkafirkan individu tertentu dari kaum muslimin yang
melakukan sesuatu yang berkonsekuensi pada kekafiran, kecuali setelah
ditegakkannya hujjah (argumen); terpenuhi syarat-syaratnya, hilang penghalang-penghalangnya (al mawâni’) dan tidak ada lagi syubhat (kesamaran) dalam diri seorang jahil atau memiliki ta’wil/penafsiran (muta-awwil).
Dan sudah
dipahami, bahwa hal ini hanya pada perkara-perkara samar/tersembunyi
yang butuh kepada penjelasan, bukan pada persoalan-persoalan yang sudah
sangat jelas, seperti mengingkari wujud Allah Ta’ala, mendustakan Rasul ﷺ, atau mengingkari risalah atau penutup kenabiannya.
Ahlussunnah tidak mengkafirkan orang yang dalam keadaan dipaksa (mukrah), jika hatinya tetap tenang dalam keimanan.
Demikian
juga, mereka tidak mengkafirkan seorang pun dari kaum muslimin dengan
setiap dosa, walaupun dosa-dosa itu merupakan dosa-dosa besar (kabâ-ir adz dzunûb)
yang selain syirik. Ahlussunnah tidak memvonis kafir kepada para pelaku
dosa besar. Mereka hanya menghukuminya dengan sifat kefasikan atau
berkurangnya iman selama dia tidak menghalalkan dosanya tersebut. Karena
Allah Ta’ala berfirman,
إنَّ
اللهَ لاَ يَغْفِرُ أنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذَلِكَ
لِمَنْ يَشَاءُ, وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللهِ فَقَد افْتَرىَ إثْمًا عَظِيْمًا
“Sesungguhnya
Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa
yang selain itu bagi siapa yang dikehendakiNya. Barangsiapa yang
mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar.” (QS. An-Nisa’ ayat 48).
Dan firmanNya,
قُلْ
يَا عِبَادِيَ الَّذِيْنَ أسْرَفُوا عَلىَ أنْفُسِهِمْ لاَ تَقْنَطُوا مِن
رَحْمَةِ اللهِ إنَّ اللهَ يَغْفِرُوا الذُنُوْبَ جَمِيْعًا إنَّهُ هُوَ
الغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ
“Katakanlah
: Hai hamba-hambaKu yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri,
janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah
mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dia-lah Yang Maha Pengampun
lagi Maha Penyayang.” (QS. Az-Zumar ayat 53).
Ahlussunnah
wal Jama’ah tidak mengkafirkan seorang pun karena sebuah dosa yang
tidak terdapat dalil yang menunjukkan bahwa dosa itu adalah sebuah
kekufuran. Jika orang tersebut meninggal dalam keadaan demikian, maka
urusannya dikembalikan kepada Allah Ta’ala, jika Dia menghendaki Dia
akan menyiksanya, dan jika Dia menghendaki maka Dia akan mengampuninya.
Hal ini menyelisihi firqah-firqah sesat yang menghukumi para pelaku dosa
besar dengan kekafiran seperti keyakinan sekte Khawarij, atau berada
pada satu diantara dua status (al-manzilah bainal manzilatain), bukan muslim dan bukan kafir sebagaimana
yang diyakini Mu’tazilah.
Nabi ﷺ telah memperingatkan dari bahaya mengkafirkan tersebut. Beliau bersabda,
أيما امرئٍ قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، إن كان كما قال وإلا رجعت عليه
“Siapa
saja yang berkata kepada saudaranya: Hai kafir!, maka perkataan itu
kembali kepada salah satu dari keduanya. Jika benar seperti yang orang
itu katakan, atau jika tidak benar, perkataan itu kembali kepadanya.” (HR. Muslim).
Beliau ﷺ bersabda,
من دعا رجلاً بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه
“Siapa
yang memanggil seseorang dengan kekafiran, atau dia mengatakan: Musuh
Allah!, dan orang itu tidaklah demikian, melainkan hal itu akan kembali
kepada yang mengucapkan.” (HR. Muslim).
Beliau ﷺ juga bersabda,
ومن رمى مؤمنًا بكفلرٍ فهو كقتله
“Siapa yang menuduh seorang mukmin dengan vonis kekafiran, maka itu seperti membunuhnya.” (HR. Al-Bukhary).
Dan beliau ﷺ bersabda,
إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء به أحدهما
“Jika seorang laki-laki berkata kepada saudaranya: Hai kafir!, maka perkataan itu kembali kepada salah satu dari keduanya.” (HR. Al-Bukhary).
Ahlussunnah
wal Jama’ah membedakan antara hukum mutlak terhadap para pelaku bid’ah
dan maksiat atau kekafiran, serta hukum terhadap individu tertentu
–orang yang telah pasti keislamannya dengan yakin- bahwasannya dia
adalah seorang pendosa, seorang fasik atau seorang yang kafir. Mereka
tidak menghukuminya dengan vonis-vonis tersebut hingga jelas baginya
kebenaran, yaitu dengan menegakkan hujjah dan menghilangkan syubhat. Ini
dalam perkara-perkara yang tersembunyi dan samar, bukan dalam
perkara-perkara yang jelas.
Dan mereka tidak mengkafirkan individu tertentu kecuali jika telah terpenuhi padanya syarat-syarat (asy syurûth) dan hilang penghalang-penghalangnya (al mawâni’).
Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu ia berkata : Saya mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, “Dahulu
ada dua orang dari Bani Israil yang saling bersaudara. Salah satunya
suka melakukan dosa, sementara yanng lainnya rajin beribadah. Ahli
ibadah itu selalu melihat yang lainnya melakukan dosa, maka ia berkata :
Berhentilah! Suatu hari ia mendapatkannya sedang melakukan dosa dan ia
berkata padanya : Berhentilah! Orang itu menjawab : Biarkan aku dengan
Rabb-ku! Apakah engkau diutus untuk mengawasi aku?! Maka ahli ibadah itu
berkata : Demi Allah, Allah tidak akan mengampunimu! – atau
(perkatannya) : Allah tidak akan memasukkanmu ke dalam Surga!… Mereka
akhirnya diwafatkan dan keduanya berkumpul di sisi Rabb semesta alam.
Allah berkata kepada ahli ibadah : Apakah engkau mengetahui tentang Aku
ataukah engkau berkuasa atas apa yang ada di Tangan-Ku?! Dan Dia berkata
kepada si pendosa : Pergilah, dan masuklah ke dalam Surga dengan
rahmat-Ku. Dan Dia berkata kepada yanng lainnya : Bawalah dia ke dalam
Neraka!”
Berkata
Abu Hurairah : “Demi jiwaku yang berada di Tangan-Nya, dia berbicara
dengan satu kata yang menghancurkan dunia dan akhiratnya!” (Terjemah HR.
Abu Dawud).
Kekafiran adalah lawan dari keimanan.
Hanya saja, kekafiran dalam istilah Syari’at terbagi dua; jika
disebutkan kata “kekafiran” dalam dalil-dalil maka terkadang yang
dimaksudkan adalah kekafiran yang mengeluarkan dari millah (agama), dan
terkadang dimaksudkan kekafiran yang tidak mengeluarkan dari millah.
Yang demikian itu karena kekafiran memiliki cabang-cabang sebagaimana
keimanan juga memiliki cabang.
(Sumber : Al Wajîz fî ‘Aqîdah as Salaf ash Shâlih)