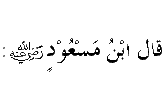31 Oktober 2015
Laki-laki Tidaklah Seperti Perempuan
Allah
Ta’ala telah menciptakan manusia dalam dua jenis. Dan Dia juga
menyebutkan bahwa kedua jenis itu berbeda satu dari yang lainnya. Allah
berfirman,
وَلَيْسَ الذَكَرُ كَالأُنْثىَ
“Dan laki-laki tidaklah seperti perempuan.” (QS. Alu ‘Imran ayat 36).
Laki-laki tidak seperti wanita dalam sifat dan bentuk penciptaannya.
Laki-laki
memiliki kesempurnaan dalam bentuk fisik dan kekuatan karakternya,
sementara wanita lebih lemah darinya karena dia harus mengalami masa
haid, kehamilan, melahirkan, menyusui, mengurus anak dan membina
generasi umat.
Karena itulah wanita diciptakan dari tulang rusuk Adam ‘alaihissalam;
dia adalah bagian darinya, mengikuti urusannya dan menjadi perhiasan
untuknya. Sementara laki-laki diamanahkan untuk mengurus wanita,
menjaganya, menafkahinya dan anak-anak yang dilahirkan darinya.
Karena
perbedaan itulah maka berbeda pula beberapa hukum syari’at yang
dibebankan kepada kedua jenis manusia tersebut dalam urusan agama dan
dunia. Laki-laki adalah “qawwâm” dalam rumah tangga dalam wujud
pembinaan, penjagaan, pengayoman dan mengurusi nafkah keluarga.
Laki-laki yang berkuasa dalam rumah tangga dan wanita tidak akan pernah
bisa menyamainya dalam urusan itu atau lebih tinggi darinya.
Allah Ta’ala berfirman,
الرِجَالُ قَوَّامُونَ عَلىَ النِسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُم عَلىَ بَعْضٍ
“Kaum
laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah
melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita).” (QS. An-Nisa’ ayat 34).
Dan firmanNya,
وَلِلرِجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ
“Dan laki-laki (suami) mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada wanita (istri).” (QS. Al-Baqarah ayat 228).
Hukum-hukum
yang Allah khususkan untuk wanita itu sangat banyak yang bisa
didapatkan dalam penjelasan fiqh ibadah, mu’amalat, pernikahan, warisan,
pengadilan dan lain-lain. Termasuk di dalamnya persoalan yang berkenaan
dengan sifat dakwah kaum muslimah.
Dakwah
adalah satu bagian penting dalam agama ini. Hukumnya fardhu kifayah
menurut jumhur ulama. Jika telah ada sekelompok umat yang bekerja untuk
mengajak orang kepada agama Allah, mengajarkan mereka Islam yang hak,
maka kewajiban tersebut gugur dari yang lainnya.
Hukum kewajiban dakwah berlaku umum untuk
laki-laki dan wanita. Hanya saja, dalam aplikasinya tentu terdapat
perbedaan yang mencolok dalam menjalankan misi mulia tersebut. Apalagi
jika “dakwah” itu dipahami sebagai sebuah lembaga yang memiliki visi dan
misi dalam memperjuangkan apa yang mereka yakini atau harapkan dari
pergerakan itu.
Kami tidak
mengingkari pentingnya dakwah yang terorganisir rapi dalam usaha untuk
mencapai sebagian tujuan yang diharapkan dari dakwah. Tapi kami ingkari
jika tujuan suci itu terkotori oleh ambisi untuk mendapatkan kekuasaan,
ketenaran dan kebanggaan di hadapan manusia.
Kami juga
mengingkari jika tujuan suci itu akhirnya terkotori oleh usaha keras
untuk mencapai kuantitas tertentu dengan mengabaikan kualitas kader dan
mad’u dalam ilmu dan ibadah.
Kami juga
ingkari dan sayangkan jika ternyata juga, banyak dari pergerakan (yang
mengatasnamakan) dakwah itu (apalagi membawa nama “dakwah Salaf”) –sadar
atau tanpa sadar- telah mengeksploitasi kaum muslimah untuk kepentingan
sesaat mereka.
Benar,
wanita memiliki kewajiban yang sama dengan laki-laki dalam dakwah, tapi
dakwah itu bukanlah “dakwah” yang justru menghilangkan jati diri wanita
itu sebagai seorang muslimah.
Allah
telah memerintahkan wanita untuk berdiam di rumahnya, dan diamnya di
rumahnya adalah sebagai bentuk ibadahnya kepada Allah Ta’ala. Mewajibkan
seorang muslimah keluar rumah untuk “berdakwah” (baca : berorganisasi)
adalah sebuah kelancangan terhadap agama Allah.
Bagaimana
mungkin mewajibkan seorang muslimah keluar rumah berdakwah, sementara
Allah tidak pernah memerintahkan mengeluarkan mereka dari rumah-rumahnya
kecuali dalam shalat Id saja. Bahkan izin untuk shalat berjamaah di
masjid bagi seorang wanita pun masih disebutkan penekanan, bahwa
rumahnya lebih baik dan utama bagi dirinya.
Dari Ummu Humaid, istri Abu Humaid as-Sa’idi radhiyallahu ‘anhuma, bahwa ia datang kepada Nabi ﷺ dan berkata : Wahai Rasulullah, saya ingin shalat bersamamu.
Beliau berkata,
قَد
عَلِمتُ أنكِ تُحِبِّينَ الصَلاة مَعِي وَصَلاتكِ في بَيتكِ خيرٌ لكِ مِن
صَلاتكِ في حُجرَتكِ وَصَلاتكِ في حُجْرَتك خيرٌ مِن صَلاتكِ في دَاركِ
وصَلاتكِ في دَاركِ خيرٌ لكِ من صَلاتكِ في مَسْجدِ قومِكِ وصَلاتكِ في
مَسجدِ قومِكِ خيرٌ لكِ مِن صَلاتكِ في مَسْجِدِي
“Aku
tahu bahwa engkau sangat ingin shalat bersamaku, namun shalatmu di
kamarmu lebih baik bagimu daripada shalatmu di ruangan rumahmu. Dan
shalatmu di ruangan rumahmu lebih baik daripada shalatmu di rumahmu. Dan
shalatmu di rumahmu lebih baik daripada shalatmu di masjid kaummu. Dan
shalatmu di masjid kaummu jauh lebih baik daripada shalatmu di masjidku.”
Maka
ia (Ummu Humaid) menyuruh dibuatkan untuknya tempat shalat di tempat
yang paling dalam dan gelap di rumahnya, dan ia shalat di tempat itu
hingga ia menjumpai Allah ‘azza wa jalla. (HR. Ahmad, dishahihkan Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban dan al-Albani rahimahumullahu).
Dan diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu ‘anha
bahwa ia pernah mengomentari perbuatan para wanita di masanya. Aisyah
berkata, “Andai Rasulullah ﷺ menjumpai apa yang dibuat oleh wanita,
niscaya beliau akan melarang mereka sebagaimana wanita-wanita Bani
Israil dilarang (ke masjid).” (HR. Al-Bukhary dan Muslim).
Anehnya,
para “aktivis dakwah muslimah” itu, benar mereka tidak keluar rumah
untuk berjamaah di masjid, tapi setiap hari justru mereka keluar rumah
untuk “dakwah”?! Wallâhul musta’ân.
Paling
banter kita katakan bahwa keluarnya seorang wanita dari rumahnya untuk
dakwah (dakwah dalam makna sebenarnya, bukan dibungkus dengan
kepentingan kelompok atau lembaga tertentu) adalah sebuah “keutamaan”.
Tapi keutamaan itu semata-mata karena ada hajat penting untuk itu dan
dengan syarat yang juga penting, yaitu tidak mengabaikan perkara yang
lebih wajib berkait dengan hak suami dan urusan rumah tangga, dan
dilakukan oleh wanita yang punya kapasitas ilmu memadai.[1]
Faktanya
di banyak kelompok pergerakan Islam, semua kadernya dituntut harus
keluar rumah hampir setiap harinya “atas nama dakwah”, bahkan tidak
tersisa hari liburnya kecuali digunakan untuk kepentingan “dakwah”.
Miris
rasanya ketika melihat para akhawat kita yang sudah terpolakan oleh
tuntutan zaman atau keluarga untuk studi atau bekerja mencari
penghasilan, kemudian mereka harus “dipaksa” lagi untuk menghabiskan
waktu dan tenaganya mengurus “bentuk dakwah” yang Allah tidak pernah
wajibkan atas mereka, bahkan tidak juga dianjurkan.
Fakta yang
sangat nyata dalam pergerakan para akhawat aktivis, ketika salah
seorang dari mereka mendapatkan hidayah untuk mengenal agama Allah,
mereka justru didoktrin habis-habisan untuk menjadi aktivis dakwah
diluar rumah, dan tidak dididik dan dibina untuk menjadi muslimah yang
hebat di rumahnya.
Katakanlah
seandainya memang para akhawat itu masih diberikan nasehat untuk
menjadi muslimah yang baik dalam dirinya, hijabnya dan urusan rumahnya,
tapi sangat aneh ketika nasehat itu disampaikan kemudian akhawat
tersebut diberikan seabrek beban kegiatan dan aktivitas lembaga –sekali
lagi mengatasnamakan Allah, Islam dan dakwah- sehingga waktunya habis
hanya untuk mengurus lembaga, mengurus orang lain agar mendapatkan
hidayah, dan yang menjadi korban adalah jatidirinya, rumahnya dan
keluarganya. Lâ haula wa lâ quwwata illâ bi_llâh.
Sebagian
aktivis dakwah berdalih untuk pembenaran aktivitas luar rumahnya dalam
dakwah, bahwa para shahabiyat juga ikut berperang dan Rasulullah ﷺ tidak
menegur mereka dengan perbuatan tersebut.(?!)
Pertanyaannya : siapa shahabiyah yang ikut berperang itu?
Dalam sirah nabawiyyah tidak dikenal wanita yang terlibat langsung dalam peperangan kecuali kisah Nusaibah bintu Ka’ab.
Riwayat kisah tersebut tidak sah[2].
Riwayat-riwayat shahih hanya menyebutkan tentang beberapa muslimah yang
bertugas membantu mengobati dan memberi minum prajurit yang terluka.[3]
Andai para
aktivis itu mau berdalih dengan kisah-kisah seperti ini, mestinya lebih
layak mereka menyuruh para muslimah untuk menjadi dokter dan perawat.
Tapi anehnya, mereka jadikan kisah itu untuk mengeluarkan para muslimah
dari rumahnya demi “dakwah”.
Kalau pun
diasumsikan riwayat tentang shahabiyah yang berperang itu shahih, maka
itu terjadi karena sebuah kondisi yang darurat dan terjadi sebelum
turunnya ayat perintah untuk berhijab. Rasulullah ﷺ tidak pernah
mengikut sertakan wanita dalam peperangan, untuk membantu orang-orang
terluka sekalipun, kecuali dalam perang Uhud. Pertimbangannya, wallahu a’lam,
karena jaraknya yang dekat dari Madinah. Dan perlu diketahui, dalam
perang Ahzab yang terjadi di kota Madinah beliau tidak mengikutsertakan
satu orang pun dari kaum wanita dalam perang tersebut.
Allah
telah menggugurkan kewajiban jihad dari kaum wanita. Karena Nabi ﷺ tidak
pernah memberikan bendera perang kepada seorang wanita dan tidak pula
para khalifah sesudahnya. Beliau bahkan tidak memberi sekedar anjuran
bagi wanita untuk berperang dan tidak pula untuk kepentingan perang.
Bahkan, memanfaatkan wanita dalam perang dan memperbanyak jumlah tentara
dengan kaum wanita adalah tanda kelemahan umat dan rusaknya pemikiran
mereka! (Hirâsah al-Fadhîlah, Syaikh Dr. Bakr Abu Zaid rahimahullahu, hal. 77)
Dari Ummu Salamah radhiyallahu ‘anha
ia berkata, “Wahai Rasulullah, kaum laki-laki berperang sementara kami
tidak berperang. Dan kami hanya mendapatkan setengah warisan?!” Maka
Allah menurunkan,
وَلاَ تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللهُ بِهِ بَعْضَكُم عَلىَ بَعْضٍ
“Dan
janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada
sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain.” (QS. An-Nisa’ ayat
32)
Belajarlah dari Aisyah radhiyallaha ‘anha
Sebagaimana diketahui, Aisyah radhiyallahu ‘anha
adalah satu-satunya ummahatul mukminin, bahkan satu-satunya wanita,
yang terlibat dalam fitnah perang di masa pemerintahan Khalifah Ali bin
Abi Thalib radhiyallahu ‘anhu. Keikutsertaan Aisyah tersebut
dengan bujukan dari keponakannya, Abdullah bin Zubair dan orang-orang
yang bersamanya. Dibayangkan kepadanya bahwa kepergiannya ke Basrah
(Irak) itu adalah kemaslahatan bagi kaum muslimin, untuk mendamaikan
perselisihan kaum muslimin dalam persoalan darah Khalifah Utsman. Aisyah
turut serta dalam peristiwa itu untuk sebuah alasan yang baik dan
terpuji, namun peristiwa itu akhirnya menjadi penyesalan terbesarnya
dalam sisa hidupnya. Setiap kali ia membaca firman Allah,
وَقَرْنَ فيِ بُيُوتِكُنَّ
“Dan berdiamlah kamu di rumahmu.” (QS. Al-Ahzab ayat 33), ia menangis hingga jilbabnya basah.
Apakah
para wanita yang keluar atas nama dakwah itu lebih baik dari Aisyah?
Apakah maslahat yang mereka tuntut sama seperti yang diharapkan dari
keluarnya Aisyah? Aisyah keluar untuk mencegah pertumpahan darah kaum
muslimin yang mereka itu adalah anak-anaknya dalam statusnya sebagai
“ummul mukminin”, sementara para aktivis itu, untuk sebuah keadaan
darurat seperti apa sehingga mereka halalkan wanita dikeluarkan dari
rumahnya sementara Allah telah menyuruhnya untuk diam di rumah?!
Aisyah
tidak pernah terlibat dalam perang. Ia hanya berharap bisa membantu
mendamaikan antar kaum muslimin dan ia mengira bahwa keluarnya dia dari
rumahnya adalah sebuah maslahat untuk tujuan tersebut. Tapi ia akhirnya
menyadari kekeliruannya dan berharap andai saja hal itu tidak pernah
terjadi. Semoga Allah merahmati Ummul Mukminin Aisyah.
Mendidik Wanita adalah Kewajiban Laki-laki
Allah telah mewajibkan kaum laki-laki untuk membina, mendidik dan mengajarkan kaum wanita dalam firmanNya,
يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا قُوا أنْفُسَكُم وَأَهْلِيْكُم نَارًا
“Hai orang-orang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka.” (QS. At-Tahrim ayat 6).
Dan disebutkan dalam kitab ash-Shahîhain
dari Abu Sa’id ia berkata : Para wanita berkata, “Wahai Rasulullah,
kaum laki-laki telah mengalahkan kami terhadap dirimu. Jadikan untuk
kami satu hari dari dirimu.” Maka beliau menjanjikan mereka satu hari
dimana beliau menjumpai mereka dan beliau menasehati mereka dan
menjelaskan perintah (agama).
Di zaman
ini, para wanita yang “terpelajar” itu justru begitu mendominasi dalam
semua urusan menuntut ilmu dan dakwah. Namun, disadari atau tidak,
“kehebatan” banyak aktivis “dakwah” wanita itulah yang justru semakin
melemahkan kaum laki-laki. Di banyak pergerakan, kaum wanitalah yang
justru lebih dominan, dan terkesan para lelaki itu bergantung kepada
wanita dalam banyak urusan kelompok mereka, terkhusus berkait dengan
jumlah pengikut. Hingga terkesan bahwa sebagian laki-laki itu menganggap
urusan ilmu dan pemahaman agama istrinya bukan lagi menjadi
tanggungjawabnya, dan ia cenderung hanya sibuk saja dengan urusan
pekerjaannya dan sangat lemah dalam kualitas ilmu dan ibadahnya. Sekali
lagi karena bergantung kepada aktivitas dakwah wanita di luar rumah!
Shalat
berjamaah di masjid adalah salah satu bentuk pendekatan diri yang sangat
agung kepada Allah Ta’ala. Namun toh demikian, shalatnya seorang wanita
di rumahnya jauh lebih utama daripada shalatnya di masjid bersama
jamaah, walaupun masjid itu adalah masjid Nabawi. Keutamaan itu berkait
dengan pentingnya seorang wanita berdiam di rumahnya. Jika demikian
keadaan wanita dengan shalat di masjid, maka bagaimana lagi hanya urusan
dakwah yang fardhu kifayah, yang tidak mungkin kewajiban dakwah itu
bagi seorang wanita bisa menandingi wajibnya melayani suami dan
berkhidmat untuk rumah tangganya.
Karenanya kita katakan, keluarnya seorang wanita dari rumahnya untuk dakwah tidak lepas dari dua keadaan,
Pertama;
hal itu menjadi sunnah dan dianggap sebagai sebuah syari’at bagi kaum
muslimin. Maka tidak diragukan bahwa yang seperti ini adalah bid’ah yang
tercela.
Kedua;
hal itu terjadi untuk sebuah urusan yang bersifat kebetulan dan tidak
sering dilakukan hingga menyita begitu banyak waktu dan tenaga, dan
lebih dekat kepada sebuah kondisi yang sangat penting/darurat untuk
menolak mafsadah/keburukan yang besar. Yang seperti ini tidak mengapa
dilakukan, bahkan terkadang menjadi sebuah hal yang wajib.
Dari sini
bisa dipahami perbedaan antara status dakwah (dakwah dalam makna yang
sebenarnya, bukan kepentingan lembaga dakwah itu) yang dianggap sebagai
sebuah sunnah/syari’at dan statusnya untuk menolak mafsadah.
Semoga
Allah menjaga para muslimah dari kepentingan tersembunyi yang ingin
mengeksploitasi diri dan agama mereka atas nama dakwah.
Wallahul musta’an.
———————
Footnotes :
[1] Diantarannya adalah perkataan Syaikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu,
“Hukum asalnya adalah berdiam di rumah. Itulah hukum asalnya. Dan
itulah yang paling selamat dan lebih utama dengan dalil firman Allah ‘azza wa jalla.
Karena (diamnya di rumahnya) itu menjauhkannya dari fitnah. Akan
tetapi, keluarnya dia untuk sebuah hajat dan keluarnya dia untuk
berdakwah kepada Allah, belajar, silaturrahim, menjenguk orang sakit
atau memberi takziyah kepada orang yang ditimpa musibah, semua ini tidak
mengapa dan disyari’atkan. Yang dbenci adalah keluarnya dia tanpa ada
hajat penting…” (Fatâwâ Nûr ‘alâ ad-Darb, no. 128).
Dakwah
yang beliau maksud adalah dakwah yang murni dakwah. Bukan aktivitas
organisasi yang kemudian disebut sebagai “dakwah” yang menguras seluruh
waktu, tenaga dan pikiran seorang wanita yang lemah hingga mengabaikan
kewajibannya dalam rumah.
Beliau
menyebut bolehnya keluar itu untuk sebuah hajat atau darurat. Dan sifat
darurat ditetapkan dengan kadarnya, bukan justru dimudah-mudahkan hingga
semua urusan dianggap sebagai hajat dan darurat.
[2] Disebutkan dalam Sirah Ibn Hisyam (III/32) dengan sanad munqathi’ (terputus) dan dalam Maghazi al-Waqidi (I/268), sementara al-Waqidi dha’îf jiddan (sangat lemah). Silahkan rujuk ke as-Sîrah an-Nabawiyyah ash-Shahîhah, II/390.
[3] Fathul Bâry (VI/78, VII/366), Syarh an-Nawawî ‘alâ Shahîh Muslim
(XII/189). Para ulama menjelaskan bahwa riwayat-riwayat tersebut
menunjukkan bolehnya memanfaatkan jasa para wanita dalam kondisi darurat
untuk mengobati dan merawat prajurit yang terluka jika keadaan aman
dari fitnah mereka dengan tetap menjaga hijabnya. Dan mereka boleh
mempertahankan diri dengan berperang jika musuh datang mengganggu
mereka.
27 Oktober 2015
Hadits Mursal
Menurut istilah, hadits al-mursal (المُرسل) adalah hadits yang gugur pada akhir sanadnya perawi yang setelah Tabi’iy.[1]
Perawi yang setelah tabi’iy adalah shahabiy[2]. Akhir dari sebuah sanad adalah penghujungnya yang padanya terdapat nama shahabat.
Contoh
Imam Muslim meriwayatkan dalam Shahih-nya dalam Kitâb al Buyû’, ia berkata,
حدثني
محمد بن رافع، ثنا حُجين، ثنا الليث، عن عُقيل، عن ابن شهاب، عن سعيد بن
المسيب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المزابنة
Telah
menceritakan kepadaku Muhammad bin Rafi’, ia berkata : Telah
menceritakan kepada kami Hujain, ia berkata : Telah menceritakan kepada
kami al-Laits, dari ‘Uqail, dari Ibnu Syihab, dari Sa’id bin
al-Musayyib, bahwa Rasulullah ﷺ melarang jual beli muzâbanah.[3]
Sa’id bin al-Musayyib adalah seorang Tabi’in senior. Ia telah meriwayatkan hadits ini dari Nabi ﷺ tanpa menyebutkan perantara antara dirinya dengan Nabi ﷺ . Ia telah menghilangkan perawi yang berada di akhir sanad, yaitu perawi yang setelah tabi’i. Minimal, as-saqth
(yang gugur) dalam sanad tersebut adalah seorang shahabat, dan
kemungkinan juga terdapat yang lainnya, yaitu tabi’i yang seperti Ibnul
Musayyib.
Hukum Hadits Mursal
Pada
asalnya, hadits mursal adalah hadits lemah yang tertolak, karena
hilangnya salah satu syarat diterimanya sebuah hadits yaitu ittishâl as-sanad (sanad yang bersambung), dan juga karena ketidakjelasan (jahâlah) keadaan perawi yang gugur dari sanad, karena bisa jadi perawi tersebut adalah bukan seorang shahabat.
Akan tetapi, para ulama dari kalangan ahli hadits dan yang selain mereka berselisih tentang hukum mursal. Jenis inqithâ’
(terputusnya sanad) ini berbeda dengan yang lainnya yang terjadi dalam
sanad. Karena yang hilang/gugur dari sanadnya umumnya adalah seorang
shahabat, dan seluruh shahabat adalah orang-orang yang terpercaya, dan
tidak disebutkannya nama mereka dalam sanad sama sekali tidak menjadi
celaan bagi ‘adâlah mereka.
Perselisihan para ulama tentang hukum hadits mursal bisa disimpulkan dalam tiga pendapat berikut,
1. Dha’if
dan tertolak, menurut pendapat mayoritas para ahli hadits, ulama ushul
dan ahli fiqh. Alasan mereka adalah dikarenakan jahâlah pada diri perawi yang tidak dsebutkan dalam sanad, dan juga kemungkinan bahwa ia bukanlah seorang shahabat.
2. Shahih
dan bisa dijadikan hujjah, menurut pendapat sebagian ulama, termasuk
para imam; Abu Hanifah, Malik dan Ahmad. Tetapi dengan syarat, mursil (orang yang melakukan irsâl) adalah seorang yang tsiqah
(sangat terpercaya), dan dia tidak meriwayatakan hadits mursal tersebut
kecuali dari orang yang tsiqah. Alasan mereka bahwa seorang tabi’in
tsiqah tidak mungkin mengatakan : “Bersabda Rasulullah ﷺ ” kecuali jika dia mendengarnya dari seorang yang tsiqah.
3. Diterima dengan beberapa syarat. Ini adalah pendapat Imam asy-Syafi’i dan beberapa ulama.
Syarat-syarat
tersebut ada empat; tiga pada diri perawi yang meriwayatkan mursal
tersebut dan satu pada haditsnya yang mursal. Yaitu,
a. Yang meriwayatkan hadits mursal tersebut adalah dari kalangan kibâr at-tâbi’în (tabi’in senior)
b. Jika
dia menyebutkan perawi yang dia riwayatkan mursal itu darinya, maka dia
akan menyebutkan nama seorang yang tsiqah. Jika dia ditanya tentang
perawi yang dia gugurkan dalam sanad, maka dia akan menyebutkan nama
seorang yang tsiqah.
c. Jika para perawi yang huffadz
dan terpercaya ikut meriwayatkan hadits bersamanya, maka mereka tidak
menyelisihinya dalam riwayat tersebut. Dalam makna, bahwa perawi itu
adalah seorang yang dhabth-nya sempurna.
d. Ditambahkan pada ketiga syarat tersebut hal-hal berikut ini :
- Haditsnya diriwayatkan dari jalan periwayatan yang lain secara musnad (bersambung)
- Atau,
haditsnya diriwayatkan dari jalan periwayatan yang lain secara mursal,
yang dia mengambilnya dari para perawi yang lain, yang bukan
perawi-perawi orang yang meriwayatkan mursal pertama
- Atau, haditsnya selaras dengan perkataan/pendapat seorang shahabat
- Atau, banyak dari para ulama yang telah berfatwa dengan konsekuensi hadits tersebut
Mursal Shahâbiy (المرسل الصحابيّ)
Mursal shahâbiy adalah hadits yang diriwayatkan seorang shahabat dari perkataan Nabi ﷺ
atau perbuatan beliau, namun shahabat itu tidak pernah mendengarkannya
secara langsung atau menyaksikannya. Entah karena usianya yang masih
kecil, atau keterlambatan keislamannya, atau ketidakhadirannya pada
kejadian tertentu. Yang seperti ini sangat banyak dari para shahabat
kecil (shighâr ash shahâbah) semisal Ibnu Abbas, Ibnu az-Zubair dan lain-lain.
Hukum Mursal Shahâbiy
Pendapat
yang paling shahih dan masyhur yang dipegang oleh jumhur ulama bahwa
hadits mursal yang diriwayatkan seorang shahabat adalah hadits shahih dan bisa dijadikan hujjah
(dalil). Karena, riwayat seorang shahabat dari seorang tabi’in
sangatlah jarang, dan andai pun seorang shahabat meriwayatkannya dari
seorang tabi’in, dia pasti akan menjelaskannya. Jika shahabat itu tidak
menjelaskannya dan berkata : “Bersabda Rasulullah ﷺ …”,
maka hukum asalnya ia mendengarkannya dari shahabat lainnya. Dan
dihapuskannya nama shahabat dari sebuah sanad tidaklah berpengaruh pada
keshahihan suatu riwayat.
Wallahu a’lam.
———————–
Footnotes :
[1] Tabi’iy (التابعيّ) adalah orang yang berjumpa dengan shahabat Nabi ﷺ dalam keadaan muslim dan wafat diatas Islamnya. Bentuk jama’nya adalah tâbi’ûn/tâbi’în (التابعون)
[2] Shahabiy (الصحابيّ) adalah orang yang berjumpa dengan Nabi ﷺ dalam keadaan muslim dan wafat diatas Islamnya, walaupun sempat diselingi oleh kemurtadan. Bentuk jama’nya adalah shahâbah (الصحابة)
[3]
Muzabanah adalah jual beli sesuatu tanpa memiliki kejelasan tentang
kadar takaran atau timbangannya, hanya dengan perkiraan dan persangkaan
(Sumber : Taysîr Mushthalah al Hadîts, ath-Thahhan)
24 Oktober 2015
Ujian yang Menimpa Rasul ﷺ dalam Fase Dakwah Jahriyah
Dimulainya fase dakwah secara terang-terangan telah menyebabkan kemarahan besar
dari pihak Quraisy. Keyakinan batil mereka yang telah diwariskan secara
turun temurun, sangat dipahami telah memberi faedah besar bagi Quraisy
dalam mewujudkan kepentingan sosial dan ekonomi mereka. Kepemimpinan
Quraisy terhadap Makkah dan Ka’bah yang dikelilingi oleh 360 berhala
telah memberikan keuntungan besar bagi para pembesar-pembesar Quraisy
melalui perdagangan dalam kedudukan Makkah sebagai jalur transit antara
Syam dan Yaman, dan juga penghormatan bangsa Arab terhadap Quraisy.
Karenanya, Quraisy melakukan segala cara yang mungkin untuk menghalangi
berkembangnya dakwah Islam di kalangan bangsa Arab.
Penindasan Quraisy terhadap Rasulullah ﷺ dan para shahabatnya dilakukan dengan berbagai macam cara, dari cacian secara terang-terangan sampai siksaan secara fisik.
Abdullah bin Mas’ud menceritakan : Ketika Rasulullah ﷺ
sedang berdiri shalat di sisi Ka’bah, dan sekelompok orang Quraisy
sedang berada di majelis mereka, seseorang diantara mereka berkata :
“Tidakkah kalian melihat kepada orang yang suka pamer itu? Siapa yang
akan pergi kepada ternak keluarga fulan, mengambil kotoran, darah dan
isi perutnya, dia datangkan, dan menunggu sampai orang itu sujud dan dia
letakkan diantara kedua pundaknya?” Maka berdirilah orang yang paling
celaka diantara mereka, dan ketika Rasulullah ﷺ bersujud, ia letakkan kotoran itu diantara pundak beliau. Nabi ﷺ
diam tetap bersujud, dan mereka tertawa sampai-sampai sebagiannya
miring kepada sebagian lainnya karena tertawa. Seseorang kemudian pergi
kepada Fathimah, saat itu Fathimah masih gadis kecil, dan ia datang dengan bersegera. Nabi ﷺ
tetap dalam sujudnya sampai Fathimah menyingkirkan kotoran itu, dan
kemudian Fathimah mendatangi mereka dan mencaci mereka. Ketika
Rasulullah ﷺ menyelesaikan shalatnya, beliau berdoa : “Ya Allah, balaslah Quraisy.. Ya Allah, balaslah Quraisy.. Ya Allah, balaslah Quraisy!!”
Kemudian beliau menyebut : “Ya
Allah, balaslah ‘Amr bin Hisyam, Utbah bin Rabi’ah, Syaibah bin
Rabi’ah, al-Walid bin Utbah, Umayyah bin Khalaf, Uqbah bin Abi Mu’ith
dan Umarah bin al-Walid!”
Berkata
Abdullah bin Mas’ud : Demi Allah! Aku telah melihat mereka tewas pada
hari perang Badar, kemudian diseret ke sumur, yaitu sumur Badar,
kemudian Rasulullah ﷺ bersabda : “Dan kutukan mengikut penghuni sumur.”[1]
Urwah bin
az-Zubair pernah bertanya kepada Abdullah bin ‘Amr bin al-‘Ash :
Ceritakan padaku hal terburuk yang pernah dilakukan orang-orang musyrik
terhadap Rasulullah ﷺ .
Abdullah berkata : Ketika Rasulullah ﷺ sedang shalat di pelataran Ka’bah, tiba-tiba datanglah Uqbah bin Abi Mu’ith. Ia memegang pundak Rasulullah ﷺ
dan melingkarkan kainnya di lehernya dan mencekiknya dengan kuat.
Datanglah Abu Bakr memegang pundak Uqbah dan mendorongnya dari
Rasulullah ﷺ sambil berkata,
أتَقْتُلُونَ رَجُلاً أن يَقولَ رَبّيَ الله وقدْ جَاءَكمْ بالبَيّنَاتِ مِن رَبِّكُمْ
“Apakah
kamu akan membunuh seorang laki-laki karena dia menyatakan : Rabbku
adalah Allah? Padahal dia telah datang kepadamu dengan membawa
keterangan-keterangan dari Rabbmu.” (QS. Ghafir ayat 28).[2]
Cacian dan ejekan terhadap Rasullah ﷺ
dan dakwahnya juga menjadi salah satu cara yang ditempuh orang-orang
musyrik dalam perang kata-kata untuk memalingkan manusia dari dakwah Islam.
Abu Jahl pernah berkata dengan mengejek : “Ya Allah, jika ini adalah
kebenaran dari sisiMu, maka turunkanlah kepada kami hujan batu dari
langit atau datangkan kepada kami azab yang pedih!” Maka turunlah ayat,
وَمَا
كانَ الله ليُعَذِبَهُم وَأنْتَ فِيْهِمْ وَمَا كانَ اللهُ مُعَذّبَهُم
وَهُمْ يَسْتغْفِرُونَ، وَمَا لَهُم ألا يُعَذِبَهمُ الله وَهُم يَصُدّونَ
عَن المَسْجدِ الحَرَامِ
“Dan
Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka sedang kamu berada diantara
mereka. Dan tidaklah (pula) Allah akan mengazab mereka, sedang mereka
meminta ampun. Kenapa Allah tidak mengazab mereka padahal mereka
menghalangi orang untuk (mendatangi) Masjidil Haram…” (QS. Al-Anfal ayat 33-34).[3]
Siksaan dan penindasan terhadap Rasulullah ﷺ
sampai pada usaha mereka untuk membunuhnya di akhir fase dakwah
makkiyah yang merupakan sebab utama terjadinya hijrah ke Madinah.
Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhuma : Sekelompok
Quraisy berkumpul di al-Hijr (Hijr Isma’il di Ka’bah), dan mereka
bersumpah atas nama al-Lat, al-‘Uzza dan Manat yang ketiga yang “Jika
kita melihat Muhammad, kita akan menyerangnya dengan sekali serang, dan
kita tidak akan melepaskannya sampai membunuhnya!”
Fathimah
datang dengan menangis dan masuk kepada ayahnya. Ia berkata : “Mereka
itu dari kaummu di al-Hijr telah bersumpah jika mereka melihatmu, mereka
akan menyerang dan membunuhmu. Tidak ada seorang pun dari mereka
melainkan dia sudah mengetahui bagiannya dari darahmu.”
Beliau berkata : “Wahai putriku, dekatkan untuk ayah air wudhu itu!”
Beliau
berwudhu kemudian mendatangi mereka di Masjid (al-Haram). Ketika
melihatnya, mereka berkata : “Itu dia!”, dan mereka menundukkan
pandangan mereka. Mereka diam di tempat-tempat duduk mereka dan sama
sekali tidak mengangkat pandangan mereka. Tidak seorang pun dari mereka
yang berdiri.
Rasulullah ﷺ datang sampai beliau berdiri diatas kepala-kepala
mereka. Beliau mengambil segenggam tanah dan menaburkannya sambil
berkata : “Wajah-wajah yang buruk!”
Berkata
Ibnu Abbas : Tidaklah debu menimpa salah seorang dari mereka melainkan
orang itu terbunuh di hari perang Badar dalam keadaan kafir.[4] Peristiwa seperti ini -yaitu beliau menaburkan pasir ke wajah-wajah orang-orang kafir- kembali berulang di malam hijrah.
Jika saja demikian kelancangan Quraisy terhadap Rasulullah ﷺ
yang sangat dihormati dan memiliki kedudukan di kaumnya, maka bagaimana
lagi dengan keadaan para Shahabat yang mulia? Terutama orang-orang
lemah diantara mereka.
Kami akan sebutkan –insyaallah- sebagian
dari kisah mereka sebagai “hiburan” bagi para da’i yang mengajak kepada
Allah di zaman yang penuh dengan ujian kemewahan hidup, yang barangkali
saja mampu sedikit mengokohkan kaki-kaki mereka diatas jalan ini, dan
memberikan mereka sedikit kekuatan. Wallahul musta’an.
—————————
Footnotes :
[1] HR. Al-Bukhary dan Muslim
[2] HR. Al-Bukhary
[3] HR. Al-Bukhary dan Muslim
[4] HR. Ahmad dengan dua sanad yang shahih sebagaimana disebutkan Ahmad Syakir
[2] HR. Al-Bukhary
[3] HR. Al-Bukhary dan Muslim
[4] HR. Ahmad dengan dua sanad yang shahih sebagaimana disebutkan Ahmad Syakir
20 Oktober 2015
Mengagungkan Tokoh Wali & Orang Shalih dengan Gambar
Sebagaimana
yang telah diketahui bahwa permulaan terjadinya syirik di muka bumi ini disebabkan oleh
sikap ghuluww (berlebihan) terhadap orang-orang shalih dengan menvisualisasikan
mereka dalam bentuk patung dan gambar sebagaimana yang terjadi pada kaum Nuh 'alaihissalam.
Karena besarnya bahaya patung dan gambar serta besarnya dosa orang yang membuatnya, maka dalil-dalil shahih sangat keras mengecam orang-orang yang
membuat gambar atau patung makhluk bernyawa yang menunjukkan haramnya
perkara tersebut dengan segala bentuknya.[1]
Diantara dalilnya adalah sabda Nabi ﷺ ,
إن أشد الناس عذابًا يوم القيامة المصورون
“Sesungguhnya orang yang paling keras siksanya pada Hari Kiamat adalah orang-orang membuat gambar/patung.” (HR. Al-Bukhary dan Muslim).
Diriwayatkan
dari Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhuma bahwa seorang laki-laki mendatanginya dan berkata, “Aku
orang yang suka menggambar gambar-gambar ini, berilah fatwa tentang
ini.” Ibnu Abbas berkata padanya, “Saya mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,
كل مصور فى النار يجعل بكل صورة صورها نفسًا فتعذبه فى جهنم
‘Setiap
orang yang menggambar berada di Neraka. Dijadikan untuknya nyawa pada
setiap gambar yang digambarnya, yang akan menyiksanya di Jahannam.’
Jika engkau mesti melakukannya, gambarlah pepohonan dan apa yang tidak memiliki nyawa.” (HR. Al-Bukhary dan Muslim).
Diriwayatkan
dari Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu 'anhu bahwa ia berkata kepada Abu al-Hayyaj
al-Asadi, “Tidakkah aku mengutusmu dengan apa yang dahulu aku diutus
oleh Rasulullah ﷺ ? Jangan engkau
biarkan sebuah gambar/patung melainkan engkau hancurkan, dan (jangan
biarkan) sebuah kubur yang tinggi melainkan engkau ratakan.” (HR.
Muslim).
Karenanya,
selayaknya seorang muslim tidak meremehkan persoalan gambar dengan
segala jenisnya, baik itu yang berbentuk tubuh seperti patung atau yang semacamnya yang memiliki bayangan atau apa yang ada pada dinding,
pahatan kayu dan lain-lain. Dan lebih besar lagi dosa berkait patung atau gambar tersebut jika dia adalah patung atau gambar seorang tokoh agama yang dihormati dan diagungkan yang memiliki kedudukan di hati-hati manusia.[2]
(Disadur dari Tahdzîb Tashîl al Aqîdah al Islâmiyyah)
——————
Footnotes :
[1]
Ulama di masa sekarang berbeda pendapat tentang hukum fotografi, yaitu
pengambilan gambar dengan menggunakan kamera. Sebagian tetap
mengharamkan kecuali apa yang dalam status darurat karena sangat
dibutuhkan, sementara sebagian lainnya memandang bahwa fotografi tidak
termasuk dalam jenis gambar yang diharamkan.
Demikian
pula sebagian ulama berpendapat bahwa gambar film video tidaklah masuk
kategori gambar yang diharamkan. Sementara sebagian lainnya tetap dengan
memandang keharamannya dengan keumuman dalil pelarangan, dan sebagian
mengecualikan apa yang padanya ada maslahat syar’i.
[2] Imam Ibnul Arabi al-Maliki menukil ijma’ (kesepakatan ulama) tentang haramnya gambar replika. (‘Âridhah al-Ahwadzi, VII/253, Kitab al-Libâs).
Sebagian ulama mengecualikan darinya permainan anak-anak jika gambarnya berbentuk umum, tidak digambarkan secara mendetail.
Yang menjadi patokan dalam pengharaman gambar/patung adalah kepala/wajah, dengan dalil hadits,
الصورة الرأس
“Gambar (yang diharamkan) adalah kepala (wajah).” (Diriwayatkan oleh al-Isma’iliy dalam Mu’jamnya, dan dishahihkan oleh al-Albani dalam ash-Shahihah)
15 Oktober 2015
Puasa di Bulan Muharram dan Hari Asyura'
Bulan Muharram adalah salah satu dari bulan-bulan Haram yang Allah maksudkan dalam firmanNya,
إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْراً فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلاَ تَظْلِمُوا فِيْهِنَّ أَنْفُسَكُمْ
"Sesungguhnya bilangan bulan pada
sisi Allah adalah dua belas bulan, dalam ketetapan Allah di waktu Dia
menciptakan langit dan bumi, diantaranya empat bulan Haram. Itulah
(ketetapan) agama yang lurus, maka janganlah kamu menganiaya diri kamu
dalam bulan yang empat itu." (QS. At-Taubah : 36).
Dan Nabi ﷺ bersabda,
Dan Nabi ﷺ bersabda,
السنة اثنا عشر شهراً منها أربعة حرم ، ثلاث متواليات : ذو القعدة ، وذو الحجة ، والمحرم ، ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان
"Satu tahun terdiri dari dua belas
bulan, diantaranya empat bulan Haram; tiga berurutan (yaitu) Dzulqi'dah,
Dzulhijjah dan Muharram, serta Rajab Mudhar yang diantara bulan Jumada
dan Sya'ban." (HR. Al-Bukhary dan Muslim).
Bulan-bulan Haram adalah bulan-bulan yang dihormati dan diagungkan dalam Syari'at dan diharamkan berperang di bulan-bulan tersebut kecuali untuk menolak serangan.
Berkait dengan bulan Muharram, disyari'atkan memperbanyak puasa di bulan tersebut, dengan dalil sabda Nabi ﷺ ,
Berkait dengan bulan Muharram, disyari'atkan memperbanyak puasa di bulan tersebut, dengan dalil sabda Nabi ﷺ ,
أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم
"Seutama-utama puasa setelah Ramadhan adalah bulan Allah, al-Muharram." (HR. Muslim).
Dan di bulan Muharram terdapat hari Asyura', yaitu hari kesepuluhnya, yang disunnahkan dan sangat ditekankan untuk berpuasa padanya.
Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu 'anhuma ia berkata, "Saya tidak melihat Nabi ﷺ sangat peduli dengan puasa pada hari tertentu yang ia utamakan dari yang selainnya kecuali di hari ini, yaitu hari Asyura', dan bulan ini yaitu bulan Ramadhan." (HR. Al-Bukhary dan Muslim).
Berpuasa pada hari Asyura' memiliki keutamaan yang sangat besar. Nabi ﷺ bersabda,
Dan di bulan Muharram terdapat hari Asyura', yaitu hari kesepuluhnya, yang disunnahkan dan sangat ditekankan untuk berpuasa padanya.
Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu 'anhuma ia berkata, "Saya tidak melihat Nabi ﷺ sangat peduli dengan puasa pada hari tertentu yang ia utamakan dari yang selainnya kecuali di hari ini, yaitu hari Asyura', dan bulan ini yaitu bulan Ramadhan." (HR. Al-Bukhary dan Muslim).
Berpuasa pada hari Asyura' memiliki keutamaan yang sangat besar. Nabi ﷺ bersabda,
صيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يُكفّر السنة التي قبله
"Puasa pada hari Asyura', aku mengharapkan pada Allah agar Dia berkenan menghapuskan dosa setahun yang sebelumnya." (HR. Muslim).
Dan hukum puasanya adalah sunnah mu'akkadah dan tidak diwajibkan. Nabi ﷺ bersabda ,
Dan hukum puasanya adalah sunnah mu'akkadah dan tidak diwajibkan. Nabi ﷺ bersabda ,
إن عاشوراء يوم من أيام الله ، فمن شاء صامه ومن شاء تركه
"Sesungguhnya Asyura' adalah satu
hari dari hari-hari Allah. Siapa yang ingin maka hendaknya dia berpuasa
padanya, dan siapa yang ingin dia boleh meninggalkannya." (HR. Muslim).
Dan disebutkan dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu 'anha, ia berkata, "Asyura' adalah satu hari yang orang-orang Quraisy berpuasa padanya di masa Jahiliyyah. Dahulu Nabi ﷺ berpuasa padanya. Ketika beliau datang ke Madinah, beliau berpuasa Asyura' dan menyuruh (kaum muslimin) berpuasa. Ketika turun (kewajiban) puasa Ramadhan, maka siapa yang ingin ia berpuasa Asyura', dan siapa yang ingin ia boleh tidak melaksanakannya." (HR. Al-Bukhary).
Dan bersama dengan puasa Asyura' tersebut, disunnahkan pula berpuasa sehari sebelumnya, di hari kesembilan, dengan dalil hadits Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhuma, ia berkata,
Dan disebutkan dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu 'anha, ia berkata, "Asyura' adalah satu hari yang orang-orang Quraisy berpuasa padanya di masa Jahiliyyah. Dahulu Nabi ﷺ berpuasa padanya. Ketika beliau datang ke Madinah, beliau berpuasa Asyura' dan menyuruh (kaum muslimin) berpuasa. Ketika turun (kewajiban) puasa Ramadhan, maka siapa yang ingin ia berpuasa Asyura', dan siapa yang ingin ia boleh tidak melaksanakannya." (HR. Al-Bukhary).
Dan bersama dengan puasa Asyura' tersebut, disunnahkan pula berpuasa sehari sebelumnya, di hari kesembilan, dengan dalil hadits Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhuma, ia berkata,
حِينَ صَامَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللّهِ: إِنَّهُ يَوْمٌ تُعَظِّمُهُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ. فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم : فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ، إِنْ شَاءَ اللّهُ، صُمْنَا الْيَوْمَ التَّاسِعَ . قَالَ: فَلَمْ يَأْتِ الْعَامُ الْمُقْبِلُ، حَتَّىٰ تُوُفِّيَ رَسُولُ اللّه صلى الله عليه وسلم
Ketika Rasulullah ﷺ berpuasa pada hari Asyura' dan menyuruh berpuasa (padanya), mereka berkata, "Wahai Rasulullah, hari itu adalah hari yang diagungkan Yahudi dan Nasrani." Maka Rasulullah ﷺ bersabda, "Jika datang tahun depan, kita akan berpuasa pada hari kesembilan." Berkata Ibnu Abbas : Dan belum tiba tahun berikutnya hingga Rasulullah ﷺ wafat. (HR. Muslim).
Hukum puasa pada hari kesembilan itu juga sunnah. Jika seseorang luput darinya puasa hari kesembilan, dan ia hanya berpuasa pada hari kesepuluh saja, hal itu tidak mengapa dan bukan perkara yang makruh (dibenci) dalam agama Allah.
Sebagian ulama menyebutkan sunnahnya
untuk berpuasa pada sehari sebelum dan sehari sesudah hari Asyura' (yaitu
tanggal 9 dan 11 Muharram), dengan berdalilkan apa yang diriwayatkan
dari Ibnu Abbas secara marfu',
صوموا يوم عاشوراء وخالفوا اليهود،
وصوموا قبله يوماً و بعده يوماً
"Berpuasalah pada hari Asyura' dan selisihilah orang-orang Yahudi. Berpuasalah sehari sebelumnya dan sehari sesudahnya." (HR. Ahmad dan Ibnu Khuzaimah).
Hadits ini diperselisihkan keshahihannya oleh para ulama. Syaikh Ahmad Syakir menilainya sebagai hadits hasan. Tapi para pen-tahqiq Musnad Imam Ahmad menganggapnya lemah (dha'if).
Hadits ini diperselisihkan keshahihannya oleh para ulama. Syaikh Ahmad Syakir menilainya sebagai hadits hasan. Tapi para pen-tahqiq Musnad Imam Ahmad menganggapnya lemah (dha'if).
Imam Ibnu Khuzaimah juga meriwayatkannya dengan redaksi yang sama, dan Syaikh Al-Albani berkata, "Sanadnya lemah, karena buruknya hafalan Ibnu Abi Laila. Atha' dan yang lainnya menyelisinya dan meriwayatkannya dari Ibnu Abbas dengan jalan periwayatan yang mauquf, dan sanadnya shahih dalam riwayat ath-Thahawi dan al-Baihaqi."
Sangat baik jika kita mencukupkan amalan dengan apa yang telah disepakati keshahihannya, namun jika ada yang ingin mengamalkan puasa pada hari kesembilan dan kesebelas bersama dengan puasa hari Asyura', maka -wallahu a'lam- hadits lemah yang seperti ini termasuk hadits-hadits yang diberikan toleransi oleh para ulama untuk mengamalkannya, karena kelemahannya relatif ringan dan masuk dalam keutamaan amal (fadha-il al a'mal).
Tidak mengapa orang yang berpuasa pada hari kesebelas meniatkannya sebagai puasa mutlak pada bulan Muharram karena Rasulullah ﷺ telah menganjurkan berpuasa pada bulan Muharram, atau mengamalkannya untuk kehati-hatian sebagaimana yang disebutkan sebagian ulama. Terlebih di zaman sekarang banyak dari kita yang tidak mengetahui hasil ru'yah hilal Muharram kecuali melalui hitungan kalender. Imam Ahmad rahimahullahu berkata, "Siapa yang ingin berpuasa Asyura' maka berpuasalah pada hari kesembilan dan kesepuluh. Kecuali jika bulan itu bermasalah (buatnya), maka dia berpuasa tiga hari. Ibnu Sirin menyebutkan hal tersebut." (Al-Mughni, IV/441).
Sangat baik jika kita mencukupkan amalan dengan apa yang telah disepakati keshahihannya, namun jika ada yang ingin mengamalkan puasa pada hari kesembilan dan kesebelas bersama dengan puasa hari Asyura', maka -wallahu a'lam- hadits lemah yang seperti ini termasuk hadits-hadits yang diberikan toleransi oleh para ulama untuk mengamalkannya, karena kelemahannya relatif ringan dan masuk dalam keutamaan amal (fadha-il al a'mal).
Tidak mengapa orang yang berpuasa pada hari kesebelas meniatkannya sebagai puasa mutlak pada bulan Muharram karena Rasulullah ﷺ telah menganjurkan berpuasa pada bulan Muharram, atau mengamalkannya untuk kehati-hatian sebagaimana yang disebutkan sebagian ulama. Terlebih di zaman sekarang banyak dari kita yang tidak mengetahui hasil ru'yah hilal Muharram kecuali melalui hitungan kalender. Imam Ahmad rahimahullahu berkata, "Siapa yang ingin berpuasa Asyura' maka berpuasalah pada hari kesembilan dan kesepuluh. Kecuali jika bulan itu bermasalah (buatnya), maka dia berpuasa tiga hari. Ibnu Sirin menyebutkan hal tersebut." (Al-Mughni, IV/441).
Wallahu a'lam.
12 Oktober 2015
Firqah Al-Mu'tazilah
Sebelum munculnya Mu’tazilah sebagai sebuah firqah
(sekte) pemikiran di tangan Washil bin Atha’, telah terjadi perdebatan
yang merupakan bibit awal pemikiran Mu’tazilah. Perdebatan tersebut
beredar pada persoalan-persoalan berikut,
- Perkataan bahwa manusia sepenuhnya bebas dan dialah yang menciptakan perbuatannya sendiri. Pendapat ini dimunculkan oleh Ma’bad al-Juhani yang ikut dalam pemberontakan Abdurrahman bin al-Asy’ats terhadap pemerintahan Abdul Malik bin Marwan. Ma’bad dibunuh oleh al-Hajjaj pada tahun 80 H setelah gagalnya pemberontakan tersebut. Pendapat ini pula yang disebutkan oleh Ghailan ad-Dimasyqi pada masa Umar bin Abdil Aziz, dan ia dibunuh oleh Hisyam bin Abdil Malik.
- Perkataan bahwa al-Quran adalah makhluk dan penolakan terhadap sifat-sifat Allah Ta’ala. Pemikiran ini dibawa oleh al-Jahm bin Shofwan, dan ia dibunuh oleh Salim bin Ahwaz di Merv pada tahun 128 H.
- Diantara orang-orang yang mendakwakan penolakannya terhadap sifat-sifat Allah adalah al-Ja’ad bin Dirham yang dibunuh oleh Khalid bin Abdillah al-Qusari, gubernur Bani Umayyah di Kufah.
Setelah
itu, muncullah Mu’tazilah sebagai sebuah sekte pemikiran melalui Washil
bin ‘Atha al-Ghazzal (80-131 H) yang dahulunya merupakan murid al-Hasan
al-Bashri, kemudian ia berpisah dari majelis al-Hasan setelah
mengemukakan pendapatnya bahwa pelaku dosa besar berada pada satu
diantara dua kedudukan/status (manzilah baina al manzilatain) yaitu bukan
mukmin dan bukan pula kafir, dan dia kekal di Neraka jika belum
bertaubat sebelum kematiannya. Firqah Mu’tazilah yang dinisbatkan
pada Washil bin 'Atha disebut al-Washiliyah.
Karena
prinsipnya yang sangat mengagungkan akal dalam memahami
persoalan-persoalan aqidah, Mu’tazilah terpecah ke dalam banyak sekte
walaupun semuanya sepakat dalam 5 prinsip pokoknya yang akan dijelaskan.
Setiap sekte akan datang dengan bid’ah baru yang membuatnya berbeda
dari sekte lainnya, dan menisbatkan dirinya dengan tokohnya.
Pada masa pemerintahan Abbasiyah, Mu’tazilah muncul di masa pemerintahan al-Ma’mun,
ketika ia menganut paham tersebut melalui Bisyr al-Mirrisi, Tsumamah bin
Asyras dan Ahmad bin Abi Du’ad. Nama terakhir ini merupakan seorang
tokoh bid’ah mazhab i’tizâl di zamannya, biang dari munculnya fitnah perkataan bahwa al-Quran adalah makhluk dan menjabat hakim agung di masa al-Mu’tashim.
Di masa
fitnah tersebut, Imam Ahmad telah menolak perintah al-Ma’mun untuk
mengakui bid’ah ini. Ia akhirnya dipenjara, disiksa dan dicambuk
pada masa al-Mu’tashim setelah wafatnya al-Ma’mun. Imam Ahmad berdiam di
penjara selama dua setengah tahun dan kemudian dikembalikan ke
rumahnya. Beliau berstatus sebagai "tahanan rumah" sepanjang pemerintahan
al-Mu’tashim dan putranya, al-Watsiq.
Ketika
al-Mutawakkil memangku jabatan khilafah (232 H), ia membela Ahlussunnah,
memuliakan Imam Ahmad dan menghentikan masa kekuasaan Mu’tazilah dalam
pemerintahan dan usaha mereka untuk memaksakan aqidahnya dengan kekuatan
selama masa 14 tahun.
Pada masa
kerajaan Syiah, Bani Buwaih tahun 334 H di Persia, semakin eratlah
hubungan antara Syiah dan Mu’tazilah. Mu’tazilah semakin mendapatkan
tempat di bawah naungan kerajaan ini. Ditunjuklah al-Qadhi Abdul Jabbar,
tokoh senior Mu’tazilah di masanya sebagai qadhi (hakim) Ray
pada tahun 360 H dengan perintah ash-Shahib bin Abbad, perdana menteri
Mu’ayyid ad-Daulah al-Buwaihi, dan ia tergolong penganut Rafidhah dan sekaligus penganut paham Mu'tazilah.
Setelah itu, hampir saja pemikiran i’tizâl
hilang sebagai sebuah pemikiran tersendiri, selain apa yang diambil dan
diyakini oleh sebagian sekte-sekte Syiah dan lainnya dari
pemikiran-pemikiran mereka.
Pada masa sekarang, pemikiran i’tizal
kembali dihidupkan oleh sebagian penulis dan pemikir yang tergolong
dalam neo-Mu’tazilah yang sangat mengagungkan dan memuliakan
akal/logika.
Pokok Utama Keyakinan Mu'tazilah
Pada permulaannya, Mu’tazilah datang dengan dua pemikiran bid’ah;
Pertama,
perkataan bahwa seorang manusia memiliki pilihan secara mutlak dalam
setiap perbuatannya, dan dialah yang menciptakan perbuatannya itu.
Diantara tokoh yang sangat menonjol dalam pemikiran ini pada
permulaannya adalah Ghailan ad-Dimasyqi di masa pemerintahan Umar bin
Abdil Aziz hingga masa Hisyam bin Abdil Malik. Ia dibunuh oleh Hisyam
disebabkan bid’ahnya tersebut.
Kedua, perkataan bahwa pelaku dosa besar bukanlah mukmin dan bukan pula kafir, akan tetapi fasik. Dia berada diantara dua kedudukan (manzilah baina al-manzilatain).
Demikianlah keadaannya di dunia. Adapun di Akhirat, maka dia tidak akan
pernah masuk Surga karena dia tidak beramal dengan amal ahli Surga,
bahkan dia kekal dalam Neraka. Menurut mereka, tidak ada halangan untuk
menyebut orang itu “muslim” dari sisi lahirnya dan mengucapkan syahadatain, akan tetapi dia tidak bisa disebut “mukmin”.
Kemudian setelah itu, Mu’tazilah menetapkan dan menyepakati mazhab mereka dalam lima prisip dasar yaitu at-tauhîd, al-‘adl (keadilan), al-wa’d wa al-wa’îd (janji dan ancaman), al-manzilah baina al-manzilatain dan al-amr bil ma’rûf wa an-nahy ‘anil munkar.
1. At-Tauhîd
Ringkasnya
menurut pandangan bid’ah mereka; Allah Ta’ala harus disucikan dari
penyerupaan dengan makhlukNya, tidak ada seorang pun yang menandingi Dia
dalam kekuasaanNya dan tidak berlaku baginya apa yang berlaku bagi para hamba. Ungkapan seperti ini adalah kebenaran, akan tetapi mereka membangun
diatasnya keyakinan yang batil, diantaranya bahwa Allah tidak bisa
dilihat pada Hari Kiamat karena konsekuensinya adalah menafikan
(meniadakan) sifat, dan sifat itu bukanlah sesuatu selain Dzat-Nya,
karena –menurut mereka- jika tidak demikian, maka Dzat yang qadim
(terdahulu tanpa permulaan) tersebut akan berbilang. Karenanya mereka
tergolong kelompok yang mengingkari sifat-sifat Allah Ta’ala. Demikian
juga, dengan pemikiran batilnya itu mereka mengambil kesimpulan bahwa
al-Quran adalah makhluk ciptaan Allah karena mereka menafikan dariNya
sifat al-Kalam (berbicara).
2. Al-‘Adl
Maknanya
menurut mereka bahwa Allah tidak menciptakan perbuatan para hamba, dan
Dia juga tidak menyukai kerusakan. Bahkan, para hamba itu melakukan apa
yang mereka perintahkan sendiri dan berhenti dari apa yang mereka larang
sendiri dengan qudrah (kemampuan) yang Allah jadikan dan adakan
dalam diri-diri mereka. Dia tidak memerintahkan kecuali dengan apa yang
Dia inginkan dan tidak melarang kecuali dari apa yang Dia benci. Dia
adalah pelindung bagi setiap kebaikan yang diperintahkanNya dan berlepas dari setiap keburukan yang dilarangNya. Dia tidak membebankan
kepada para hamba kecuali apa yang mereka mampu dan Dia tidak
menginginkan dari mereka selain apa yang ada dalam upaya dan kemampuan
mereka. Pendapat seperti ini muncul karena rancunya mereka dalam
membedakan antara iradah (kehendak) Allah al-kauniyyah dan iradahNya yang syar'i (al-iradah as-syar’iyyah).
3. Al-Wa’d wa Al-Wa’îd
Yang
mereka maksudkan dengan prinsip ini bahwa Allah akan memberi balasan
kebaikan kepada orang yang melakukan kebaikan dan membalas pelaku
keburukan dengan keburukan, dan Dia sekali-kali tidak akan mengampuni bagi pelaku
dosa besar kecuali jika dia bertaubat.
4. Al-Manzilah baina Al-Manzilatain
Yaitu
keyakinan mereka bahwa pelaku dosa besar berada pada satu kedudukan
antara iman dan kekafiran, bukan mukmin dan bukan pula seorang yang
kafir. Aqidah ini telah ditetapkan sejak permulaan oleh syaikh
Mu’tazilah, Washil bin Atha’.
5. A-Amr bi Al-Ma’rûf wa An-Nahy ‘an Al-Munkar
Mereka
telah menetapkan wajibnya perkara ini bagi orang-orang mukmin dalam
rangka menyebarkan dakwah Islam, hidayah bagi orang yang sesat dan
petunjuk bagi orang yang lalai, setiap orang sesuai dengan kemampuannya;
yang memiliki penjelasan dengan penjelasannya, seorang alim dengan
ilmunya, yang memiliki senjata dengan senjatanya, dan seterusnya. Akan
tetapi, hakikat dari prinsip ini sebenarnya adalah perkataan mereka
tentang wajibnya memberontak terhadap penguasa muslim jika dia telah
menyelisihi dan menyimpang dari kebenaran!
Diantara
prinsip pokok aqidah Mu’tazilah adalah bersandar sepenuhnya kepada akal
dalam berargumen terhadap aqidah yang mereka yakini. Dan diantara akibat
buruknya dari perkara ini, mereka menghukumi baik buruknya sesuatu
dengan akal mereka. Demikian pula mereka menta’wil (menafsirkan)
sifat-sifat Allah dengan apa yang mereka anggap cocok dengan akalnya.
Dan sudah dimaklumi bahwa Mu’tazilah menafikan seluruh sifat-sifat Allah
Ta’ala.
Karena pengagungan terhadap akal itu juga sehingga tokoh-tokoh mereka berani
mencaci para pembesar Shahabat dan menuduh mereka berdusta. Washil bin
Atha’ mendakwakan bahwa salah satu dari dua kelompok yang terlibat dalam
perang Jamal adalah fasik. Entah kelompok Ali bin Abi Thalib, Ammar bin
Yasir, al-Hasan, al-Husain dan Abu Ayyub, atau kelompok Aisyah, Thalhah
dan az-Zubair. Mereka bahkan menolak persaksian para Shahabat yang
mulia tersebut dengan mengatakan, “Persaksian mereka tidak diterima!”.
Disebabkan
oleh ketergantungan mereka kepada akal dan jauhnya mereka dari
dalil-dalil shahih yang bersumber dari al-Quran dan as-Sunnah, mereka
pun terpecah kedalam banyak firqah (sekte).
Demikianlah
Mu’tazilah, mereka telah mengubah agama ini kepada kumpulan persoalan
rasio dan argumen-argumen mantiq, disebabkan pengaruh besar yang masuk
dalam keyakinan mereka yang berasal dari filsafat Yunani, terkhusus
mantiq Arsitoteles.
Wallahu a’lam.
------------------------
Sumber tulisan : Al Mausû’ah al Muyassarah fî al Adyân wa al Madzâhib wa al Ahzâb al Mu’âshirah, WAMY, cet. tahun 1424.
09 Oktober 2015
Ketika Muslimah Keluar Rumah untuk “Dakwah”
Seorang
wanita ketika benar ia telah mendapat hidayah dan berubah menjadi salah
seorang “akhawat muslimah”, maka yang mesti menjadi obsesinya adalah
berdiam di rumahnya, belajar untuk menjadi wanita sejati yang
profesional dalam rumahnya (bukan justru lebih hebat di luar) serta
melayani dan mengurus suami dan anak-anaknya jika ia sudah menikah
sebagai wujud ibadah dan kepatuhannya kepada perintah Allah Ta’ala.
Tapi
sebuah fakta yang sangat aneh di zaman ini dari banyak pergerakan Islam,
hampir tidak ada perbedaan antara wanita yang awam dengan wanita yang
“telah mendapatkan hidayah” itu. Kecuali sedikit saja “perbedaan” dalam
pemahaman dan gaya berpakaian saat keluar rumah.
Wanita
“yang telah mendapatkan hidayah” itu justru lebih semangat keluar rumah,
sangat aktif di luar rumah dan rela menyibukkan diri mengurus orang
lain –dan anehnya- dengan anggapan dan keyakinan bahwa itu adalah sebuah
“pengorbanan” yang mengatasnamakan Allah, Islam dan dakwah (?!).
Sebagian
suami “yang tertipu” bahkan berbangga dengan aktivitas istrinya itu dan
mendorong orang lain melakukannya –juga katanya- untuk kebaikan Islam
dan dakwah.
Kalau
benar mereka taat kepada aturan Allah, maka Allah telah menyuruh wanita
untuk berdiam di rumah. Bagaimana bisa kemudian ada “pemikiran” atau
“dalih” yang lebih baik dari perintah Allah dan –hebatnya lagi-
mengatasnamakan agama Allah.
Berdiam di
rumah adalah sebuah ibadah agung bagi seorang wanita, karena Allah
telah memerintahkan hal itu dalam Kitab Suci-Nya. Sementara pemikiran
sebagian orang, entah dia seorang ustadz atau siapapun, adalah sekedar
pemikiran yang tidak bisa dibenturkan dengan dalil.
Allah Ta’ala berfirman,
وقَرْنَ فى بُيُوْتِكُنَّ وَلا تَبَرّجْنَ تَبَرّجَ الجَاهِلِيّةِ الأوْلىَ
“Dan berdiamlah kamu di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu.” (QS. Al-Ahzab ayat 33).
Benar apa
yang dikatakan Syaikh Al-Albani rahimahullahu, “Karena kaum lelaki tidak
menunaikan kewajibannya, hingga akhirnya medan perjuangan itu kosong,
dan kemudian dibayangkan pada sebagian wanita bahwa tidak boleh tidak,
kita mesti mengisi kekosongan tersebut”. (Az Zawâj fi al Islâm).
Ya,
“kehebatan” banyak aktivis “dakwah” wanita di zaman ini justru semakin
melemahkan kaum laki-laki. Di banyak pergerakan, kaum wanitalah yang
justru lebih dominan, dan terkesan para lelaki itu bergantung kepada
wanita dalam urusan jumlah pengikut dakwah mereka.
Dakwah
adalah kewajiban setiap muslim, laki-laki maupun wanita. Tapi secara
sengaja mengorganisir atau memobilisasi kaum wanita untuk keluar rumah
atas nama dakwah (baca : lembaga/organisasi) adalah bid’ah yang tidak
pernah dicontohkan oleh Rasulullah ﷺ dan para Salaf radhiyallahu ‘anhum.
Jangan
tertipu dengan “manfaat” tersebarnya dakwah dan terselamatkannya banyak
wanita dengan dakwah tersebut yang sering mereka dengungkan, karena
mendatangkan manfaat tidak dengan cara yang bertentangan dengan aturan
Allah Ta’ala dan petunjuk rasul-Nya.
Terimalah kebenaran, walaupun pahit terasa.
Wallahul musta’an.
06 Oktober 2015
Asuransi Kesehatan
Nadwah (simposium) Majma’ al-Fiqh al-Islami di India (Islamic Fiqh Academy India) memutuskan dalam persoalan asuransi kesehatan sebagai berikut,
Syari’at tidak membolehkan perjudian (qimâr)
dengan segala bentuknya. Dan asuransi kesehatan yang berkembang pada
hari ini masuk dalam kategori perjudian ditinjau dari hasil akhir
(sistem tersebut), yaitu mengubah maksud pengobatan dari bentuk
pelayanan kepada komersialisasi yang mendatangkan keuntungan. Dengan
kenyataan ini maka al-Majma’ menetapkan hal-hal berikut ini,
Pertama;
Asuransi kesehatan sama seperti jenis-jenis asuransi lainnya, yang
mengandung perkara-perkara yang diharamkan dalam tinjauan syar’i. Tidak
boleh memanfaatkannya dalam kondisi normal. Dan tidak ada perbedaan
hukum antara lembaga-lembaga asuransi pemerintah atau swasta.
Kedua;
Dalam kondisi terpaksa yang diatur oleh undang-undang (negara),
asuransi kesehatan itu boleh, akan tetapi wajib bagi orang yang mampu
jika mengambil manfaat pengobatan melebihi dana (premi yang dibayarkan)
untuk bersedekah sesuai dengan nilai dana tersebut tanpa meniatkan
pahala (dari sedekah itu).
Ketiga;
Memungkinkan untuk menyediakan alternatif islami bagi asuransi
kesehatan. Maka wajib bagi kaum muslimin untuk mendirikan lembaga yang
seperti itu, yang bertujuan untuk mengobati dan membantu orang-orang
yang membutuhkan.
Ketetapan no. 64 (15/2), tahun 1427 H/2006 M
03 Oktober 2015
Hadits Mu’allaq
Seperti
yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, hadits mardûd (yang tertolak) secara garis besar disebabkan oleh dua hal; yang pertama
adalah perawi yang gugur dalam sanad (as saqth min al isnâd), dan yang kedua adalah celaan pada diri sang perawi (ath tha’n fi ar râwi).
As-saqth min al-isnâd terbagi kepada saqth dzhâhir dan saqth khafiy. Dan diantara bentuk saqth dzhâhir adalah al-mu’allaq.
Hadits al-mu’allaq (المعلق) adalah hadits yang gugur sejak permulaan sanadnya seorang perawi atau lebih secara berurutan.
Permulaan
sanad adalah ujung yang terdekatnya dari arah kita, yaitu syaikh (guru)
dari penulis buku. Disebut “permulaan sanad” karena kita memulai membaca
hadits dengannya.
Diantara bentuk-bentuk hadits mu’allaq adalah;
1. Dihapus seluruh sanad kemudian dikatakan –misalkan- : Bersabda Rasulullah ﷺ
2. Diantaranya juga adalah dengan menghapus/menggugurkan seluruh sanad kecuali nama shahabat atau shahabat dan tabi’i.
Contoh hadits mu’allaq adalah hadits yang diriwayatkan al-Bukhary dalam permulaan bâb mâ yudzkar fî al fakhidz (bab : Apa yang Disebutkan tentang Paha). Al-Bukhary berkata : "Dan berkata Abu Musa : Nabi ﷺ menutup kedua lututnya ketika Utsman datang."
Hukum Hadits Mu'allaq
Hadits
mu’allaq tertolak karena ia kehilangan salah satu syarat dari
syarat-syarat diterimanya sebuah hadits, yaitu bersambungnya sanad (ittishâl as sanad),
dengan hilangnya/gugurnya penyebutan seorang perawi atau lebih dari
sanad sementara kita tidak mengetahui keadaan/status dari perawi
tersebut.
Hadits-hadits Mu'allaq dalam Kitab ash-Shahihain
Hukum tertolaknya hadits mu'allaq berlaku untuk hadits-hadits secara mutlak. Namun, jika kasus itu ada pada sebuah kitab yang penulisnya komitmen hanya menuliskan hadits-hadits shahih saja seperti kitab Shahih al-Bukhary atau Shahih Muslim, maka yang seperti ini memiliki hukum tersendiri.
1. Hadits yang disebutkan dengan redaksi "al-jazm" (memastikan) seperti "berkata" ( قاَل ), "menyebutkan" ( ذَكر ), "menceritakan" ( حَكى ), maka yang seperti ini dipastikan keshahihannya dari orang yang mengucapkannya.
2. Jika disebutkan dengan redaksi "at-tamridh" (bentuk pasif) seperti "dikatakan" ( قِيلَ ), "disebutkan" ( ذُكِرَ ), "diceritakan" ( حُكِيَ ), maka ini tidak dihukumi keshahihannya kepada orang yang mengucapkannya. Perkataan itu bisa saja shahih, hasan atau dha'if, namun tidak ada hadits yang sangat lemah karena keberadaannya dalam kitab yang disebut sebagai "ash-shahih". Untuk memastikan keshahihannya adalah dengan mencari sanad dari riwayat tersebut dan menghukuminya dengan kekuatan atau kelemahan sanad itu.
Wallahu a'lam.
(Syaikh Dr. Muhammad ath-Thahhan, Taysir al-Mushthalah)