Allah
Ta’ala telah menciptakan manusia dalam dua jenis. Dan Dia juga
menyebutkan bahwa kedua jenis itu berbeda satu dari yang lainnya. Allah
berfirman,
وَلَيْسَ الذَكَرُ كَالأُنْثىَ
“Dan laki-laki tidaklah seperti perempuan.” (QS. Alu ‘Imran ayat 36).
Laki-laki tidak seperti wanita dalam sifat dan bentuk penciptaannya.
Laki-laki
memiliki kesempurnaan dalam bentuk fisik dan kekuatan karakternya,
sementara wanita lebih lemah darinya karena dia harus mengalami masa
haid, kehamilan, melahirkan, menyusui, mengurus anak dan membina
generasi umat.
Karena itulah wanita diciptakan dari tulang rusuk Adam ‘alaihissalam;
dia adalah bagian darinya, mengikuti urusannya dan menjadi perhiasan
untuknya. Sementara laki-laki diamanahkan untuk mengurus wanita,
menjaganya, menafkahinya dan anak-anak yang dilahirkan darinya.
Karena
perbedaan itulah maka berbeda pula beberapa hukum syari’at yang
dibebankan kepada kedua jenis manusia tersebut dalam urusan agama dan
dunia. Laki-laki adalah “qawwâm” dalam rumah tangga dalam wujud
pembinaan, penjagaan, pengayoman dan mengurusi nafkah keluarga.
Laki-laki yang berkuasa dalam rumah tangga dan wanita tidak akan pernah
bisa menyamainya dalam urusan itu atau lebih tinggi darinya.
Allah Ta’ala berfirman,
الرِجَالُ قَوَّامُونَ عَلىَ النِسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُم عَلىَ بَعْضٍ
“Kaum
laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah
melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita).” (QS. An-Nisa’ ayat 34).
Dan firmanNya,
وَلِلرِجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ
“Dan laki-laki (suami) mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada wanita (istri).” (QS. Al-Baqarah ayat 228).
Hukum-hukum
yang Allah khususkan untuk wanita itu sangat banyak yang bisa
didapatkan dalam penjelasan fiqh ibadah, mu’amalat, pernikahan, warisan,
pengadilan dan lain-lain. Termasuk di dalamnya persoalan yang berkenaan
dengan sifat dakwah kaum muslimah.
Dakwah
adalah satu bagian penting dalam agama ini. Hukumnya fardhu kifayah
menurut jumhur ulama. Jika telah ada sekelompok umat yang bekerja untuk
mengajak orang kepada agama Allah, mengajarkan mereka Islam yang hak,
maka kewajiban tersebut gugur dari yang lainnya.
Hukum kewajiban dakwah berlaku umum untuk
laki-laki dan wanita. Hanya saja, dalam aplikasinya tentu terdapat
perbedaan yang mencolok dalam menjalankan misi mulia tersebut. Apalagi
jika “dakwah” itu dipahami sebagai sebuah lembaga yang memiliki visi dan
misi dalam memperjuangkan apa yang mereka yakini atau harapkan dari
pergerakan itu.
Kami tidak
mengingkari pentingnya dakwah yang terorganisir rapi dalam usaha untuk
mencapai sebagian tujuan yang diharapkan dari dakwah. Tapi kami ingkari
jika tujuan suci itu terkotori oleh ambisi untuk mendapatkan kekuasaan,
ketenaran dan kebanggaan di hadapan manusia.
Kami juga
mengingkari jika tujuan suci itu akhirnya terkotori oleh usaha keras
untuk mencapai kuantitas tertentu dengan mengabaikan kualitas kader dan
mad’u dalam ilmu dan ibadah.
Kami juga
ingkari dan sayangkan jika ternyata juga, banyak dari pergerakan (yang
mengatasnamakan) dakwah itu (apalagi membawa nama “dakwah Salaf”) –sadar
atau tanpa sadar- telah mengeksploitasi kaum muslimah untuk kepentingan
sesaat mereka.
Benar,
wanita memiliki kewajiban yang sama dengan laki-laki dalam dakwah, tapi
dakwah itu bukanlah “dakwah” yang justru menghilangkan jati diri wanita
itu sebagai seorang muslimah.
Allah
telah memerintahkan wanita untuk berdiam di rumahnya, dan diamnya di
rumahnya adalah sebagai bentuk ibadahnya kepada Allah Ta’ala. Mewajibkan
seorang muslimah keluar rumah untuk “berdakwah” (baca : berorganisasi)
adalah sebuah kelancangan terhadap agama Allah.
Bagaimana
mungkin mewajibkan seorang muslimah keluar rumah berdakwah, sementara
Allah tidak pernah memerintahkan mengeluarkan mereka dari rumah-rumahnya
kecuali dalam shalat Id saja. Bahkan izin untuk shalat berjamaah di
masjid bagi seorang wanita pun masih disebutkan penekanan, bahwa
rumahnya lebih baik dan utama bagi dirinya.
Dari Ummu Humaid, istri Abu Humaid as-Sa’idi radhiyallahu ‘anhuma, bahwa ia datang kepada Nabi ﷺ dan berkata : Wahai Rasulullah, saya ingin shalat bersamamu.
Beliau berkata,
قَد
عَلِمتُ أنكِ تُحِبِّينَ الصَلاة مَعِي وَصَلاتكِ في بَيتكِ خيرٌ لكِ مِن
صَلاتكِ في حُجرَتكِ وَصَلاتكِ في حُجْرَتك خيرٌ مِن صَلاتكِ في دَاركِ
وصَلاتكِ في دَاركِ خيرٌ لكِ من صَلاتكِ في مَسْجدِ قومِكِ وصَلاتكِ في
مَسجدِ قومِكِ خيرٌ لكِ مِن صَلاتكِ في مَسْجِدِي
“Aku
tahu bahwa engkau sangat ingin shalat bersamaku, namun shalatmu di
kamarmu lebih baik bagimu daripada shalatmu di ruangan rumahmu. Dan
shalatmu di ruangan rumahmu lebih baik daripada shalatmu di rumahmu. Dan
shalatmu di rumahmu lebih baik daripada shalatmu di masjid kaummu. Dan
shalatmu di masjid kaummu jauh lebih baik daripada shalatmu di masjidku.”
Maka
ia (Ummu Humaid) menyuruh dibuatkan untuknya tempat shalat di tempat
yang paling dalam dan gelap di rumahnya, dan ia shalat di tempat itu
hingga ia menjumpai Allah ‘azza wa jalla. (HR. Ahmad, dishahihkan Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban dan al-Albani rahimahumullahu).
Dan diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu ‘anha
bahwa ia pernah mengomentari perbuatan para wanita di masanya. Aisyah
berkata, “Andai Rasulullah ﷺ menjumpai apa yang dibuat oleh wanita,
niscaya beliau akan melarang mereka sebagaimana wanita-wanita Bani
Israil dilarang (ke masjid).” (HR. Al-Bukhary dan Muslim).
Anehnya,
para “aktivis dakwah muslimah” itu, benar mereka tidak keluar rumah
untuk berjamaah di masjid, tapi setiap hari justru mereka keluar rumah
untuk “dakwah”?! Wallâhul musta’ân.
Paling
banter kita katakan bahwa keluarnya seorang wanita dari rumahnya untuk
dakwah (dakwah dalam makna sebenarnya, bukan dibungkus dengan
kepentingan kelompok atau lembaga tertentu) adalah sebuah “keutamaan”.
Tapi keutamaan itu semata-mata karena ada hajat penting untuk itu dan
dengan syarat yang juga penting, yaitu tidak mengabaikan perkara yang
lebih wajib berkait dengan hak suami dan urusan rumah tangga, dan
dilakukan oleh wanita yang punya kapasitas ilmu memadai.[1]
Faktanya
di banyak kelompok pergerakan Islam, semua kadernya dituntut harus
keluar rumah hampir setiap harinya “atas nama dakwah”, bahkan tidak
tersisa hari liburnya kecuali digunakan untuk kepentingan “dakwah”.
Miris
rasanya ketika melihat para akhawat kita yang sudah terpolakan oleh
tuntutan zaman atau keluarga untuk studi atau bekerja mencari
penghasilan, kemudian mereka harus “dipaksa” lagi untuk menghabiskan
waktu dan tenaganya mengurus “bentuk dakwah” yang Allah tidak pernah
wajibkan atas mereka, bahkan tidak juga dianjurkan.
Fakta yang
sangat nyata dalam pergerakan para akhawat aktivis, ketika salah
seorang dari mereka mendapatkan hidayah untuk mengenal agama Allah,
mereka justru didoktrin habis-habisan untuk menjadi aktivis dakwah
diluar rumah, dan tidak dididik dan dibina untuk menjadi muslimah yang
hebat di rumahnya.
Katakanlah
seandainya memang para akhawat itu masih diberikan nasehat untuk
menjadi muslimah yang baik dalam dirinya, hijabnya dan urusan rumahnya,
tapi sangat aneh ketika nasehat itu disampaikan kemudian akhawat
tersebut diberikan seabrek beban kegiatan dan aktivitas lembaga –sekali
lagi mengatasnamakan Allah, Islam dan dakwah- sehingga waktunya habis
hanya untuk mengurus lembaga, mengurus orang lain agar mendapatkan
hidayah, dan yang menjadi korban adalah jatidirinya, rumahnya dan
keluarganya. Lâ haula wa lâ quwwata illâ bi_llâh.
Sebagian
aktivis dakwah berdalih untuk pembenaran aktivitas luar rumahnya dalam
dakwah, bahwa para shahabiyat juga ikut berperang dan Rasulullah ﷺ tidak
menegur mereka dengan perbuatan tersebut.(?!)
Pertanyaannya : siapa shahabiyah yang ikut berperang itu?
Dalam sirah nabawiyyah tidak dikenal wanita yang terlibat langsung dalam peperangan kecuali kisah Nusaibah bintu Ka’ab.
Riwayat kisah tersebut tidak sah[2].
Riwayat-riwayat shahih hanya menyebutkan tentang beberapa muslimah yang
bertugas membantu mengobati dan memberi minum prajurit yang terluka.[3]
Andai para
aktivis itu mau berdalih dengan kisah-kisah seperti ini, mestinya lebih
layak mereka menyuruh para muslimah untuk menjadi dokter dan perawat.
Tapi anehnya, mereka jadikan kisah itu untuk mengeluarkan para muslimah
dari rumahnya demi “dakwah”.
Kalau pun
diasumsikan riwayat tentang shahabiyah yang berperang itu shahih, maka
itu terjadi karena sebuah kondisi yang darurat dan terjadi sebelum
turunnya ayat perintah untuk berhijab. Rasulullah ﷺ tidak pernah
mengikut sertakan wanita dalam peperangan, untuk membantu orang-orang
terluka sekalipun, kecuali dalam perang Uhud. Pertimbangannya, wallahu a’lam,
karena jaraknya yang dekat dari Madinah. Dan perlu diketahui, dalam
perang Ahzab yang terjadi di kota Madinah beliau tidak mengikutsertakan
satu orang pun dari kaum wanita dalam perang tersebut.
Allah
telah menggugurkan kewajiban jihad dari kaum wanita. Karena Nabi ﷺ tidak
pernah memberikan bendera perang kepada seorang wanita dan tidak pula
para khalifah sesudahnya. Beliau bahkan tidak memberi sekedar anjuran
bagi wanita untuk berperang dan tidak pula untuk kepentingan perang.
Bahkan, memanfaatkan wanita dalam perang dan memperbanyak jumlah tentara
dengan kaum wanita adalah tanda kelemahan umat dan rusaknya pemikiran
mereka! (Hirâsah al-Fadhîlah, Syaikh Dr. Bakr Abu Zaid rahimahullahu, hal. 77)
Dari Ummu Salamah radhiyallahu ‘anha
ia berkata, “Wahai Rasulullah, kaum laki-laki berperang sementara kami
tidak berperang. Dan kami hanya mendapatkan setengah warisan?!” Maka
Allah menurunkan,
وَلاَ تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللهُ بِهِ بَعْضَكُم عَلىَ بَعْضٍ
“Dan
janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada
sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain.” (QS. An-Nisa’ ayat
32)
Belajarlah dari Aisyah radhiyallaha ‘anha
Sebagaimana diketahui, Aisyah radhiyallahu ‘anha
adalah satu-satunya ummahatul mukminin, bahkan satu-satunya wanita,
yang terlibat dalam fitnah perang di masa pemerintahan Khalifah Ali bin
Abi Thalib radhiyallahu ‘anhu. Keikutsertaan Aisyah tersebut
dengan bujukan dari keponakannya, Abdullah bin Zubair dan orang-orang
yang bersamanya. Dibayangkan kepadanya bahwa kepergiannya ke Basrah
(Irak) itu adalah kemaslahatan bagi kaum muslimin, untuk mendamaikan
perselisihan kaum muslimin dalam persoalan darah Khalifah Utsman. Aisyah
turut serta dalam peristiwa itu untuk sebuah alasan yang baik dan
terpuji, namun peristiwa itu akhirnya menjadi penyesalan terbesarnya
dalam sisa hidupnya. Setiap kali ia membaca firman Allah,
وَقَرْنَ فيِ بُيُوتِكُنَّ
“Dan berdiamlah kamu di rumahmu.” (QS. Al-Ahzab ayat 33), ia menangis hingga jilbabnya basah.
Apakah
para wanita yang keluar atas nama dakwah itu lebih baik dari Aisyah?
Apakah maslahat yang mereka tuntut sama seperti yang diharapkan dari
keluarnya Aisyah? Aisyah keluar untuk mencegah pertumpahan darah kaum
muslimin yang mereka itu adalah anak-anaknya dalam statusnya sebagai
“ummul mukminin”, sementara para aktivis itu, untuk sebuah keadaan
darurat seperti apa sehingga mereka halalkan wanita dikeluarkan dari
rumahnya sementara Allah telah menyuruhnya untuk diam di rumah?!
Aisyah
tidak pernah terlibat dalam perang. Ia hanya berharap bisa membantu
mendamaikan antar kaum muslimin dan ia mengira bahwa keluarnya dia dari
rumahnya adalah sebuah maslahat untuk tujuan tersebut. Tapi ia akhirnya
menyadari kekeliruannya dan berharap andai saja hal itu tidak pernah
terjadi. Semoga Allah merahmati Ummul Mukminin Aisyah.
Mendidik Wanita adalah Kewajiban Laki-laki
Allah telah mewajibkan kaum laki-laki untuk membina, mendidik dan mengajarkan kaum wanita dalam firmanNya,
يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا قُوا أنْفُسَكُم وَأَهْلِيْكُم نَارًا
“Hai orang-orang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka.” (QS. At-Tahrim ayat 6).
Dan disebutkan dalam kitab ash-Shahîhain
dari Abu Sa’id ia berkata : Para wanita berkata, “Wahai Rasulullah,
kaum laki-laki telah mengalahkan kami terhadap dirimu. Jadikan untuk
kami satu hari dari dirimu.” Maka beliau menjanjikan mereka satu hari
dimana beliau menjumpai mereka dan beliau menasehati mereka dan
menjelaskan perintah (agama).
Di zaman
ini, para wanita yang “terpelajar” itu justru begitu mendominasi dalam
semua urusan menuntut ilmu dan dakwah. Namun, disadari atau tidak,
“kehebatan” banyak aktivis “dakwah” wanita itulah yang justru semakin
melemahkan kaum laki-laki. Di banyak pergerakan, kaum wanitalah yang
justru lebih dominan, dan terkesan para lelaki itu bergantung kepada
wanita dalam banyak urusan kelompok mereka, terkhusus berkait dengan
jumlah pengikut. Hingga terkesan bahwa sebagian laki-laki itu menganggap
urusan ilmu dan pemahaman agama istrinya bukan lagi menjadi
tanggungjawabnya, dan ia cenderung hanya sibuk saja dengan urusan
pekerjaannya dan sangat lemah dalam kualitas ilmu dan ibadahnya. Sekali
lagi karena bergantung kepada aktivitas dakwah wanita di luar rumah!
Shalat
berjamaah di masjid adalah salah satu bentuk pendekatan diri yang sangat
agung kepada Allah Ta’ala. Namun toh demikian, shalatnya seorang wanita
di rumahnya jauh lebih utama daripada shalatnya di masjid bersama
jamaah, walaupun masjid itu adalah masjid Nabawi. Keutamaan itu berkait
dengan pentingnya seorang wanita berdiam di rumahnya. Jika demikian
keadaan wanita dengan shalat di masjid, maka bagaimana lagi hanya urusan
dakwah yang fardhu kifayah, yang tidak mungkin kewajiban dakwah itu
bagi seorang wanita bisa menandingi wajibnya melayani suami dan
berkhidmat untuk rumah tangganya.
Karenanya kita katakan, keluarnya seorang wanita dari rumahnya untuk dakwah tidak lepas dari dua keadaan,
Pertama;
hal itu menjadi sunnah dan dianggap sebagai sebuah syari’at bagi kaum
muslimin. Maka tidak diragukan bahwa yang seperti ini adalah bid’ah yang
tercela.
Kedua;
hal itu terjadi untuk sebuah urusan yang bersifat kebetulan dan tidak
sering dilakukan hingga menyita begitu banyak waktu dan tenaga, dan
lebih dekat kepada sebuah kondisi yang sangat penting/darurat untuk
menolak mafsadah/keburukan yang besar. Yang seperti ini tidak mengapa
dilakukan, bahkan terkadang menjadi sebuah hal yang wajib.
Dari sini
bisa dipahami perbedaan antara status dakwah (dakwah dalam makna yang
sebenarnya, bukan kepentingan lembaga dakwah itu) yang dianggap sebagai
sebuah sunnah/syari’at dan statusnya untuk menolak mafsadah.
Semoga
Allah menjaga para muslimah dari kepentingan tersembunyi yang ingin
mengeksploitasi diri dan agama mereka atas nama dakwah.
Wallahul musta’an.
———————
Footnotes :
[1] Diantarannya adalah perkataan Syaikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu,
“Hukum asalnya adalah berdiam di rumah. Itulah hukum asalnya. Dan
itulah yang paling selamat dan lebih utama dengan dalil firman Allah ‘azza wa jalla.
Karena (diamnya di rumahnya) itu menjauhkannya dari fitnah. Akan
tetapi, keluarnya dia untuk sebuah hajat dan keluarnya dia untuk
berdakwah kepada Allah, belajar, silaturrahim, menjenguk orang sakit
atau memberi takziyah kepada orang yang ditimpa musibah, semua ini tidak
mengapa dan disyari’atkan. Yang dbenci adalah keluarnya dia tanpa ada
hajat penting…” (Fatâwâ Nûr ‘alâ ad-Darb, no. 128).
Dakwah
yang beliau maksud adalah dakwah yang murni dakwah. Bukan aktivitas
organisasi yang kemudian disebut sebagai “dakwah” yang menguras seluruh
waktu, tenaga dan pikiran seorang wanita yang lemah hingga mengabaikan
kewajibannya dalam rumah.
Beliau
menyebut bolehnya keluar itu untuk sebuah hajat atau darurat. Dan sifat
darurat ditetapkan dengan kadarnya, bukan justru dimudah-mudahkan hingga
semua urusan dianggap sebagai hajat dan darurat.
[2] Disebutkan dalam Sirah Ibn Hisyam (III/32) dengan sanad munqathi’ (terputus) dan dalam Maghazi al-Waqidi (I/268), sementara al-Waqidi dha’îf jiddan (sangat lemah). Silahkan rujuk ke as-Sîrah an-Nabawiyyah ash-Shahîhah, II/390.
[3] Fathul Bâry (VI/78, VII/366), Syarh an-Nawawî ‘alâ Shahîh Muslim
(XII/189). Para ulama menjelaskan bahwa riwayat-riwayat tersebut
menunjukkan bolehnya memanfaatkan jasa para wanita dalam kondisi darurat
untuk mengobati dan merawat prajurit yang terluka jika keadaan aman
dari fitnah mereka dengan tetap menjaga hijabnya. Dan mereka boleh
mempertahankan diri dengan berperang jika musuh datang mengganggu
mereka.








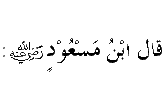

0 tanggapan:
Posting Komentar