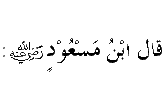29 Februari 2016
Firqah Al-Murji’ah
Al-Irjâ’ menurut bahasa memiliki beberapa makna diantaranya adalah harapan (al amal), rasa takut (al khauf), penundaan (at ta’khîr), pemberian harapan (i’thâ’ ar rajâ’).
Menurut istilah, para ulama berbeda pendapat tentang makna sebenarnya dari kata al-Irja’.
Sebagian mengatakan bahwa al-irja’
menurut istilah kembali kepada makna bahasanya, yaitu bermakna
penundaan, yaitu penundaan atau mengakhirkan amal dari level keimanan
dan menjadikannya pada level kedua, yang bermakna bahwa amal itu
bukanlah bagian dari definisi iman. Iman mencakup amalan dari sisi
majaz, sementara hakikat sebenarnya adalah sekedar pembenaran (at tashdîq).
Sebagian lain berpendapat bahwa yang dimaksudkan dengan al-irja’
adalah menunda hukum pelaku dosa besar hingga hari Kiamat nanti,
dan tidak divonis dengan hukum tertentu dalam kehidupan dunia ini.
Sebagian
lagi mengaitkannya dengan fitnah yang terjadi diantara para Shahabat,
yaitu menunda atau mengembalikan perkara yang terjadi antara Utsman dan
Ali radhiyallahu ‘anhuma, atau antara Ali dan Mu’awiyah kepada
Allah Ta’ala, serta tidak menghukumi salah satu diantara mereka dengan
keimanan atau kekafiran.
Pondasi yang Dibangun diatasnya Mazhab Murji’ah
Pondasi
itu adalah perselisihan tentang hakikat keimanan; iman itu terdiri dari
apa, apa saja batasan maknanya, apakah iman hanya perbuatan hati saja,
ataukah dia perbuatan hati dan lisan, dan amalan tidak termasuk bagian
dari hakikat iman tersebut, yang konsekuensinya iman itu tidak akan
bertambah dan berkurang. Itulah poin-poin terpenting yang menjadi
pembahasan firqah-firqah Murji’ah.
- Sebagian
besar firqah-firqah Murji’ah berpendapat bahwa iman hanyalah apa yang
ada di dalam hati, dan tidak akan membahayakannya apa yang nampak dari
amal perbuatannya bahkan walaupun hal itu berupa kekafiran dan
pembangkangan. Inilah mazhab al-Jahm bin Shafwan. Dalam pandangannya,
pengakuan dengan lisan dan amalan bukanlah perkara penting karena hal
itu bukanlah bagian dari hakikat keimanan.
-
Al-Karramiyyah berpendapat bahwa iman adalah ucapan dengan lisan, dan
tidak akan berbahaya setelahnya menyembunyikan keyakinan apapun bahkan
walaupun hal itu berupa kekafiran.
- Sementara Abu Hanifah rahimahullahu
berpendapat bahwa iman adalah pembenaran dengan hati dan ucapan dengan
lisan, satu dengan yang lainnya akan saling membutuhkan. Siapa yang
membenarkan dengan hatinya dan terang-terangan mendustakan dengan
lisannya, maka ia tidak disebut sebagai mukmin. Diatas keyakinan inilah
tegak mazhab Hanafi, dan inilah pemahaman Murji’ah yang paling dekat
kepada Ahlussunnah karena mereka sepakat dengan Ahlussunnah bahwa pelaku
maksiat berada dalam kehendak (masyî-ah) Allah dan dia tidak keluar dari keimanannya.
Bagaimana Pemahaman Irja’ itu Muncul?
Al-irja’
pada permulaannya dimaksudkan –dalam sebagian definisinya- sebuah sikap
yang diambil oleh orang-orang yang menginginkan keselamatan, menjauhkan
perselisihan dan meninggalkan pertikaian dalam urusan-urusan politik
dan keagamaan, khususnya yang berkait dengan hukum-hukum akhirat;
tentang keimanan, kekafiran, surga dan neraka, demikian pula yang
berkait dengan perkara tentang Ali, Utsman, Thalhah, az-Zubair, Ummul
Mukminin Aisyah dan apa yang terjadi antara Ali dan Mu’awiyah.
Setelah terbunuhnya Utsman radhiyallahu ‘anhu dan kemunculan Khawarij dan Syi’ah, maka mulailah pemahaman irja’ berkembang secara bertahap.
Bagaimana Pemahaman Irja’ Berkembang menjadi sebuah Mazhab?
Ketika
terjadi perselisihan tentang hukum pelaku dosa besar dan perselisihan
tentang kedudukan amal dalam iman, maka muncullah sekelompok orang yang
membawa pemahaman irja’ kepada sikap ekstrim dan melampaui batas yang tercela. Maka mulailah pemahaman irja’
terbentuk dalam sifatnya sebagai sebuah mazhab. Mereka menetapkan bahwa
pelaku dosa besar memiliki iman yang sempurna, maksiat tidak akan
membahayakan iman dan ketaatan tidak akan bermanfaat bagi kekafiran,
iman itu tempatnya di hati sehingga tidak akan membahayakan seseorang
apapun yang dilakukannya sesudah itu. Walaupun dia melafalkan kekafiran
dan pembangkangan, imannya tetap sempurna dan tidak tergoyahkan.
Tidak diragukan bahwa keyakinan seperti ini adalah pemahaman yang buruk dan sikap melampaui batas. Para penganut paham irja’
dalam level ini adalah orang-orang yang sangat tercela dan mazhab
mereka akan membawa manusia kepada kemalasan, menghalalkan segala cara
dan bersandar secara keliru kepada sifat pengampun Allah Ta’ala tanpa
mau beramal.
Siapa yang Pertama Kali Berbicara tentang Irja’?
Para ulama
menyebutkan bahwa al-Hasan bin Muhammad bin al-Hanafiyyah adalah orang
yang pertama kali menyebutkan tentang pemahaman irja’ di kota
Madinah, khususnya yang berkait dengan Ali, Utsman, Thalhah dan
az-Zubair ketika manusia memperbincang pribadi-pribadi yang mulia itu
dan al-Hasan berdiam diri. Kemudian ia berkata, “Aku telah mendengarkan
pembicaraan kalian, dan aku tidak melihat sesuatu yang lebih pantas
selain menunda/mendiamkan (perkara) Ali, Utsman, Thalhah dan az-Zubair.
Tidak memberikan wala’ (loyalitas) kepada mereka dan tidak juga berlepas diri.”
Akan
tetapi, al-Hasan telah menyesali perkataannya tersebut dan
berandai-andai kalau saja ia telah meninggal sebelum mengucapkannya.
Perkataannya inilah yang menjadi jalan pembuka untuk tumbuhnya pemahaman
irja’. Perkataannya itu sampai kepada ayahnya, Muhammad bin
al-Hanafiyyah, dan ia pun memukul al-Hasan sampai melukainya dan
berkata, “Engkau tidak membela ayahmu, Ali?!”
Orang-orang
yang mengambil perkataan itu dari al-Hasan tidak pernah mau melihat
kepada penyesalan al-Hasan. Perkataan itu menyebar di kalangan manusia
dan berjumpa dengan hawa nafsu dalam jiwa-jiwa beberapa kalangan dan
menjadikannya sebagai sebuah keyakinan.
Pendapat lain mengatakan bahwa yang pertama kali berbicara tentang irja’
dalam bentuk ekstrimnya adalah seseorang yang disebut Dzirr bin
Abdillah al-Hamadani dari masa generasi Tabi’in. Para ulama di masa itu
telah mengecam Dzirr, bahkan sebagian mereka tidak menjawab salamnya
karena ia mengeluarkan amal dari definisi iman.
Pendapat lain : Yang pertama mengadakan pemikiran irja’ adalah seorang laki-laki di Irak yang bernama Qais bin ‘Amr al-Madhiri.
Pendapat
lain : Yang pertama mengadakan bid’ah ini adalah Hammad bin Abi
Sulaiman, guru Abu Hanifah dan murid dari Ibrahim an-Nakha’i, rahimahumullahu.
Dan pemikiran itu tersebar di kalangan penduduk Kufah, Irak. Syaikhul
Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan bahwa yang pertama kali menyebutkan irja’ di kalangan penduduk Kufah adalah Hammad.
Pemahaman irja’ para imam inilah yang dikenal sebagai irja’nya para ahli fiqh (irja-ul fuqaha’).
Pendapat lainnya lagi mengatakan bahwa yang pertama kali berbicara tentang irja’ adalah seseorang yang bernama Salim al-Afthas.
Yang nampak, wallahu a’lam, pendapat-pendapat itu tidaklah saling berjauhan karena mereka hidup dalam masa yang sama.
Siapa Tokoh-Tokoh Besar Murji’ah?
Yang kami
maksudkan adalah kalangan Murji’ah ekstrim yang dengannya Murji’ah
dikenal sebagai sebuah firqah/sekte sesat dan keyakinannya bertolak
belakang dengan aqidah Ahlussunnah wal Jama’ah.
Mereka
adalah al-Jahm bin Shafwan, Abul Husain ash-Shalihi, Yunus as-Samri, Abu
Tsauban, al-Husain bin Muhammad an-Najjar, Ghailan ad-Dimasyqi,
Muhammad bin Syabib, Bisry al-Mirrisi, Muhammad bin Karram, Muqatil bin
Sulaiman yang menyerupakan Allah ‘azza wa jalla dengan makhlukNya, dan yang serupa dengannya, yaitu al-Jawaribi. Keduanya termasuk golongan musyabbihah ekstrim.
Prinsip-Prinsip Keyakinan Murji’ah
1. Iman menurut mereka adalah pembenaran (at-tashdîq) dengan ucapan, atau pengetahuan (al-ma’rifah), atau pengakuan (al-iqrâr).
Amal tidaklah masuk dalam hakikat keimanan, dan bukan bagian darinya,
walaupun sebenarnya mereka tidak mengabaikan sepenuhnya kedudukan amal
dalam iman, kecuali pandangan sesatnya al-Jahm bin Shafwan.
2. Iman
tidak bertambah dan tidak berkurang, karena pembenaran terhadap sesuatu
dan pemastiannya tidak akan memberikan tambahan apapun atau pengurangan.
Karenanya, menurut mereka, para pelaku maksiat memiliki iman yang
sempurna dengan kesempurnaan pembenaran mereka (at-tashdiq), dan mereka dipastikan tidak akan masuk neraka di akhirat nanti.
3. Sebagian sekte mereka meyakini bahwa manusialah yang menciptakan perbuatan mereka sendiri.
4. Mereka juga mengimani bahwa Allah tidak dapat dilihat di akhirat nanti.
5. Al-Imâmah
(kepemimpinan) bukanlah perkara wajib dalam pandangan mereka. Kalau
imamah itu mesti ditegakkan, maka ia bisa dijabat oleh siapapun walaupun
bukan berasal dari Quraisy.
6.
Diantara keyakinan Murji’ah bahwa kufur kepada Allah adalah kejahilan
tentang Dia. Itulah perkataan al-Jahm. Dan iman itu hanyalah mengenal
Allah (ma’rifah) saja dan iman itu tidak terbagi-bagi.
7. Mereka
juga meyakini bahwa surga dan neraka tidaklah kekal. Demikian juga
dengan penghuni keduanya, dan tidak ada keabadian pada keduanya.
8.
Sebagian mereka berkeyakinan bahwa setiap maksiat adalah dosa besar, dan
sebagian mereka juga berpendapat bahwa ampunan Allah terhadap dosa-dosa
dengan taubat adalah bentuk keutamaan yang datang dari Allah dan
sebagian mengatakannya sebagai sebuah keharusan.
9. Sebagian mereka membolehkan terjadinya perbuatan dosa besar dari para nabi ‘alaihimussalam.
10.
Sebagian mereka juga menetapkan mungkinnya melihat Allah di akhirat,
sementara sebagian lainnya menolaknya sebagaimana pandangan Mu’tazilah.
11. Mereka
berselisih dalam pandangan tentang perkataan bahwa al-Quran adalah
makhluk. Sebagian mengatakan bahwa al-Quran adalah makhluk, sebagian
berpendapat bukan makhluk dan sebagian lagi mengambil sikap diam (tawaqquf).
12. Mereka juga berbeda pendapat tentang masalah takdir. Sebagian menolaknya dan sebagian menetapkannya.
13. Dan mereka juga berbeda pendapat dalam persoalan al-asmâ’ wa ash-shifât
(nama-nama dan sifat-sifat Allah). Sebagian Murji’ah mengikuti
pendapatnya Abdullah bin Kullab, dan sebagian lainnya mengikuti metode
Mu’tazilah.
Wallahu a’lam.
----------------------
Sumber bacaan : Firaq Mu’âshirah Tantasib ilâ al Islâm, Syaikh Dr. Ghalib bin Ali ‘Awaji
21 Februari 2016
Hukum Bunga Bank
Majelis Majma’ al-Fiqh al-Islami dibawah
naungan Organisasi Konferensi Islam* dalam pertemuannya yang kedua di
Jeddah, 10-16 Rabi’ul Akhir 1406 H/22-28 Desember 1985 M; setelah
disodorkan padanya beberapa makalah tentang transaksi perbankan modern,
dan setelah menelaah dan mendiskusikannya, maka nampaklah berbagai
keburukan transaksi tersebut yang berdampak pada sistem dan stabilitas
perekonomian dunia, khususnya di dunia ketiga. Dan setelah menelaah
akibat buruk yang ditimbulkan oleh sistem tersebut karena pengabaian
terhadap aturan yang ada dalam Kitab Allah yang mengharamkan riba secara
parsial maupun global, dan mengajak untuk bertaubat darinya serta
mengajak kepada sistem perekonomian untuk pengembalian modal pokok
pinjaman tanpa ada tambahan atau pengurangan, sedikit ataupun banyak,
dan juga ancaman berupa perang terbuka dari Allah dan rasulNya terhadap
orang-orang yang memakan riba, maka Majelis memutuskan beberapa hal
berikut ini :
1. Setiap tambahan atau bunga terhadap pembayaran hutang yang jatuh tempo yang tidak sanggup dibayar oleh peminjam sebagai dispensasi atas penangguhan pembayaran, dan demikian juga tambahan atau bunga terhadap pinjaman yang diterapkan sejak permulaan akad kesepakatan; kedua bentuk transaksi ini adalah riba yang diharamkan.
1. Setiap tambahan atau bunga terhadap pembayaran hutang yang jatuh tempo yang tidak sanggup dibayar oleh peminjam sebagai dispensasi atas penangguhan pembayaran, dan demikian juga tambahan atau bunga terhadap pinjaman yang diterapkan sejak permulaan akad kesepakatan; kedua bentuk transaksi ini adalah riba yang diharamkan.
2.
Alternatif yang bisa menjamin perputaran uang dan membantu pergerakan
ekonomi dalam bentuknya yang diridhai Islam adalah transaksi yang
selaras dengan hukum-hukum Syari’at.
3. Majelis
menetapkan pentingnya mengajak pemerintahan-pemerintahan Islam (kepada
persoalan ini) dan membuka peluang pendirian perbankan Syari’ah di
setiap negeri Islam demi untuk memenuhi kebutuhan kaum muslimin, agar
seorang muslim tidak hidup dalam sebuah hal yang kontradiktif antara
realita (yang ada) dan konsekuensi (dari berpegang terhadap) ajaran
aqidahnya.
Wallahu a’lam
(Sumber : Islamtoday)
—————————
* Sekarang bernama Organisasi Kerjasama Islam (OIC)
19 Februari 2016
Bolehkah Mengulangi Pandangan Pertama?
Sebagian
kalangan membolehkan seorang laki-laki memandang kembali kecantikan
wanita yang menarik hatinya pada pandangan pertama, dengan dalih bahwa
hal itu akan menjadi obat yang meringankan rasa suka dan penasaran yang
ada dalam hatinya.
Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu memiliki jawaban yang bagus untuk masalah tersebut. Beliau menyebutkan sepuluh perkara sebagai bantahan atas pendapat itu.
Pertama,
Allah
Ta’ala menyuruh untuk menjaga pandangan, dan Dia tidak pernah menjadikan
kesembuhan penyakit yang ada dalam hati dengan sesuatu yang Dia telah
haramkan.
Kedua,
Nabi ﷺ
pernah ditanya tentang pandangan yang terjadi secara kebetulan, dan
beliau mengetahui bahwa pandangan pertama itu memiliki pengaruh di hati,
namun beliau menyuruh mengobatinya dengan memalingkan pandangan bukan
justru mengulanginya.
Ketiga,
Beliau ﷺ
secara jelas menyebutkan bahwa pandangan pertama adalah untuk orang yang
memandang, dan pandangan kedua bukanlah bagiannya. Sangat mustahil jika
penyakitnya ada pada (pandangan) yang menjadi bagiannya, sementara
obatnya berada dalam perkara yang bukan bagiannya.
Keempat,
Yang
sangat nampak adalah bertambah kuatnya urusan itu dengan pandangan
kedua, bukan justru semakin berkurang. Dan fakta membuktikan akan hal
tersebut.
Kelima,
Barangkali saja dia akan melihat lebih dari apa yang ada dalam bayangan dirinya, sehingga bertambahlah rasa sakitnya.
Keenam,
Iblis akan
menungganginya pada pandangan keduanya itu, dia akan menjadikan indah
apa yang sebenarnya tidak indah hingga sempurnalah bencana itu.
Ketujuh,
Orang itu
tidak akan ditolong dari kesulitannya jika dia berpaling dari perintah
syariat dan justru mengobatinya dengan pekara yang diharamkan atasnya.
Bahkan sangat layak jika pertolongan itu dipalingkan darinya.
Kedelapan,
Pandangan
pertama adalah panah beracun dari panah-panah Iblis, dan sudah dimaklumi
bahwa pandangan kedua lebih keras racunnya. Maka bagaimana racun akan
diobati dengan racun?!
Kesembilan,
Orang yang berada dalam situasi ini (yaitu menjaga pandangan dari yang diharamkan), dia sedang berinteraksi dengan Allah ‘Azza wa Jalla
untuk meninggalkan sesuatu yang dia sukai untuk mencari keridhaan
Allah. Ketika dia memandang yang kedua kalinya, dia ingin memastikan
kembali keadaan wanita yang dilihatnya pada pandangan pertama. Jika
ternyata wanita itu tidak sebagaimana yang dia inginkan, dia akan
meninggalkan pandangan tersebut. Kalau demikian keadaannya, maka
pandangan yang dia tinggalkan itu semata-mata karena tidak sesuai dengan
apa yang dia harapkan, bukan karena Allah Ta’ala. Maka dimanakah
interaksinya terhadap Allah Ta’ala dengan meninggalkan sesuatu yang
disukai dirinya karena mengharapkan ridhaNya?
Kesepuluh,
Penjelasannya
akan lebih terang dengan permisalan berikut ini; Jika engkau menunggang
kuda baru dan dia berjalan menuju jalan sempit yang tidak bisa dimasuki
dan tidak mungkin baginya berputar untuk keluar, jika kuda itu ingin
memaksa masuk maka engkau harus mencegahnya. Jika dia telah masuk
selangkah atau dua langkah, bersegeralah untuk menariknya mundur sebelum
dia benar-benar memasukinya. Jika engkau bisa menariknya mundur,
urusannya akan mudah. Jika engkau berlambat-lambat hingga dia masuk dan
engkau menggiringnya lebih dalam, kemudian engkau berusaha menariknya
dengan ekornya maka urusan itu akan menjadi parah dan sulit baginya
keluar. Apakah orang yang berakal akan mengatakan bahwa jalan untuk
membebaskannya adalah dengan menggiringnya masuk?! Demikian pula dengan
pandangan jika telah memberikan pengaruh pada hati. Jika orang itu
bersegera memutuskan penyakit itu semenjak awal, akan mudahlah
mengobatinya. Jika dia mengulangi pandangan dan lebih dalam lagi
memandangi keindahan obyeknya serta memindahkannya ke dalam hati yang
kosong dan mengukir di dalamnya, maka bersemayamlah rasa cinta itu.[1]
Dan benarlah Allah Ta’ala dalam firmanNya,
قُلْ
لِلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ أَبْصَارِهِم وَيَحْفَظُوْا
فُرُوْجَهُمْ ذَلِكَ أزْكىَ لَهُمْ إِنَّ اللهَ خَبِيْرٌ بِمَا
يَصْنَعُوْنَ
“Katakanlah
kepada orang laki-laki yang beriman : Hendaklah mereka menahan
pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu lebih suci
bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat.” (QS. An-Nur ayat 30).
Rasulullah ﷺ bersabda dalam wasiatnya kepada Ali radhiyallahu ‘anhu,
يَا عَلِيُّ لا تُتْبِعْ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ فَإِنَّ لَكَ الأُولَى وَلَيْسَتْ لَكَ الآخِرَةُ
“Wahai
Ali, janganlah engkau mengikutkan satu pandangan dengan pandangan
(berikutnya), karena pandangan pertama untukmu dan yang kedua bukan
untukmu.” (HR. Abu Dawud dan At-Tirmidzi).
Dalam kitab Ash-Shahih, beliau ﷺ bersabda,
كُتِبَ
عَلَى ابْنِ آدَمَ نَصِيبُهُ مِنْ الزِّنَا مُدْرِكٌ ذَلِكَ لَا مَحَالَةَ
: فَالْعَيْنَانِ زِنَاهُمَا النَّظَرُ ، وَالْأُذُنَانِ زِنَاهُمَا
الِاسْتِمَاعُ ، وَاللِّسَانُ زِنَاهُ الْكَلَامُ ، وَالْيَدُ زِنَاهَا
الْبَطْشُ ، وَالرِّجْلُ زِنَاهَا الْخُطَا ، وَالْقَلْبُ يَهْوَى
وَيَتَمَنَّى ، وَيُصَدِّقُ ذَلِكَ الْفَرْجُ وَيُكَذِّبُهُ
“Telah
ditetapkan untuk seeorang anak Adam bagiannya dari zina. Dia pasti akan
mendapatkannya. Kedua mata zinanya adalah memandang, kedua telinga
zinanya adalah mendengar, kedua lisan zinanya adalah berbicara, tangan
zinanya adalah memegang dan kaki zinanya adalah melangkah. Hati
berkeinginan dan berangan-angan, dan kemaluanlah yang membenarkannya
atau mendustakannya.” (HR. Muslim, dan diriwayatkan Al-Bukhary dengan redaksi yang mendekati maknanya).
Nabi ﷺ memulai dengan menyebutkan zina mata, karena dari matalah bermula hingga terjadilah zina hati, tangan, kaki dan kemaluan.
Dan dalam sebuah hadits diriwayatkan,
إِنَّ النَّظْرَةَ سَهْمٌ مِنْ سِهَامِ إِبْلِيسَ مَسْمُومٌ
“Pandangan adalah panah beracun dari panah-panah Iblis.” (Diriwayatkan Al-Hakim dalam Al-Mustadrak dengan sanad yang dha’if).
Wallahu a’lam.
————————
Footnotes :
[1] Disadur dari kitab Raudhah Al-Muhibbîn wa Nuzhah Al-Musytâqqîn, hal. 94-95
16 Februari 2016
Iman terhadap Karamah Wali
Diantara prinsip pokok aqidah Salafiyyah, Ahlussunnah wal Jama’ah adalah mengimani karamah para wali Allah.
Karamah
adalah perkara-perkara luar biasa yang Allah jadikan pada sebagian
wali-waliNya dari kalangan orang-orang shalih yang komitmen dengan hukum-hukum Syari'at, sebagai bentuk pemuliaan dariNya terhadap mereka.
Jika hal itu terjadi tanpa disertai iman yang benar dan amal yang shalih, maka itu adalah istidrâj.
Jika hal itu terjadi tanpa disertai iman yang benar dan amal yang shalih, maka itu adalah istidrâj.
Allah Ta’ala berfirman,
ألاَ
إِنَّ أولِيَاءَ اللهِ لاَ خَوفٌ عَلَيهِم وَلاَ هُم يَحْزَنُونَ،
الَّذِينَ ءَامَنُوا وَكَانُوا يَتَقُونَ، لَهُمُ البُشْرىَ فِي الحَيَاةِ
الدُّنْيَا وَفِي الآخِرَةِ لاَ تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللهِ ذَلِكَ هُوَ
الفَوزُ العَظِيْمُ
“Ingatlah
sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka
dan tidak pula mereka bersedih hati. (Yaitu) orang-orang yang beriman
dan mereka selalu bertakwa. Bagi mereka berita gembira di dunia dan
(dalam kehidupan) di akhirat. Tidak ada perubahan bagi kalimat-kalimat
(janji-janji) Allah. Yang demikian itu adalah kemenangan yang besar.” (QS. Yunus ‘alaihissalam ayat 62-64).
Ahlussunnah
wal Jama’ah meyakini kebenaran karamah para wali, namun dengan
kaedah-kaedah syar’i yang dijelaskan oleh dalil. Tidaklah setiap perkara
luar biasa merupakan karamah dari Allah Ta’ala, karena bisa jadi itu
merupakan bentuk istidrâj atau perbuatan para pendusta, tukang sihir atau perbuatan syaitan.
Karamah
berasal dari Allah dan sebabnya adalah ketaatan dan ketakwaan. Karamah
hanya berlaku khusus bagi orang-orang yang istiqamah diatas agama Allah
Ta’ala. Allah berfirman,
وَمَا كَانُوا أوْلِيَاءَهُ إنْ أولِيَاؤُهُ إِلاَّ المُتَّقُونَ
“Dan
mereka bukanlah orang-orang yang berhak menguasainya. Orang-orang yang
berhak menguasainya hanyalah orang-orang yang bertakwa, tetapi
kebanyakan mereka tidak mengetahui.” (QS. Al-Anfal ayat 34).
Sementara
sihir berasal dari syaitan yang sebabnya adalah kekufuran dan maksiat,
dan hanya berlaku bagi para pelaku kesesatan. Allah Ta’ala berfirman,
وَإنَّ الشَيَاطِينَ لَيُوحُونَ إلىَ أولِيَائِهِم لِيُجَادِلُوكُم وَإنْ أطَعْتُمُوهُم أنَّكُم لَمُشْرِكُونَ
“Sesungguhnya
syaitan-syaitan itu membisikkan kepada kawan-kawannya agar mereka
membantah kamu; dan jika kamu menuruti mereka, sesungguhnya kamu
tentulah menjadi orang-orang yang musyrik.” (QS. Al-An’am ayat 121).
Terjadinya karamah terhadap para wali-wali pada hakikatnya adalah sebuah bentuk mukjizat untuk para nabi 'alaihimussalâm. Karena karamah itu tidak mungkin terjadi untuk salah seorang dari mereka kecuali dengan berkah mutâba'ahnya dia terhadap nabinya dan istiqamahnya dia di atas petunjuk dan syari'at nabinya.
Di antara bentuk karamah yang disebutkan para Salaf adalah istiqamah di atas al-Kitab dan as-Sunnah, taat kepada keduanya, ridha terhadap hukum keduanya dan sejalan dengan keduanya dalam ilmu dan amal.
Tidak adanya karamah pada diri sebagian -bahkan banyak- orang-orang mukmin tidak menunjukkan akan kelemahan iman mereka, jika benar dia seorang muslim yang komitmen terhadap al-Quran dan Sunnah. Karena itu, pada banyak Shahabat radhiyallâhu 'anhum, karamah itu tidak terlihat pada diri-diri mereka, karena kuatnya iman mereka dan sempurnanya keyakinan mereka, yang merupakan salah satu sebab munculnya karamah tersebut.
Di antara sebab lainnya datangnya karamah tersebut pada sebagian mukmin adalah untuk menegakkan hujjah/argumen terhadap musuh.
Sihir dan Ahli Sihir
Terjadinya karamah terhadap para wali-wali pada hakikatnya adalah sebuah bentuk mukjizat untuk para nabi 'alaihimussalâm. Karena karamah itu tidak mungkin terjadi untuk salah seorang dari mereka kecuali dengan berkah mutâba'ahnya dia terhadap nabinya dan istiqamahnya dia di atas petunjuk dan syari'at nabinya.
Di antara bentuk karamah yang disebutkan para Salaf adalah istiqamah di atas al-Kitab dan as-Sunnah, taat kepada keduanya, ridha terhadap hukum keduanya dan sejalan dengan keduanya dalam ilmu dan amal.
Tidak adanya karamah pada diri sebagian -bahkan banyak- orang-orang mukmin tidak menunjukkan akan kelemahan iman mereka, jika benar dia seorang muslim yang komitmen terhadap al-Quran dan Sunnah. Karena itu, pada banyak Shahabat radhiyallâhu 'anhum, karamah itu tidak terlihat pada diri-diri mereka, karena kuatnya iman mereka dan sempurnanya keyakinan mereka, yang merupakan salah satu sebab munculnya karamah tersebut.
Di antara sebab lainnya datangnya karamah tersebut pada sebagian mukmin adalah untuk menegakkan hujjah/argumen terhadap musuh.
Sihir dan Ahli Sihir
Ahlussunnah juga meyakini bahwa di dunia ini terdapat sihir dan ahli sihir. Allah Ta’ala berfirman,
فَلَمَّا جَاءَ السَحَرَةُ
“Maka tatkala ahli-ahli sihir itu datang…” (QS. Yunus ayat 80).
Dan firmanNya,
وَلَكِنَّ الشَيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِحْرَ
“Akan tetapi syaitan-syaitan itulah yang kafir (mengerjakan sihir). Mereka mengajarkan sihir kepada manusia.” (QS. Al-Baqarah ayat 102).
Hanya
saja, sihir dan para pelakunya tidak akan mampu menimpakan keburukan
kepada seseorang kecuali dengan izin Allah sebagaimana dalam firmanNya,
وَمَا هُم بِضَارِّينَ بِهِ مِن أحَدٍ إِلاَّ بِإِذْنِ اللهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُم وَلاَ يَنْفَعُهُمْ
“Dan
mereka itu (ahli sihir) tidak memberi mudharat dengan sihirnya kepada
seorang pun kecuali dengan izin Allah. Dan mereka mempelajari sesuatu
yang memberi mudharat kepadanya dan tidak memberi manfaat.” (QS. Al-Baqarah ayat 102).
Siapa yang
meyakini bahwa sihir itu mampu membahayakan atau memberi kebaikan
dengan sendirinya maka dia kafir. Kaum muslimin telah bersepakat tentang
keharaman sihir. Pelaku sihir diminta untuk bertaubat, jika dia tidak
mau bertaubat maka dia berhak mendapat hukuman mati.
(Sumber : Al Wajîz fî ‘Aqîdah as Salaf ash Shâlih, dengan ringkas)
14 Februari 2016
Siapakah Mereka Para Salaf?
Berikut ini
adalah seorang penanya wanita dari Riyadh, memiliki beberapa pertanyaan.
Ia berkata pada pertanyaan pertama : Saya pernah mendengar tentang
as-Salaf. Syaikh yang mulia, siapakah mereka para Salaf?
Jawab :
“As-Salaf”
maknanya adalah orang-orang yang terdahulu. Setiap orang yang mendahului
orang yang lainnya, maka itu adalah salafnya. Akan tetapi, jika
disebutkan istilah “As-Salaf” secara mutlak, maka yang dimaksudkan
dengannya adalah tiga generasi yang diutamakan; para Sahabat, Tabi’in
dan para pengikut Tabi’in. Merekalah As-Salaf ash-Shalih.
Siapa yang datang setelah mereka, dan berjalan diatas manhaj (metode/jalan) mereka, maka dia juga seperti mereka berada diatas thariqah
(jalan) para as-Salaf walaupun dia datang belakangan dari masa
(kehidupan) mereka. Karena “As-Salafiyyah” dimaksudkan sebagai manhaj
yang ditempuh oleh as-Salaf ash-Shalih radhiyallahu ‘anhum sebagaimana yang disabdakan Nabi ﷺ,
إن أمتي ستفترق على ثلاثة وسبعين فرقة كلها فى النار إلا واحدة وهي الجماعة
“Sesungguhnya umatku akan terpecah kepada 73 golongan, seluruhnya di neraka kecuali satu golongan, yaitu al-Jama’ah.”
Dalam redaksi lain,
من كان على مثل ما أنا عليه و أصحابي
“(Yang selamat adalah) orang yang berada diatas apa yang aku dan sahabat-sahabatku berada diatasnya.”
Dengan
landasan ini, as-Salafiyyah berkait dengan makna. Setiap orang yang
berada diatas manhaj para Sahabat, Tabi’in dan orang-orang yang
mengikuti mereka dengan baik, maka dia adalah “Salafy”, walaupun dia
berada di masa kita sekarang, yaitu abad XIV Hijri.
(Sumber : Fatâwâ Nûr ‘ala ad-Darb)
13 Februari 2016
Firqah Al-Asyâ’irah
Firqah
Asyâ’irah atau sekte Asy’ari adalah sebuah firqah ahli kalam yang
disandarkan kepada Abul Hasan al-Asy’ari yang membelot dari paham
Mu’tazilah. Dalam menetapkan Aqidah Islam, Asya’irah menggunakan
metode-metode akal dan kalam sebagai sarana untuk meruntuhkan argumen
lawan-lawannya dari kalangan Mu’tazilah, ahli filsafat dan lain-lain,
dengan mengikuti prinsip pemikiran Ibnu Kullab.
Sejarah Berdiri
Sekte ini didirikan oleh Abul Hasan al-Asy’ari, yaitu Ali bin Isma’il, dari keturunan Abu Musa al-Asy’ari radhiyallahu ‘anhu. Dilahirkan di Bashrah tahun 270 H dan kehidupan ilmiahnya dilalui dalam tiga fase :
Fase
pertama, ia hidup dalam asuhan Abu Ali al-Jubba’i, tokoh besar
Mu’tazilah pada masanya. Abul Hasan mengambil ilmu darinya hingga
menjadi orang kepercayaannya. Dan Abul Hasan terus memegang kepemimpinan
Mu’tazilah selama 40 tahun.
Fase
kedua, ia mulai mengkritisi pemikiran Mu’tazilah yang dibelanya selama
ini. Setelah berdiam di rumahnya selama 15 hari untuk berpikir, mengkaji
dan beristikharah kepada Allah, jiwanya pun tenang dan mengumumkan
bahwa dirinya berlepas dari pemikiran i’tizâl, dan ia menetapkan sebuah mazhab baru dalam menta’wil nash
(dalil) dengan apa yang disangkanya sesuai dengan rasio. Dalam mazhab
barunya itu, Abul Hasan mengikuti metode yang dipegangi oleh Abdullah
bin Sa’id bin Kullab dalam penetapan sifat-sifat Allah yang tujuh dengan
metode akal, yaitu al-hayâh (kehidupan), al-‘ilm (pengetahuan), al-irâdah (kehendak), al-qudrah (kekuasaan), as-sam’u (pendengaran), al-bashar (penglihatan) dan al-kalâm (berbicara). Adapun sifat-sifat khabariyah (yang bersandar pada khabar/berita tanpa ada peluang akal dalam menetapkannya) seperti al-wajh (wajah), al-yadain
(dua tangan) dan yang semacamnya, ia menta’wilnya kepada apa yang
disangkanya bisa sejalan dengan akal. Inilah fase yang pemahaman Abul
Hasan masih diwarisi oleh pengikut-pengikut firqah Asya’irah sampai hari
ini.
Fase ketiga, menetapkan seluruh sifat-sifat Allah tanpa takyîf, tanpa tasybîh, tanpa ta’thîl dan tanpa tahrîf. Pada fase ini ia menulis kitab “Al-Ibânah ‘an Ushûl ad-Diyânah”
dimana ia mengungkapkan tentang keutamaan aqidah Salaf dan manhaj
mereka, yang salah satu pembawa panjinya adalah Imam Ahmad bin Hanbal.
Tidak cukup dengan itu, bahkan ia meninggalkan tulisan yang begitu
banyak untuk membela Sunnah dan menjelaskan tentang aqidah yang
diperkirakan berjumlah 68 judul buku.
Abul Hasan rahimahullahu wafat pada tahun 324 H dan dimakamkan di Baghdad. Pada hari kematiannya diumumkan : Pada hari ini, telah wafat pembela Sunnah!
Sepeninggal
Abul Hasan al-Asy’ari, dan dibawah kepemimpinan imam-imam mazhab dan
peletak pondasi dasar pemikirannya, mazhab Asy’ari mengalami beberapa
fase perubahan, yang membuat pemikiran-pemikiran dan metode-metode
mereka dalam prinsip-prinsip keyakinan mazhab menjadi bermacam-macam.
Hal itu terjadi karena mazhab ini memang sejak awalnya tidak dibangun
diatas landasan manhaj yang kokoh, yang jelas prinsip aqidahnya, dan
tidak juga memiliki prinsip bagaimana berinteraksi dengan dalil-dalil
syar’i. Mazhab Asy’ari terombang-ambing pendirian dan ijtihad mereka
antara penyesuaian dengan mazhab Salaf dan membantah Mu’tazilah tapi
dengan menggunakan metode ilmu kalam untuk menguatkan aqidah dan menolak
pemikiran Mu’tazilah. Diantara fenomena besar dalam ragam perubahan
mazhab ini adalah :
- Dekat dengan ahli kalam dan penganut mazhab i’tizal
- Masuk kepada pemikiran tasawuf, dan bersinggungannya mazhab Asya’ri dengan tasawuf
- Masuk kepada pemikiran filsafat dan menjadikannya sebagai bagian dari mazhab
- Masuk kepada pemikiran tasawuf, dan bersinggungannya mazhab Asya’ri dengan tasawuf
- Masuk kepada pemikiran filsafat dan menjadikannya sebagai bagian dari mazhab
Diantara Imam-Imam Besar Mazhab Asy’ari
1.
Al-Qâdhi Abu Bakr al-Bâqillâni, Muhammad bin ath-Thayyib bin Muhammad
bin Ja’far (328-403 H). Seorang pembesar ulama ahli kalam. Ia meringkas
tulisan-tulisan ilmiah al-Asy’ari dan berbicara tentang pengantar
dalil-dalil akal dalam persoalan tauhid dan sangat ekstrim dalam
pembahasannya karena perkara ini tidak pernah disebutkan dalam al-Kitab
maupun Sunnah. Kemudian akhirnya ia sampai ke mazhab Salaf, kembali
kepadanya dan menetapkan seluruh sifat-sifat Alah menurut hakikatnya dan
menolak seluruh jenis ta’wil yang digunakan oleh ahli ta’wil dalam
bukunya Tamhîd al Awâ-il wa Talkhîsh ad Dalâ-il. Ia dilahirkan di
Bashrah, bermukim dan wafat di Baghdad. Diantara kitab-kitab yang ditulisnya : I’jâz al Qur-ân, al Inshâf, Manâqib al A-immah, Daqâ-iq al Kalâm, al Milal wa an Nihal, al Istibshâr dan Kasyf Asrâr al Bâthinah.
2. Abu
Ishâq asy-Syîrâzi, Ibrâhim bin Ali bin Yûsuf al-Fairûz Âbâdi asy-Syîrâzi
(393-476 H). Dilahirkan di Fairuzabad, Persia dan berpindah ke Syiraz,
kemudian Bashrah dan darinya ke Baghdad. Terkenal dengan keahliannya dalam
fiqh Syafi’i dan ilmu kalam dan menjadi rujukan bagi para penuntut
ilmu dan mufti umat di masanya. Terkenal dengan kekuatan argumennya
dalam berdebat. Al-Wazir Nizham al-Mulk membangunkan untuknya Madrasah
Nizhamiyah di tepian Sungai Tigris, dan disitulah ia mengajar dan
mengelola madrasah tersebut.
Asy-Syirazi hidup
dalam kefakiran dan bersabar. Seorang yang sangat baik dalam
bermajelis, murah senyum, fasih, pakar dalam debat dan menyusun sya’ir.
Wafat di Baghdad dan dishalatkan oleh al-Muqtadi al-Abbasi. Diantara
buku-bukunya : at Tanbîh, al-Muhadzdzab (dalam fiqh), at Tabshirah (dalam pokok-pokok mazhab Syafi’i), Thabaqât al Fuqahâ’, al Luma’ (dalam ushul fiqh dan penjelasannya) dan lain-lain.
3. Abu
Ishâq al-Isfirâyîni, Ibrâhîm bin Muhammad bin Ibrâhîm bin Mihrân (w. 418
H). Abu Ishaq adalah seorang alim dalam fiqh dan ushul. Ia digelari Rukn ad-Dîn,
dan ia yang pertama digelari dengannya dari kalangan ahli fiqh. Tumbuh
besar di Isfirayin (antara Naisabur dan Jurjan), kemudian pergi ke
Naisabur dan dibuatkan untuknya sebuah madrasah besar dan ia mengajar di
sana. Kemudian ia pergi ke Khurasan dan sebagian negeri di Irak, dan
mulailah namanya dikenal di penjuru dunia Islam saat itu. Ia telah
menuliskan sebuah buku besar dalam ilmu kalam yang diberi judul al Jâmi’ fî Ushûl ad Dîn wa ar Radd ‘alâ al Mulhidîn.
Abu Ishaq wafat pada hari Asyura’ tahun 418 H di Naisabur dalam usia
lebih dari 80 tahun. Jenazahnya dipindahkan ke Isfirayin dan dimakamkan
di sana.
4. Imâm
al-Haramain, Abul Ma’âli al-Juwaini, Abdul Malik bin Abdillâh bin Yûsuf
bin Muhammad al-Juwaini (419-478 H), seorang ahli fiqh mazhab Syafi’i.
Dilahirkan di Juwain, Naisabur, kemudian berkelana ke Baghdad, kemudian
ke Makkah dan berdiam di sana selama 4 tahun. Setelah itu ia pergi ke
Madinah, berfatwa dan mengajar. Kemudian kembali ke Naisabur dan
al-Wazir Nizham a-Mulk membuatkan untuknya Madrasah Nizhamiyah.
Majelisnya dihadiri oleh pembesar-pembesar ulama. Ia tetap dengan
posisinya itu selama 30 tahun tanpa ada tandingan. Menjadi pendukung kuat dan pembela
mazhab Asy’ariyah dan namanya disebut di seluruh penjuru. Hanya saja,
diakhir hayatnya ia kembali ke mazhab Salaf. Ia berkata dalam
risalahnya, an-Nizhamiyyah, “Yang kami ridhai dalam pendapat dan
kami imani Allah dengannya dalam aqidah adalah mengikuti Salaf umat ini
dengan dalil yang sangat jelas bahwa ijma’ umat ini adalah hujjah.”
Abul Ma’ali rahimahullahu wafat di Naisabur dan saat itu ia memiliki 400 murid. Diantara buku-bukunya : al Aqîdah an Nizhâmiyyah fî al Arkân al Islâmiyyah, al Burhân fî Ushûl al Fiqh, Nihâyah al Mathlab fî Dirâyah al Mazhab (dalam fiqh Syafi’i) dan asy Syâmil fî Ushûl ad Dîn.
5. Abu
Hâmid al-Ghazâli, Muhammad bin Muhammad bin Muhammad al-Ghazâli
ath-Thûsi (450-505 H), Hujjatul Islam. Dilahirkan dan wafat di Thabiran,
daerah Thus, Khurasan. Ia berkelana ke Naisabur, kemudian ke Baghdad,
Hejaz, negeri Syam dan Mesir, kemudian kembali lagi ke negerinya.
Al-Ghazali
tidak menempuh metode al-Baqillani, bahkan ia menyelisihi al-Asy’ari
dalam sebagian pendapat, khususnya yang berkait dengan muqaddimah ‘aqliyyah
dalam berdalil. Ia mencela ilmu kalam dan menjelaskan bahwa ilmu kalam
tidak memberikan keyakinan sebagaimana yang ia sebutkan dalam al Munqidz min adh Dhalâl dan at Tafriqah baina al Imân wa az Zandaqah.
Ia berkata, “Kalau kami tinggalkan bermanis-manis muka, niscaya kami
akan berterus terang bahwa masuk dalam ilmu kalam adalah haram!” Ia
kemudian cenderung kepada tasawuf dan meyakini bahwa itulah satu-satunya
jalan kepada ma’rifah. Di akhir hayatnya, ia kembali kepada Sunnah di
sela-sela pengkajiannya terhadap Shahîh al-Bukhâry.
6. Al-Imam
al-Fakr ar-Râzy, Abu Abdillah Muhammad bin Umar bin al-Hasan bin
al-Husain at-Taimi ath-Thabaristâni ar-Râzi, digelari Fakhruddin,
yang dikenal dengan nama Ibnul Khathîb al-Faqîh asy-Syâfi’i. Ialah yang
menjadi “juru bicara” mazhab al-Asy’ari di fase terakhirnya, dimana ia
mencampur adukkan ilmu kalam dengan filsafat. Ia sangat membela akal dan
mendahulukannya di atas dalil-dalil syar’i. Hanya saja, ia akhirnya
memahami tentang lemahnya akal manusia dan berwasiat dengan sebuah
wasiat yang memberikan petunjuk akan baiknya aqidahnya. Di akhir
hidupnya, ia menekankan pentingnya mengikuti manhaj para Salaf, dan
mengumumkan bahwa itulah manhaj yang paling selamat.
Pokok Aqidah dan Pemikiran Mazhab Asy'ari
Diantara pokok-pokok aqidah yang diyakini oleh mazhab Asy’ari adalah sebagai berikut :
1. Sumber
talaqqî dalam mazhab Asy’ari adalah al-Kitab dan as-Sunnah sesuai dengan
konsekuensi kaedah-kaedah ilmu Kalam. Karenanya, mereka lebih
mendahulukan akal daripada dalil ketika terjadi kontradiksi.
2. Mereka tidak berhujjah dengan hadits Ahad dalam perkara aqidah karena hal itu menurut mereka tidak memberikan al-‘ilm al-yaqînî (ilmu yang yakin tanpa ada keraguan).
3. Mazhab
Asy’ari menyelisihi aqidah Salaf dalam penetapan wujud Allah Ta’ala.
Mereka sepakat dengan para ahli filsafat dan ahli kalam dalam berdalil
tentang wujud Allah dengan perkataan mereka: “Alam ini adalah hâdits (sesuatu yang baru dan diadakan). Maka tidak boleh tidak, alam ini harus memiliki muhdits qadîm (Dzat yang mengadakannya, yang memiliki sifat qadîm/terdahulu tanpa permulaan). Dan yang terkhusus dari sifat al-Qadîm adalah mukhâlafatuhu li al-hawâdits (berbeda dari segala apa yang ada) dan tidak bercampurnya Dia pada hawâdits tersebut. Termasuk dalam sifat mukhâlafah-nya li al-hawâdits adalah : Dia bukan materi, bukan jasad, tidak berada di arah atau tempat tertentu.” (astaghfirullah!)
Konsekuensi
dari perkataan ini, mereka membangun diatasnya prinsip-prinsip
keyakinan yang rusak yang tidak terbatas seperti pengingkaran mereka
terhadap sifat-sifat ar-ridhâ (keridhaan), al-ghadhab (marah) dan al-istiwâ’ (bersemayam diatas ‘Arsy), dengan dalih menolak bercampurnya “al-hawâdits” pada “al-Qadîm” demi untuk membantah pemahaman tentang qadîm-nya alam ini. Sementara metode para Salaf adalah metode al-Quran dalam berdalil tentang wujudnya al-Khaliq subhanahu wa ta’ala.
4. Tauhid
menurut Asy’ari adalah meniadakan berbilangnya Dzat dan menolak
pembagian, susunan dan potongan. Dalam perkara ini mereka mengatakan :
Sesungguhnya Allah itu Esa dalam Dzat-Nya tidak ada pembagian untuk-Nya,
Esa dalam sifat-sifatNya tidak ada yang serupa dengan-Nya dan Esa dalam
perbuatan-Nya tidak ada sekutu bagi-Nya. Karenanya, mereka menafsirkan al-Ilâh sebagai al-Khâliq (Pencipta) atau al-Qâdir
(Yang berkuasa) dalam penciptaan. Dan mereka mengingkari sifat-sifat
wajah, dua tangan dan mata, karena hal-hal itu –menurut mereka- membawa
kepada pemahaman tentang adanya susunan dan bagian-bagian. Dengan ini,
mazhab Asy’ari hanya menjadikan tauhid terbatas pada penetapan tauhid
rububiyah Allah ‘azza wa jalla tanpa uluhiyyah-Nya dan menta’wil sebagian sifat-sifatNya.
Mereka juga meyakini wajibnya menta’wil sifat-sifat khabariyyah seperti wajah, dua tangan, mata, tangan kanan, telapak kaki dan jari-jari, dan juga sifat al-‘uluww (ketinggian) dan al-istiwâ’. Ulama-ulama mereka yang belakangan cenderung kepada mazhab tafwîdh,
yaitu menyerahkan makna-makna sifat-sifat tersebut kepada Allah Ta’ala
dengan keyakinan bahwa hal itu merupakan kewajiban sebagai konsekuensi
dari pensucian Allah Ta’ala. Tidak cukup dengan itu, mereka bahkan juga
melebar dalam masalah ta’wil hingga mencakup sebagian besar dalil-dalil
tentang keimanan, khususnya yang berkait dengan bertambah dan
berkurangnya iman, serta persoalan kema’shuman para nabi.
5. Mazhab
Asy’ari dalam persoalan iman berada diantara pemikiran Murji’ah yang
mengatakan cukup mengucapkan syahadatain untuk sahnya iman seseorang
tanpa perlu adanya amal, dan antara pemikiran Jahmiyah yang mengatakan
cukup dengan pembenaran dalam hati. Hal ini sangat bertentangan dengan
prinsip Ahlussunnah wal Jama’ah yang mengatakan bahwa iman adalah
ucapan, amal dan keyakinan hati, dan menyelisihi dalil-dalil al-Quran
yang sangat banyak.
6. Mazhab Asy’ari bimbang dalam persoalan takfîr
(vonis kafir). Terkadang mereka mengatakan: Kami tidak mengkafirkan
seorang pun; terkadang mereka mengatakan: Kami tidak mengkafirkan
kecuali siapa yang kami kafirkan; dan terkadang mereka mengatakan
tentang perkara-perkara yang mewajibkan vonis fasik dan bid’ah atau
perkara-perkara yang tidak berkonsekuensi pada vonis kafir dan bid’ah.
Adapun
Ahlussunnah wal Jama’ah memandang bahwa takfir adalah hak Allah yang
tidak dijatuhkan kecuali kepada yang berhak sesuai dengan pandangan
syar’i. Dan tidak ada keraguan untuk menetapkannya kepada orang yang
telah pasti kekufurannya dengan adanya syarat-syarat takfir dan
hilangnya penghalang-penghalang untuk jatuhnya vonis tersebut.
7. Mereka mengatakan bahwa al-Quran bukanlah Kalâm Allah menurut hakikatnya, akan tetapi ia adalah kalâm nafsî, dan bahwa kitab-kitab yang diturunkan adalah makhluk.
8. Mereka
mengatakan bahwa Allah bisa dilihat. Allah ada dan bisa dillihat dengan
pandangan. Akan tetapi, mereka beranggapan bahwa pandangan tersebut
tidak boleh dikaitkan dengan arah, tempat, bentuk dan saling berhadapan,
karena yang demikian itu adalah perkara yang mustahil. Pendapat mereka
ini meniadakan sifat ketinggian Allah dan arahnya, bahkan meniadakan
penglihatan itu sendiri.
9. Pelaku
dosa besar jika keluar dari dunia ini tanpa taubat maka hukumnya
dikembalikan kepada Allah; Dia akan mengampuninya dengan kasih
sayangNya, atau diberikan syafa’at oleh Nabi ﷺ . Hal ini selaras dengan mazhab Ahlussunnah wal Jama’ah.
10. Mazhab Asy’ari meyakini bahwa kemampuan (qudrah)
seorang hamba tidak memiliki pengaruh terhadap apa yang ada dalam
kemampuannya itu (perbuatannya), tidak pula pada salah satu dari
sifat-sifatNya. Dan Allah memperjalankan sebuah kebiasaan (perbuatan)
dengan menciptakan apa yang dalam kemampuannya itu, selaras dengannya.
Dengan demikian, perbuatan hamba tersebut adalah ciptaan (khalq) dari Allah Ta’ala, dan usaha (kasb) dari hamba untuk terjadinya hal itu yang sejalan dengan kemampuannya.
11. Mazhab Asy’ari sejalan dengan Ahlussunnah dalam iman tentang alam barzakh dan perkara-perkara akhirat; mahsyar, timbangan, shirât, syafa’at, surga dan neraka.
12. Mereka
juga sejalan dalam persoalan para Shahabat, urutan khilafah mereka, dan
apa yang terjadi diantara mereka adalah perkara ijtihad yang bersumber
dari mereka. Karenanya, wajib menahan diri untuk berbicara tentang
perselisihan yang terjadi diantara para Shahabat, karena celaan terhadap
mereka akan berkonsekuensi pada kekufuran, atau bid’ah atau kefasikan.
Mereka juga memandang bahwa khilafah untuk Quraisy, boleh shalat di
belakang imam yang baik maupun jahat, tidak boleh memberontak terhadap
para penguasa yang zalim, dan perkara-perkara ibadah dan mu’amalah
lainnya.
(Sumber : Al-Mausû’ah al-Muyassarah fî al-Adyân wa al-Madzâhib wa al-Ahzâb al-Mu’âshirah, WAMY, cet. tahun 1424, Saudi Arabia)
11 Februari 2016
Ta’at kepada Penguasa Muslim dalam Perkara yang Ma’ruf
Diantara
prinsip aqidah as-Salaf ash-Shalih, Ahlussunnah wal Jama’ah; mereka
memandang wajibnya mematuhi dan mentaati para penguasa kaum muslimin
selama mereka tidak menyuruh kepada maksiat terhadap Allah Ta’ala.
Jika
mereka menyuruh kepada perkara maksiat, tidak boleh mentaati perintah
mereka dalam perkara tersebut, namun tetap wajib tunduk dan patuh dalam
perkara-perkara lainnya.
Prinsip
ini, yaitu taat kepada para penguasa muslim dalam perkara yang ma’ruf,
adalah sebuah prinsip yang sangat agung dan mendasar dalam aqidah Islam.
Karenanya, ulama Salaf memasukkannya dalam bagian prinsip-prinsip dasar
aqidah. Hampir tidak ada satu buku aqidah yang ditulis oleh para imam,
melainkan padanya terdapat penyebutan dan penjelasan dari prinsip
tersebut.
Ketaatan
terhadap penguasa ini adalah kewajiban syar’i bagi setiap muslim, tidak
akan terwujud ketenangan dan stabilitas dalam sebuah negara tanpa adanya
ketaatan terhadap penguasa.
Allah Ta’ala berfirman,
يَا
أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا أطِيْعُوا اللهَ وَأَطِيْعُوا الرَسُوْلَ
وَأُولِى الأمْرِ مِنْكُمْ، فَإِن تَنَازَعْتُم فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ
إِلىَ اللهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ وَاليَوْمِ
الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَاْوِيْلاً
“Hai
orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah rasul, dan ulil
amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berselisih pendapat tentang
sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan rasul jika kamu
benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu
lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (QS. An-Nisa’ ayat 59).
Dan dalam hadits-hadits shahih;
Abu Bakrah radhiyallahu ‘anhu meriwayatkan dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,
إن السلطان ظل الله فى الأرض، فمن أكرمه أكرمه الله و من أهانه أهانه الله
“Sesungguhnya
penguasa adalah naungan Allah di muka bumi. Siapa yang memuliakan
penguasa, niscaya Allah akan memuliakannya, dan siapa yang menghinakan
penguasa, niscaya Allah akan menghinakannya.” (HR. Ibnu Abi ‘Ashim, dishahihkan Al-Albani).
Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, ia berkata : Rasulullah ﷺ bersabda,
من أطاعني فقد أطاع الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعصى الامير فقد عصاني
“Barangsiapa
yang taat kepadaku, maka sungguh dia telah taat kepada Allah.
Barangsiapa taat kepada penguasa, maka dia telah taat kepadaku. Dan
barangsiapa yang membangkang kepada penguasa maka dia telah bermaksiat
kepadaku.” (HR. Al-Bukhari dan Muslim).
Dari ‘Auf bin Malik radhiyallahu ‘anhu ia berkata : Rasulullah ﷺ bersabda,
ألا من ولي عليه والٍ فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره الذي يأتي من معصية الله ولا ينزع يدا من طاعة
“Ketahuilah,
barangsiapa yang berkuasa atasnya seorang pemimpin, dan dia melihatnya
melakukan sesuatu perbuatan maksiat kepada Allah, maka bencilah
perbuatannya tersebut dan jangan melepaskan tangan dari ketaatan!” (HR. Muslim).
Beliau ﷺ bersabda kepada Hudzaifah radhiyallahu ‘anhu,
تسمع وتطيع للأمير وإن ضُرب ظهرك وَأُخِذَ مالُك، فاسمعْ وأطعْ
“Engkau mendengar dan taat kepada penguasa, walaupun punggungmu dicambuk dan hartamu dirampas. Dengar dan taatlah!” (HR. Muslim).
Dan pesan beliau ﷺ kepada para shahabatnya,
اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبدٌ حبشيٌّ كأن رأسه زبيبة
“Mendengar dan taatlah, walaupun berkuasa atas kalian seorang budak Habasyi seakan-akan kepalanya seperti anggur kering.” (HR. Al-Bukhary).
08 Februari 2016
Wanita yang Haram Dinikahi karena Penyusuan
Diharamkan bagi seorang laki-laki menikahi wanita yang keduanya pernah menyusu pada satu ibu susu.
Allah Ta’ala berfirman,
وَأمَّهَاتُكُمُ اللاَتِي أرْضَعْنَكُم وَأخَوَاتُكُم مِنَ الرَضَاعَةِ
“(Dan diharamkan atas kamu menikahi) ibu-ibumu yang menyusui kamu dan saudara-saudara perempuanmu sepersusuan.” (QS. An-Nisa’ ayat 23).
Dan Nabi ﷺ bersabda,
الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة
“Penyusuan mengharamkan (pernikahan) seperti apa yang diharamkan oleh (sebab) kelahiran.” (HR. Al-Bukhary dan Muslim).
Dengan ini bisa dipahami, pengharaman menikahi seorang wanita karena penyusuan sama seperti diharamkannya menikahi seorang wanita disebabkan oleh pertalian nasab/garis keturunan, yaitu dengan menjadikan status wanita yang menyusui sama seperti seorang ibu.
Wanita-wanita yang haram dinikahi oleh seorang laki-laki yang disebabkan oleh penyusuan tersebut adalah sebagai berikut,
1. Wanita yang menyusui dan ibunya. (karena mereka berstatus sebagai ibunya dan neneknya)
2. Anak-anak perempuan dari ibu susu, baik yang dilahirkan sebelum kelahirannya atau sesudahnya. (karena mereka adalah saudarinya)
3. Saudara perempuan ibu susu. (karena ia adalah bibinya dari pihak ibu susunya)
4. Anak perempuan dari anak perempuan dan anak laki-laki ibu susunya. (karena mereka adalah anak saudari dan saudaranya)
5. Ibu dari suami ibu susu yang air susunya datang darinya disebabkan kehamilan yang terjadi darinya. (karena wanita itu adalah neneknya)
6. Saudara perempuan suami ibu susu. (karena ia adalah bibinya dari pihak ayah susu)
7. Anak perempuan dari suami ibu susu, walaupun dari istri lainnya. (karena ia adalah saudarinya dari pihak ayah susunya)
8. Istri lain dari bapak susunya. (karena mereka adalah istri ayahnya)
9. Istri anak susu haram dinikahi oleh suami ibu susunya. (karena ia adalah istri anaknya).
Sebab pengharaman ini adalah air susu yang keluar dari seorang ibu karena kehamilan dari suaminya. Jika bayi tumbuh dari air susu itu, maka dia menjadi bagian dari kedua pasangan suami istri tersebut.
Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu ‘anha, bahwa Nabi ﷺ menyuruhnya untuk mengizinkan masuk Aflah, saudara Abul Qu’ais yang merupakan paman susu Aisyah. (HR. Al-Bukhary dan Muslim).
Ibnu Abbas radhiyallahu ‘anhuma ditanya tentang seorang laki-laki yang memiliki dua istri, salah satunya menyusui seorang anak laki-laki, dan yang lainnya menyusui anak perempuan. Ditanyakan padanya, “Apakah boleh anak laki-laki itu menikahi anak perempuan tersebut?” Ia menjawab, “Tidak boleh, (karena) benihnya satu.” (Riwayat Malik, At-Tirmidzi dan lain-lain dengan sanad yang shahih sampai ke Ibnu Abbas).
Maksud perkataan Ibnu Abbas, bahwa air susu yang keluar dari kedua wanita tersebut disebabkan oleh kehamilan yang berasal dari satu orang.
Jika bayi yang menyusu adalah anak perempuan, maka dia haram dinikahi oleh suami dari ibu yang menyusuinya (karena ia adalah ayahnya), saudara dari ibu susunya (karena ia adalah pamannya), bapak dari ayah dan ibu susunya (karena ia adalah kakeknya), dan seterusnya.
Hukum pengharaman ini hanya berlaku bagi si bayi yang menyusu, dan tidak berkonsekuensi pada seorang pun dari kerabatnya. Karenanya, saudari sesusuannya bukanlah saudari untuk saudara kandungnya yang lain. Kaedahnya dalam masalah ini : “semua orang yang berkumpul pada satu air susu, maka mereka semua menjadi bersaudara”.
Maka, misalkan, saudara kandung anak susu itu yang tidak ikut menyusu bersama mereka, dia boleh menikahi anak perempuan ibu susu saudaranya, karena wanita itu seorang ajnabî (bukan mahram) walaupun dia adalah saudara sesusuan bagi saudara kandungnya.
Wallahu a’lam.
(Sumber : Shahîh Fiqh as-Sunnah)
04 Februari 2016
Alangkah Indahnya Sifat Qona’ah
Alangkah indahnya sifat qonâ’ah… Yaitu merasa cukup dan ridha dengan apa yang telah Allah anugerahkan kepada dirinya.
Orang yang
komitmen dengan sifat ini, dia akan menggapai kebahagiaan.
Kalau saja
manusia menghiasi diri mereka dengan sifat ini, niscaya akan hilang dari
mereka sifat dengki dan hasad. Karena banyak perselisihan dan
perpecahan yang terjadi di antara manusia disebabkan oleh dunia dan
berlomba-lomba kepada dunia itu. Tidaklah melemah agama yang ada dalam
hati-hati manusia melainkan disebabkan oleh terjerumusnya mereka kepada
gemerlapnya dunia dan keindahannya. Benarlah Rasulullah ﷺ ketika beliau
bersabda,
وَاللهِ
مَا الفقرُ أخشَى عَليكم، وَلكنِي أخشَى أن تُبسَطَ الدُنيا عَليكم؛ كمَا
بُسِطت علىَ مَن كانَ قَبلكم فتنافسُوهَا كمَا تَنافسُوهَا وَتُهلِككم كمَا
أهْلكتهُم
“Demi
Allah, tidaklah kemiskinan yang aku takutkan atas kalian, akan tetapi
aku khawatir jika dunia dilapangkan kepada kalian sebagaimana dahulu
pernah dilapangkan kepada orang-orang sebelum kamu, kalian
berlomba-lomba kepadanya sebagaimana mereka berlomba-lomba, hingga
akhirnya dunia itu membinasakan kalian sebagaimana dia telah
membinasakan mereka.” (HR. Al-Bukhary).
Karenanya, diantara doa Nabi ﷺ adalah,
اللهُمَّ
إنِي أعُوذ بِكَ مِن قلبٍ لاَ يَخشَعُ، وَمِن دُعَاءٍ لاَ يُسْمَعُ، وَمِن
نَفْسٍ لاَ تَشْبَعُ، وَمِن عِلمٍ لاَ يَنفعُ، أعُوذ بِكَ مِن هَؤلاَءِ
الأربَع
“Ya
Allah, aku berlindung kepadaMu dari hati yang tidak khusyu’, dari doa
yang tidak didengarkan, dari jiwa yang tidak pernah puas dan dari ilmu
yang tidak bermanfaat. Aku berlindung kepadaMu dari empat perkara itu.” (HR. At-Tirmidzi, no. 3482, dishahihkan Al-Albani).
Berkata Imam an-Nawawi rahimahullahu,
“Perkataan beliau ﷺ : ‘Dari jiwa yang tidak pernah puas’, yaitu memohon
perlindungan dari kerakusan, ketamakan, keserakahan dan ketergantungan
jiwa dengan impian-impian yang jauh.” (Syarh Shahîh Muslim, XVII/41).
Wallahu a’lam.
01 Februari 2016
Hadits Al-Mursal Al-Khafiy
Jenis kedua dari jenis saqth khafiy dari sebab-sebab tertolaknya sebuah hadits disebabkan gugurnya seseorang atau beberapa perawi dalam sebuah sanad adalah al-mursal al-khafiy.
Menurut istilah, mursal khafiy
(المرسل الخفيّ) adalah sebuah kasus dimana seorang perawi meriwayatkan sebuah riwayat
dari seseorang yang pernah ia jumpai atau hidup semasa dengannya, yang riwayat
itu tidak pernah ia dengarkan dari orang tersebut, dan dalam periwayatan ia
menggunakan istilah yang mengandung kemungkinan pendengaran secara
langsung atau yang semacamnya, seperti perkataannya: “Ia berkata.”
Contoh
dari kasus ini adalah hadits yang diriwayatkan Ibnu Majah dari jalan
periwayatan 'Umar bin 'Abdil 'Aziz, dari 'Uqbah bin ‘Amir secara marfu’,
رحم الله حارس الحرس
“Semoga Allah merahmati orang yang menjaga (perkemahan) pasukan.”
'Umar bin 'Abdil 'Aziz tidak pernah berjumpa dengan 'Uqbah, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Mizzi rahimahullahu dalam kitab Al-Athrâf.
Dengan Apa Diketahui Irsal Khafiy?
Irsal khafiy bisa diketahui dengan salah satu dari tiga perkara,
- Pernyataan sebagian imam/ulama bahwa si perawi tidak pernah berjumpa dengan orang yang ia sampaikan hadits darinya, atau tidak pernah mendengarkannya secara mutlak
- Perawi tersebut mengabarkan sendiri tentang dirinya bahwa ia tidak pernah berjumpa dengan orang itu atau belum pernah mendengarkan sesuatu pun darinya
- Datangnya hadits tersebut dari jalan periwayatan yang lain; padanya terdapat tambahan perawi lain antara si perawi dengan orang yang ia riwayatkan darinya hadits tersebut
Bentuk ketiga diperselisihkan oleh para ulama, karena ia bisa saja masuk dalam jenis al-mazîd fî muttashil al-asânîd (insyaallah akan datang penjelasannya pada tempatnya)
Hukum Mursal Khafiy
Mursal khafiy termasuk hadits dha’if karena masuk dalam jenis hadits munqathi’. Jika telah jelas bentuk inqitha’ dalam sanadnya, maka hukumnya adalah hukum munqathi’.