Al-Irjâ’ menurut bahasa memiliki beberapa makna diantaranya adalah harapan (al amal), rasa takut (al khauf), penundaan (at ta’khîr), pemberian harapan (i’thâ’ ar rajâ’).
Menurut istilah, para ulama berbeda pendapat tentang makna sebenarnya dari kata al-Irja’.
Sebagian mengatakan bahwa al-irja’
menurut istilah kembali kepada makna bahasanya, yaitu bermakna
penundaan, yaitu penundaan atau mengakhirkan amal dari level keimanan
dan menjadikannya pada level kedua, yang bermakna bahwa amal itu
bukanlah bagian dari definisi iman. Iman mencakup amalan dari sisi
majaz, sementara hakikat sebenarnya adalah sekedar pembenaran (at tashdîq).
Sebagian lain berpendapat bahwa yang dimaksudkan dengan al-irja’
adalah menunda hukum pelaku dosa besar hingga hari Kiamat nanti,
dan tidak divonis dengan hukum tertentu dalam kehidupan dunia ini.
Sebagian
lagi mengaitkannya dengan fitnah yang terjadi diantara para Shahabat,
yaitu menunda atau mengembalikan perkara yang terjadi antara Utsman dan
Ali radhiyallahu ‘anhuma, atau antara Ali dan Mu’awiyah kepada
Allah Ta’ala, serta tidak menghukumi salah satu diantara mereka dengan
keimanan atau kekafiran.
Pondasi yang Dibangun diatasnya Mazhab Murji’ah
Pondasi
itu adalah perselisihan tentang hakikat keimanan; iman itu terdiri dari
apa, apa saja batasan maknanya, apakah iman hanya perbuatan hati saja,
ataukah dia perbuatan hati dan lisan, dan amalan tidak termasuk bagian
dari hakikat iman tersebut, yang konsekuensinya iman itu tidak akan
bertambah dan berkurang. Itulah poin-poin terpenting yang menjadi
pembahasan firqah-firqah Murji’ah.
- Sebagian
besar firqah-firqah Murji’ah berpendapat bahwa iman hanyalah apa yang
ada di dalam hati, dan tidak akan membahayakannya apa yang nampak dari
amal perbuatannya bahkan walaupun hal itu berupa kekafiran dan
pembangkangan. Inilah mazhab al-Jahm bin Shafwan. Dalam pandangannya,
pengakuan dengan lisan dan amalan bukanlah perkara penting karena hal
itu bukanlah bagian dari hakikat keimanan.
-
Al-Karramiyyah berpendapat bahwa iman adalah ucapan dengan lisan, dan
tidak akan berbahaya setelahnya menyembunyikan keyakinan apapun bahkan
walaupun hal itu berupa kekafiran.
- Sementara Abu Hanifah rahimahullahu
berpendapat bahwa iman adalah pembenaran dengan hati dan ucapan dengan
lisan, satu dengan yang lainnya akan saling membutuhkan. Siapa yang
membenarkan dengan hatinya dan terang-terangan mendustakan dengan
lisannya, maka ia tidak disebut sebagai mukmin. Diatas keyakinan inilah
tegak mazhab Hanafi, dan inilah pemahaman Murji’ah yang paling dekat
kepada Ahlussunnah karena mereka sepakat dengan Ahlussunnah bahwa pelaku
maksiat berada dalam kehendak (masyî-ah) Allah dan dia tidak keluar dari keimanannya.
Bagaimana Pemahaman Irja’ itu Muncul?
Al-irja’
pada permulaannya dimaksudkan –dalam sebagian definisinya- sebuah sikap
yang diambil oleh orang-orang yang menginginkan keselamatan, menjauhkan
perselisihan dan meninggalkan pertikaian dalam urusan-urusan politik
dan keagamaan, khususnya yang berkait dengan hukum-hukum akhirat;
tentang keimanan, kekafiran, surga dan neraka, demikian pula yang
berkait dengan perkara tentang Ali, Utsman, Thalhah, az-Zubair, Ummul
Mukminin Aisyah dan apa yang terjadi antara Ali dan Mu’awiyah.
Setelah terbunuhnya Utsman radhiyallahu ‘anhu dan kemunculan Khawarij dan Syi’ah, maka mulailah pemahaman irja’ berkembang secara bertahap.
Bagaimana Pemahaman Irja’ Berkembang menjadi sebuah Mazhab?
Ketika
terjadi perselisihan tentang hukum pelaku dosa besar dan perselisihan
tentang kedudukan amal dalam iman, maka muncullah sekelompok orang yang
membawa pemahaman irja’ kepada sikap ekstrim dan melampaui batas yang tercela. Maka mulailah pemahaman irja’
terbentuk dalam sifatnya sebagai sebuah mazhab. Mereka menetapkan bahwa
pelaku dosa besar memiliki iman yang sempurna, maksiat tidak akan
membahayakan iman dan ketaatan tidak akan bermanfaat bagi kekafiran,
iman itu tempatnya di hati sehingga tidak akan membahayakan seseorang
apapun yang dilakukannya sesudah itu. Walaupun dia melafalkan kekafiran
dan pembangkangan, imannya tetap sempurna dan tidak tergoyahkan.
Tidak diragukan bahwa keyakinan seperti ini adalah pemahaman yang buruk dan sikap melampaui batas. Para penganut paham irja’
dalam level ini adalah orang-orang yang sangat tercela dan mazhab
mereka akan membawa manusia kepada kemalasan, menghalalkan segala cara
dan bersandar secara keliru kepada sifat pengampun Allah Ta’ala tanpa
mau beramal.
Siapa yang Pertama Kali Berbicara tentang Irja’?
Para ulama
menyebutkan bahwa al-Hasan bin Muhammad bin al-Hanafiyyah adalah orang
yang pertama kali menyebutkan tentang pemahaman irja’ di kota
Madinah, khususnya yang berkait dengan Ali, Utsman, Thalhah dan
az-Zubair ketika manusia memperbincang pribadi-pribadi yang mulia itu
dan al-Hasan berdiam diri. Kemudian ia berkata, “Aku telah mendengarkan
pembicaraan kalian, dan aku tidak melihat sesuatu yang lebih pantas
selain menunda/mendiamkan (perkara) Ali, Utsman, Thalhah dan az-Zubair.
Tidak memberikan wala’ (loyalitas) kepada mereka dan tidak juga berlepas diri.”
Akan
tetapi, al-Hasan telah menyesali perkataannya tersebut dan
berandai-andai kalau saja ia telah meninggal sebelum mengucapkannya.
Perkataannya inilah yang menjadi jalan pembuka untuk tumbuhnya pemahaman
irja’. Perkataannya itu sampai kepada ayahnya, Muhammad bin
al-Hanafiyyah, dan ia pun memukul al-Hasan sampai melukainya dan
berkata, “Engkau tidak membela ayahmu, Ali?!”
Orang-orang
yang mengambil perkataan itu dari al-Hasan tidak pernah mau melihat
kepada penyesalan al-Hasan. Perkataan itu menyebar di kalangan manusia
dan berjumpa dengan hawa nafsu dalam jiwa-jiwa beberapa kalangan dan
menjadikannya sebagai sebuah keyakinan.
Pendapat lain mengatakan bahwa yang pertama kali berbicara tentang irja’
dalam bentuk ekstrimnya adalah seseorang yang disebut Dzirr bin
Abdillah al-Hamadani dari masa generasi Tabi’in. Para ulama di masa itu
telah mengecam Dzirr, bahkan sebagian mereka tidak menjawab salamnya
karena ia mengeluarkan amal dari definisi iman.
Pendapat lain : Yang pertama mengadakan pemikiran irja’ adalah seorang laki-laki di Irak yang bernama Qais bin ‘Amr al-Madhiri.
Pendapat
lain : Yang pertama mengadakan bid’ah ini adalah Hammad bin Abi
Sulaiman, guru Abu Hanifah dan murid dari Ibrahim an-Nakha’i, rahimahumullahu.
Dan pemikiran itu tersebar di kalangan penduduk Kufah, Irak. Syaikhul
Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan bahwa yang pertama kali menyebutkan irja’ di kalangan penduduk Kufah adalah Hammad.
Pemahaman irja’ para imam inilah yang dikenal sebagai irja’nya para ahli fiqh (irja-ul fuqaha’).
Pendapat lainnya lagi mengatakan bahwa yang pertama kali berbicara tentang irja’ adalah seseorang yang bernama Salim al-Afthas.
Yang nampak, wallahu a’lam, pendapat-pendapat itu tidaklah saling berjauhan karena mereka hidup dalam masa yang sama.
Siapa Tokoh-Tokoh Besar Murji’ah?
Yang kami
maksudkan adalah kalangan Murji’ah ekstrim yang dengannya Murji’ah
dikenal sebagai sebuah firqah/sekte sesat dan keyakinannya bertolak
belakang dengan aqidah Ahlussunnah wal Jama’ah.
Mereka
adalah al-Jahm bin Shafwan, Abul Husain ash-Shalihi, Yunus as-Samri, Abu
Tsauban, al-Husain bin Muhammad an-Najjar, Ghailan ad-Dimasyqi,
Muhammad bin Syabib, Bisry al-Mirrisi, Muhammad bin Karram, Muqatil bin
Sulaiman yang menyerupakan Allah ‘azza wa jalla dengan makhlukNya, dan yang serupa dengannya, yaitu al-Jawaribi. Keduanya termasuk golongan musyabbihah ekstrim.
Prinsip-Prinsip Keyakinan Murji’ah
1. Iman menurut mereka adalah pembenaran (at-tashdîq) dengan ucapan, atau pengetahuan (al-ma’rifah), atau pengakuan (al-iqrâr).
Amal tidaklah masuk dalam hakikat keimanan, dan bukan bagian darinya,
walaupun sebenarnya mereka tidak mengabaikan sepenuhnya kedudukan amal
dalam iman, kecuali pandangan sesatnya al-Jahm bin Shafwan.
2. Iman
tidak bertambah dan tidak berkurang, karena pembenaran terhadap sesuatu
dan pemastiannya tidak akan memberikan tambahan apapun atau pengurangan.
Karenanya, menurut mereka, para pelaku maksiat memiliki iman yang
sempurna dengan kesempurnaan pembenaran mereka (at-tashdiq), dan mereka dipastikan tidak akan masuk neraka di akhirat nanti.
3. Sebagian sekte mereka meyakini bahwa manusialah yang menciptakan perbuatan mereka sendiri.
4. Mereka juga mengimani bahwa Allah tidak dapat dilihat di akhirat nanti.
5. Al-Imâmah
(kepemimpinan) bukanlah perkara wajib dalam pandangan mereka. Kalau
imamah itu mesti ditegakkan, maka ia bisa dijabat oleh siapapun walaupun
bukan berasal dari Quraisy.
6.
Diantara keyakinan Murji’ah bahwa kufur kepada Allah adalah kejahilan
tentang Dia. Itulah perkataan al-Jahm. Dan iman itu hanyalah mengenal
Allah (ma’rifah) saja dan iman itu tidak terbagi-bagi.
7. Mereka
juga meyakini bahwa surga dan neraka tidaklah kekal. Demikian juga
dengan penghuni keduanya, dan tidak ada keabadian pada keduanya.
8.
Sebagian mereka berkeyakinan bahwa setiap maksiat adalah dosa besar, dan
sebagian mereka juga berpendapat bahwa ampunan Allah terhadap dosa-dosa
dengan taubat adalah bentuk keutamaan yang datang dari Allah dan
sebagian mengatakannya sebagai sebuah keharusan.
9. Sebagian mereka membolehkan terjadinya perbuatan dosa besar dari para nabi ‘alaihimussalam.
10.
Sebagian mereka juga menetapkan mungkinnya melihat Allah di akhirat,
sementara sebagian lainnya menolaknya sebagaimana pandangan Mu’tazilah.
11. Mereka
berselisih dalam pandangan tentang perkataan bahwa al-Quran adalah
makhluk. Sebagian mengatakan bahwa al-Quran adalah makhluk, sebagian
berpendapat bukan makhluk dan sebagian lagi mengambil sikap diam (tawaqquf).
12. Mereka juga berbeda pendapat tentang masalah takdir. Sebagian menolaknya dan sebagian menetapkannya.
13. Dan mereka juga berbeda pendapat dalam persoalan al-asmâ’ wa ash-shifât
(nama-nama dan sifat-sifat Allah). Sebagian Murji’ah mengikuti
pendapatnya Abdullah bin Kullab, dan sebagian lainnya mengikuti metode
Mu’tazilah.
Wallahu a’lam.
----------------------
Sumber bacaan : Firaq Mu’âshirah Tantasib ilâ al Islâm, Syaikh Dr. Ghalib bin Ali ‘Awaji







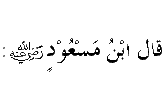

0 tanggapan:
Posting Komentar