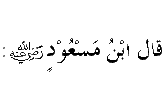30 Maret 2015
Apa yang Dimaksud "Wahyu"?
Menurut istilah syar'i , wahyu adalah pemberitahuan Allah kepada orang yang dipilihnya
dari para hamba, segala apa yang Dia kehendaki untuk diketahui hamba
tersebut dari berbagai macam petunjuk dan ilmu, akan tetapi hal itu
terjadi dengan cara yang tersembunyi, yang tidak umum dikenal manusia.
Penyampaian
wahyu memiliki tiga metode; dalam bentuk ilham, mimpi atau dengan
diutusnya malaikat. Metode ketiga inilah yang digunakan dalam
penyampaian al-Quran. Untuk salah satu dari dua cara yang pertama,
malaikat turun kepada Nabi ﷺ sebagaimana yang dijelaskan hadits Aisyah radhiyallahu ‘anha ketika ia bertanya, “Wahai Rasulullah, bagaimana wahyu itu datang kepadamu?” Beliau menjawab,
أحيانًا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده عليّ فيفصم عني وقد وعيت ما قاله، وأحيانًا يتمثل لي الملك رجلاً فيكلمني فأعي ما يقول
“Terkadang wahyu itu datang kepadaku seperti gemerincing lonceng, dan itulah yang paling berat untukku. Tiba-tiba
hal itu lepas dariku dan aku telah memahami darinya apa yang Dia
ucapkan. Dan terkadang, Malaikat datang kepadaku dalam rupa seorang
manusia, dia berbicara padaku dan aku memahami apa yang dia sampaikan.” (HR. al-Bukhary)
27 Maret 2015
Hukum Pengkafiran & Terorisme
Majelis Hai-ah Kibâr al Ulamâ
dalam pertemuannya yang ke-49 di kota Tha’if, yang dimulai tanggal
2/4/1419 H, telah mempelajari apa yang terjadi di banyak negeri-negeri
Islam dan lainnya dari kasus-kasus pengkafiran dan teror bom, serta
akibat yang ditimbulkannya dengan tertumpahnya darah dan hancurnya
infrastruktur. Melihat akan pentingnya perkara ini dengan segala
konsekuensi lenyapnya nyawa-nyawa yang tidak berdosa dan jiwa-jiwa yang
terpelihara, ketakutan masyarakat dan goncangnya stabilitas keamanan;
maka Majelis memandang perlu untuk mengeluarkan pernyataan yang
menjelaskan hukum dari perkara tersebut, sebagai nasehat untuk Allah dan
untuk hamba-hambaNya; sebagai tanggung jawab moril dan juga untuk
menyingkirkan syubhat pemahaman pada sebagian orang yang terjerumus
dalam syubhat tersebut; kami katakan dengan taufîq Allah :
Pertama : takfîr
(pengkafiran) adalah hukum syar’i yang rujukannya adalah Allah dan
rasul-Nya. Sebagaimana penghalalan, pengharaman, dan perihal mewajibkan
adalah hak Allah dan rasul-Nya, maka demikian juga dengan takfir. Tidak
setiap apa yang disifatkan sebagai kekufuran –baik berupa perkataan atau
perbuatan– bisa menjadi kufur akbar yang mengeluarkan dari agama.
Ketika
rujukan hukum pengkafiran itu dikembalikan kepada Allah dan rasul-Nya,
maka tidak boleh kita mengkafirkan kecuali siapa yang ditunjukkan oleh
al-Kitab dan as-Sunnah akan kekafirannya dengan petunjuk yang jelas,
tidak cukup hanya dengan syubhat dan persangkaan belaka, karena
konsekuensinya membawa kepada hukum yang sangat berbahaya. Jika saja
hukuman had bisa dibatalkan dengan syubhat –walaupun sebenarnya
konsekuensinya lebih ringan daripada pengkafiran-, maka vonis
pengkafiran tersebut lebih layak untuk ditolak dengan syubhat-syubhat
tertentu. Karena itulah Nabi ﷺ telah memperingatkan tentang bahayanya
menuduh kafir terhadap seseorang yang sebenarnya tidak kafir. Beliau
bersabda,
أيما امرئٍ قال لأخيه : يا كافر فقد باء بها أحدهما، إن كان كما قال وإلا رجعت عليه
“Siapa
saja yang berkata kepada saudaranya : ‘kafir!’, maka perkataan itu akan
kembali kepada salah satu dari keduanya. Entah seperti yang ia tuduhkan;
jika tidak, tuduhan itu akan kembali kepadanya.”
Telah
disebutkan dalam al-Kitab dan as-Sunnah apa yang bisa dipahami bahwa
suatu perkataan, perbuatan atau keyakinan tertentu adalah kekufuran,
namun orang yang disifatkan dengannya tidak menjadi kafir, disebabkan
oleh sesuatu yang menghalanginya dari kekafiran tersebut.
Dan hukum
yang seperti ini –sebagaimana hukum-hukum yang lainnya-, tidak akan
terwujud kecuali dengan sebab-sebab dan syarat-syaratnya, serta tidak
adanya mawâni’ (penghalang-penghalang). Sebagaimana hukum
warisan, sebabnya adalah kekerabatan –sebagai contoh kasusnya-;
seseorang bisa jadi tidak mewarisi dengan kekerabatan tersebut
disebabkan oleh sebuah penghalang, seperti perbedaan agama. Demikian
juga kekufuran. Seorang mukmin dipaksa untuk kafir, dan dia tidak kafir
dengannya. Mungkin saja seorang mukmin mengucapkan satu kalimat
kekufuran dalam situasi yang sangat gembira atau sangat marah, namun dia
tidak serta merta menjadi kafir karena tidak adanya niat untuk hal itu.
Sebagaimana dalam kisah orang yang mengucapkan : ‘Ya Allah, Engkau adalah hambaku, dan aku adalah rabb-Mu’; dia telah berbuat kesalahan karena kegembiraan yang sangat besar.
Tergesa-gesa
dalam mengkafirkan, konsekuensinya adalah perkara-perkara yang sangat
berbahaya, seperti : dihalalkannya darah dan harta, hilangnya hak waris,
batalnya pernikahan, dan lain-lain yang konsekuensinya juga adalah
murtad. Maka bagaimana mungkin seorang mukmin melakukannya dengan hanya
sebuah syubhat yang kecil.
Jika
pengkafiran tersebut ditujukan terhadap para penguasa, maka perkaranya
lebih besar lagi. Karena hal itu akan membawa kepada pembangkangan dan
pemberontakan bersenjata terhadap mereka, terjadinya kekacauan,
tertumpahnya darah, serta kerusakan bagi rakyat dan negara. Karena
itulah Nabi ﷺ melarang memberontak terhadap para penguasa. Dan beliau
bersabda,
إلا أن تروا كفرًا بواحًا عندكم فيه من الله برهان
“Kecuali jika kalian melihat kekufuran yang sangat nyata, yang kalian memiliki bukti dari Allah.”
Sabda beliau :“Kecuali jika kalian melihat”, memberikan faedah bahwa perbuatan tersebut tidak cukup hanya dengan sekedar persangkaan dan isu belaka. Sabda beliau :“Kekufuran”,
yaitu tidak cukup hanya dengan kefasikan sebesar apapun kefasikan
tersebut, seperti kezaliman, meminum khamr, berjudi, dan suka
mementingkan diri sendiri yang diharamkan. Sabda beliau :“Yang sangat nyata”, yaitu tidak cukup sebuah kekufuran yang tidak nyata dan jelas. Sabda beliau:”Kalian memiliki bukti dari Allah”, yaitu mesti disertai dengan dalil yang jelas, yang dalil tersebut shahîh ats-tsubût (dipastikan keshahihannya) dan sharîh ad-dalâlah (jelas petunjuk dalilnya). Maka tidak cukup hanya dengan sebuah dalil yang lemah sanadnya dan tidak jelas petunjuk dalilnya (ghâmidh ad-dalâlah). Sabda beliau : “Dari Allah”,
yaitu tidak ada artinya perkataan seorang yang berilmu –sebesar apapun
kedudukannya dalam ilmu dan amanah– jika perkatannya tersebut tidak
dilandasi oleh dalil yang sharîh (jelas) dan shahîh dari Kitab Allah atau Sunnah rasul-Nya ﷺ. Kaedah-kaedah ini menunjukkan betapa berbahayanya perkara tersebut.
Kesimpulannya : terburu-buru dalam mengkafirkan sangat besar bahayanya. Allah Azza wa Jalla berfirman (yang artinya) : “Katakanlah
: Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak
ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia
tanpa alasan yang benar, (mengharamkan) mempersekutukan Allah dengan
sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujjah untuk itu dan (mengharamkan)
mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui”. (QS. Al-A’raf : 33)
Kedua :
akibat yang muncul dari keyakinan yang salah tersebut adalah
dihalalkannya darah dan kehormatan, perampokan asset-asset pribadi dan
umum, pengeboman gedung dan kendaraan, serta penghancuran infrastruktur.
Seluruh perbuatan ini dan yang semisalnya diharamkan syari’at dengan ijmâ’
(konsensus) kaum muslimin. Karena hal tersebut telah merusak kehormatan
jiwa-jiwa yang terpelihara, merusak kehormatan harta benda, merusak
stabilitas keamanan, ketenangan, dan kedamaian manusia dalam kehidupan
mereka, serta merusak fasilitas-fasilitas umum yang sangat dibutuhkan
oleh orang banyak.
Islam
telah memelihara untuk kaum muslimin harta-harta, darah-darah dan
tubuh-tubuh mereka; mengharamkan kezaliman terhadap hal-hal tersebut dan
sangat ketat dalam menjaganya. Itulah salah satu wasiat terakhir yang
disampaikan Nabi ﷺ untuk ummatnya. Beliau bersabda dalam khutbah Haji
Wada’,
إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرامٌ كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ثم قال : ألا هل بلغت؟ اللهم اشهد
“Sesungguhnya
darah-darah, harta-harta, dan kehormatan-kehormatan kalian adalah haram
atas diri-diri kalian sebagaimana haramnya hari kalian ini, dalam bulan
kalian ini, dan di negeri kalian ini”. Kemudian beliau bersabda :“Ketahuilah! Apakah aku telah sampaikan? Ya Allah, saksikanlah!” (Hadits Muttafaq ‘alaihi).
Beliau bersabda,
كل المسلم على المسلم حرامٌ دمه وماله وعرضه
“Setiap muslim atas muslim lainnya, diharamkan darah, harta dan kehormatannnya.”
Beliau juga bersabda,
اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة
“Jauhilah kezaliman! Karena kezaliman itu adalah kegelapan di hari kiamat kelak.”
Allah Ta’ala telah mengancam orang yang membunuh jiwa yang ma’shum dengan ancaman yang sangat keras. Allah berfirman tentang hak seorang mukmin (artinya) : “Dan
barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka
balasannya ialah Jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka
kepadanya, dan melaknatnya serta menyediakan azab yang besar baginya”. (QS. An-Nisa’ : 93).
Dan Allah berfirman tentang hak seorang kafir yang memiliki dzimmah (jaminan perlindungan) dalam kasus pembunuhan yang tidak disengaja (artinya) : “Dan
jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai)
antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar diyat
yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan
hamba sahaya yang mukmin.” (QS. An Nisa’ : 92).
Jika saja
seorang kafir yang memiliki jaminan keamanan terbunuh dengan tidak
sengaja memiliki diyat dan kaffarat (yang harus dibayarkan kepada
keluarganya), maka bagaimana jika dia dibunuh dengan sengaja. Sungguh
kejahatan dan dosanya sangatlah besar. Telah shahih dari Rasulullah ﷺ (sabdanya),
من قتل معاهدًا لم يرح رائحة الجنة
“Barangsiapa membunuh seorang mu’ahad, niscaya dia tidak akan mencium bau surga.”
Ketiga :
Majelis ini, ketika menjelaskan hukum mengkafirkan manusia tanpa bukti
dari Kitab Allah dan Sunnah rasul-Nya serta berbahayanya persoalan
tersebut dengan segala konsekuensi keburukan dan dosa; maka Majelis
mengumumkan kepada seluruh dunia bahwa Islam berlepas diri dari
keyakinan yang salah ini. Dan apa yang terjadi di sebagian negara dari
kasus-kasus tumpahnya darah orang-orang yang tidak berdosa, pengeboman
gedung-gedung, kendaraan, sarana-sarana umum dan pribadi, serta
perusakan infrastruktur adalah tindakan kejahatan dan Islam berlepas
diri darinya. Demikian juga setiap muslim yang beriman kepada Allah dan
rasul-Nya berlepas diri darinya. Tindakan ini hanyalah perbuatan orang
yang memiliki ideologi yang menyimpang dan aqidah yang sesat. Dialah
yang akan memikul dosa dan kejahatannya. Perbuatannya tersebut tidak
bisa dibebankan kepada Islam, dan tidak juga kepada kaum muslimin yang
mengambil petunjuk dengan petunjuk Islam, yang komitmen kepada al-Kitab
dan as-Sunnah, yang berpegang teguh kepada tali Allah yang kokoh.
Perbuatan ini hanyalah kerusakan dan kejahatan semata yang dibenci oleh
syari’at dan fitrah. Karena itulah nash-nash syari’at telah
mengharamkannya dan memperingatkan bahayanya bergaul dengan para
pelakunya.
Allah Ta’ala berfirman (artinya) : “Dan
di antara manusia ada orang yang ucapannya tentang kehidupan dunia
menarik hatimu, dan dipersaksikannya kepada Allah (atas kebenaran) isi
hatinya, padahal ia adalah penantang yang paling keras. Dan apabila ia
berpaling (dari kamu), ia berjalan di bumi untuk mengadakan kerusakan
padanya, dan merusak tanam-tanaman dan binatang ternak, dan Allah tidak
menyukai kebinasaan. Dan apabila dikatakan kepadanya :’Bertakwalah
kepada Allah’, bangkitlah kesombongannya yang menyebabkannya berbuat
dosa. Maka cukuplah (balasannya) neraka Jahannam. Dan sungguh neraka
Jahannam itu tempat tinggal yang seburuk-buruknya.” (QS. Al-Baqarah : 204-206).
Wajib bagi
seluruh kaum muslimin di mana pun mereka berada untuk saling berwasiat
diatas kebenaran, saling bernasehat dan tolong-menolong dalam kebajikan
dan ketakwaan, ber-amar ma’ruf nahi munkar dengan penuh hikmah dan
pengajaran yang baik, serta berdiskusi dengan cara yang baik.
Sebagaimana firman Allah subhânahu wa ta’âla (yang artinya) : “Dan
tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan
jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan
bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.” (QS. Al-Maidah : 2).
FirmanNya subhânahu (artinya), “Dan
orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka
(adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh
(mengerjakan) yang ma’ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat,
menunaikan zakat, dan mereka ta’at kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka
itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi
Maha Bijaksana.” (QS. At-Taubah : 71).
Dan firmanNya ’azza wa jalla (artinya), “Demi
masa. Sesungguuhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian.
Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan
nasehat-menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat-menasehati
supaya menetapi kesabaran.” (QS. Al-‘Ashr : 1-3).
Dan Nabi ﷺ bersabda,
الدين النصيحة، قيل : لمن يا رسول الله؟ قال : لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين
“Agama itu adalah nasehat.” Ditanyakan: “Untuk siapa wahai Rasulullah?” Beliau bersabda: “Untuk Allah, kitab-Nya, rasul-Nya, pemimpin-pemimpin kaum muslimin dan untuk seluruh kaum muslimin.”
Beliau juga bersabda,
مثل المؤمنين فى توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضوٌ تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى
“Perumpaman
orang-orang mukmin dalam cinta, kasih sayang dan kelembutan mereka
ibarat satu tubuh. Jika satu anggota tubuh merasa sakit, maka seluruh
tubuh akan ikut merasakan tidak bisa tidur dan demam.”
Dan ayat-ayat serta hadits-hadits yang semakna sangatlah banyak.
Akhirnya kami bermohon kepada Allah Ta’ala dengan nama-nama-Nya yang husnâ
dan sifat-sifat-Nya yang mulia agar Dia mencegah segala keburukan dari
kaum muslimin; menunjuki penguasa-penguasa kaum muslimin kepada apa yang
terbaik bagi para hamba dan seluruh negeri serta (membantu mereka)
memberantas kerusakan dan para perusak, menolong agama-Nya, meninggikan
kalimat-Nya, dan memperbaiki keadaan kaum muslimin di setiap tempat,
serta menolong kebenaran dengan perantaraan mereka. Sesungguhnya Dia-lah
yang berhak dan berkuasa atas hal tersebut. Dan shalawat dan salam atas nabi kita Muhammad beserta keluarga dan para shahabatnya.
Ketua Majelis : Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz
Anggota : Shalih
bin Muhammad al Luhaydan – Abdullah bin Sulaiman bin Mani’ – Muhammad
bin Shalih al Utsaimin – Abdul Aziz bin Abdullah bin Muhammad Alu Syaikh
– Dr. Abdullah bin Muhammad bin Ibrahim Alu Syaikh – Dr. Abdullah bin
Abdul Muhsin at Turky – Dr. Abdul Wahhab bin Ibrahim Abu Sulaiman –
Rasyid bin Shalih bin Khunain – Abdullah bin Abdurrahman al Ghudayyan –
Abdullah bin Shalih al Bassam – Nashir bin Hamad ar Rasyid – Muhammad
bin Sulaiman al Badr – Muhammad bin Zaid Alu Sulaiman – Dr. Shalih bin
Abdurrahman al Athram – Muhammad bin Ibrahim bin Jubair – Dr. Shalih bin
Fauzan al Fauzan – Hasan bin Ja’far al ‘Atamy – Muhammad bin Abdullah
as Subail – Abdurrahman bin Hamzah al Marzuqy – Dr. Bakr bin Abdullah
Abu Zaid.
——————
(Majalah al Buhûts al Islâmiyyah, no. 56, hal. 362-375)
21 Maret 2015
Tawassul yang Terlarang
Tawassul
adalah bagian dari doa. Dan doa adalah salah satu dari ibadah-ibadah
yang tidak dilakukan kecuali dengan petunjuk syari’at. Tidak dibenarkan
bagi seorang pun mengada-adakan satu jenis ibadah dalam agama Allah ini
tanpa petunjuk dalil yang shahih dan sharîh (jelas). Karenanya,
siapa yang melakukan tawassul dengan perkara yang tidak dituntunkan oleh
syari’at ini maka tawassul tersebut adalah termasuk jenis tawassul
bid’ah yang diharamkan.
Diantara bentuk-bentuk tawassul yang terlarang adalah :
1.
Bertawassul kepada Allah Ta’ala dengan perantaraan zat (diri) seorang
nabi, atau seorang shalih, atau Ka’bah dan lain-lain, seperti perkataan
seseorang : “Ya Allah, aku memohon kepadamu dengan perantaraan diri
bapak kami Adam ‘alaihissalam agar Engkau merahmati aku.”
2. Bertawassul dengan hak nabi, atau seorang shalih, atau Ka’bah dan lain-lain.
3.
Bertawassul dengan “kemuliaan” seorang nabi atau seorang shalih, atau
bertawassul dengan keberkahan dan kehormatannya, atau dengan hak
kuburnya dan yang semacamnya.
Seorang
muslim tidak dibenarkan berdoa kepada Allah dengan bentuk-bentuk
tawassul seperti ini karena perkara seperti ini tidak dinukil dengan
periwayatan yang shahih dari para Salaf. Andai perkara itu baik, niscaya
mereka telah mendahului kita dalam perkara tersebut.
Telah dinukil begitu banyak doa dari para Salaf, namun tidak ada satu pun bentuk-bentuk tawassul yang disebutkan.
Hal ini
bukan berarti bahwa kita meremehkan dan merendahkan kedudukan, kemuliaan
dan kehormatan salah seorang dari para nabi atau orang-orang shalih.
Mereka adalah orang-orang terbaik yang memiliki kemuliaan dan
kehormatan. Namun kemuliaan itu adalah milik mereka masing-masing,
khusus untuk pribadi-pribadi mereka. Mereka bisa memberi syafaat dengan
kemuliaan mereka semasa hidupnya di dunia dan di akhirat nanti bagi
siapa yang mereka kehendaki. Tapi tidak ada dalil yang membolehkan bagi
yang selain mereka untuk bertawassul kepada Allah dengan menyebut zat
(diri) mereka atau kemuliaan mereka.
Demikian
pula tidak dibenarkan seseorang bersumpah terhadap Allah dalam doanya
dengan menyebut nama salah seorang dari hambaNya. Karena pada asalnya
tidak dibolehkan bersumpah dengan selain nama Allah Ta’ala. Bagaimana
lagi dengan orang yang bersumpah terhadap Allah dengan nama selainNya?!
Begitu
juga tidak dibolehkan bermohon kepada Allah dengan hak seseorang. Karena
hak seperti itu hanya milik Allah, yang menjadi kewajiban para hamba
(yaitu dalam hakNya untuk diibadahi dan tidak dipersekutukan). Tidak ada
hak para hamba atas Allah Ta’ala yang menjadi kewajibanNya terhadap
mereka kecuali apa yang Dia wajibkan atas diriNya sendiri (yaitu untuk
menolong orang-orang mukmin, tidak menyiksa yang bertauhid diantara
mereka, mengabulkan permohonan mereka).
Kalangan
yang membolehkan bentuk-bentuk tawassul seperti ini tidak memiliki
dalil-dalil yang shahih. Mereka hanya berhujjah (berargumen) dengan
beberapa hadits atau atsar yang sangat lemah seperti hadits,
إذا سألتم الله فاسألوه بجاهي فإن جاهي عند الله عظيمٌ
“Jika kamu meminta kepada Allah, mintalah padaNya dengan kemuliaanku, karena sungguh kemuliaanku di sisi Allah sangatlah agung.”
Hadits tersebut adalah hadits maudhu’ (palsu), tidak bisa dijadikan hujjah dalam pensyari’atan suatu ibadah.
Mereka
juga berdalil dengan hadits Abu Sa’id yang padanya disebutkan tentang
tawassul kepada Allah dengan hak orang-orang yang meminta dan hak
berjalan ke masjid. Haditsnya juga dha’if. Andai haditsnya
dianggap sah, hak orang-orang yang meminta adalah pengabulan doa dari
Allah Ta’ala, dan hak berjalan ke masjid adalah pahala dari Allah.
Pengabulan doa dan memberi pahala adalah dua sifat dari sifat-sifat
Allah Ta’ala, sementara bertawassul kepada Allah dengan sifat-sifatNya
adalah termasuk tawassul yang disyari’atkan.
Mereka
juga berdalil dengan sebagian hadits-hadits shahih, namun tidak secara
jelas menyebutkan makna seperti yang mereka pahami. Diantaranya adalah
hadits tentang kisah bertawassulnya Umar bin al-Khattab dan para
shahabat dengan paman Nabi ﷺ, al-Abbas bin Abdil Muththalib, radhiyallahu ‘anhum.
Hadits
tersebut sebenarnya menggugurkan apa yang mereka yakini. Kalau saja
tawassul dengan diri Nabi ﷺ atau kemuliaannya dibolehkan, niscaya Umar
dan para shahabat tidak akan bertawassul dengan al-Abbas atau dengan
kedudukan dan kemuliaan al-Abbas karena kemuliaan Nabi ﷺ tentu jauh
lebih besar dan agung. Dan kemuliaan Nabi ﷺ tidak akan pernah berkurang
dengan kematiannya. Ketika Umar berpaling kepada al-Abbas, maka ini
menunjukkan bahwa bertawassul dengan orang yang lebih mulia dari
al-Abbas setelah kematiannya adalah hal yang tidak mungkin dilakukan;
tidak dengan doanya, dirinya, haknya atau kemuliaannya karena perbuatan
itu termasuk dalam keharaman.
Ketika
banyak dari umat ini meninggalkan tawassul yang disyari’atkan dan
berpaling kepada bentuk-bentuk tawassul yang tidak ada petunjuknya dari
Nabi ﷺ, maka Anda akan banyak mendapatkan sebagian mereka pergi ke kubur
dan bertawassul kepada Allah dengan perantaraan “kemuliaan” atau diri
sang penghuni kubur. Akibat buruknya dari perbuatan seperti ini justru
mengantarkan sebagian mereka kepada tawassul syirik, yang mungkin saja
akan membawa kepada sebagian bentuk-bentuk kekufuran. Sebagian mereka
akhirnya justru meminta langsung kepada orang-orang yang sudah wafat,
meminta diberikan kebaikan atau dihindarkan dari keburukan, dan meminta
agar orang-orang mati itu memberi mereka syafa’at di sisi Allah.
Karenanya,
sepantasnya seorang muslim menjauhi bentuk-bentuk tawassul yang tidak
disyari’atkan dalam dalil-dalil yang shahih. Minimal bentuk tawassul
seperti itu masuk ke dalam perkara-perkara syubhat. Dan siapa yang
menjauhi perkara syubhat, sungguh dia telah menjaga diri dan agamanya.
Wallahul musta’an.
(Sumber : Tahdzîb Tashîl al ‘Aqîdah al Islâmiyyah, Syaikh Dr. Abdullah bin Abdul Aziz al-Jibrin hafidzhahullahu)
14 Maret 2015
Hadits Shahîh li Ghairih & Hasan li Ghairih
Hadits shahîh li ghairih adalah hadits hasan li dzâtihi jika diriwayatkan dari jalan lain yang sepertinya atau lebih kuat darinya.
Disebut
“shahîh li ghairih” karena keshahihannya tidak datang dari sanad hadits
itu sendiri, tetapi dengan kumpulan/gabungan hadits lainnya dengannya.
Gambarannya sebagai berikut :
Hasan li dzâtihi + hasan li dzâtihi = shahîh li ghairihi
Derajatnya
Hadits shahîh li ghairih lebih tinggi levelnya daripada hasan li dzâtihi, dan dibawah level hadits shahîh li dzâtihi.
Contoh
Hadits Muhammad bin ‘Amr dari Abu Salamah dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda,
لو لا أن أشقّ على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاةٍ
“Kalau aku tidak memberatkan umatku, niscaya aku akan menyuruh mereka untuk bersiwak pada setiap shalat.”
Berkata Ibnu ash-Shalah : “Muhammad bin
‘Amr bin ‘Alqamah termasuk orang-orang yang dikenal dengan kejujuran dan
kebersihannya. Akan tetapi, ia bukan termasuk ahlul it’qân (yang pakar dalam keshahihan hadits) hingga sebagian ulama melemahkannya dari sisi buruknya hafalan. Sebagian menganggapnya tsiqah
(sangat terpercaya) karena kejujuran dan kemuliaannya. Haditsnya dari
sisi ini adalah hasan. Ketika hadits itu digabungkan dengan periwayatan
dari jalan lain, maka hilanglah apa yang tadinya kami khawatirkan
darinya dalam perkara buruknya hafalannya. Dengan itu, tertutuplah
kekurangan kecil tersebut, dan shahihlah sanad itu dan masuk dalam
derajat shahih.” (Ulûm al Hadîts, hal. 31-32)
Sementara hadits hasan li ghairih adalah hadits dha’îf
(lemah) jika berbilang jalan-jalan periwayatannya, dan sebab
kelemahannya itu bukan karena kefasikan perawinya atau kedustaannya.
Dengan definisi tersebut, hadits dha’if bisa naik kepada level “hasan li ghairih” dengan dua perkara, yaitu,
1.
Diriwayatkan dari satu jalan yang lain atau lebih, dengan syarat bahwa
jalan periwayatan lain itu sama sepertinya atau lebih kuat darinya.
2. Sebab kelemahan haditsnya adalah karena buruknya hafalan perawi, atau karena inqithâ’ (terputus) dalam sanadnya, atau jahâlah (ketidak-jelasan status) pada perawi-perawinya.
Hadits ini
disebut hasan li ghairih karena status “hasan”nya tidak datang dari
sanad hadits itu sendiri, akan tetapi dengan hadits lain yang
digabungkan kepadanya. Gambaran mudahnya adalah sebagai berikut :
Dha’if + dha’if = hasan li ghairih
Derajatnya
Hadits hasan li ghairih lebih rendah levelnya daripada hadits hasan li dzâtihi.
Dengan
landasan ini, jika terjadi kontradiksi antara hadits hasan li dzâtihi
dengan hadits hasan li ghairih, didahulukan hadits hasan li dzâtihi.
Hukumnya
Hadits hasan li ghairih termasuk hadits maqbûl yang diamalkan.
Contohnya
Diriwayatkan
oleh Imam at-Tirmidzi dan ia hasankan, dari jalan Syu’bah, dari ‘Ashim
bin Ubaidillah, dari Abdullah bin ‘Amir bin Rabi’ah, dari ayahnya,
أن امرأةً من بني فزارة تزوّجت على نعلين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرضيتِ من نفسك ومالك بنعلين؟ قالت: نعم، قال: فأجاز
bahwa seorang wanita dari Bani Fazarah menikah dengan mahar dua alas kaki. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda, “Apakah engkau rela terhadap diri dan hartamu dengan dua alas kaki?” Ia menjawab : “Iya.” Maka beliau pun membolehkannya.
Berkata
at-Tirmidzi : “Dalam bab ini (diriwayatkan juga) dari Umar, Abu
Hurairah, Sahl bin Sa’ad, Abu Sa’id, Anas, A’isyah, Jabir dan Abu Hadrad
al-Aslami.”
‘Ashim adalah seorang perawi yang dha’if karena buruknya hafalannya (sû-u al hifdzh). At-Tirmidzi menghasankan haditsnya karena telah diriwayatkan lebih dari satu jalan.
(Sumber : Taysîr Mushthalah al-Hadîts, Dr. Mahmud ath-Thahhan)
10 Maret 2015
Pernikahan Nabi ﷺ dengan Khadijah
Riwayat-riwayat lemah -bahkan sebagian besarnya sangat lemah- menyebutkan tentang detail kisah pernikahan Nabi ﷺ dengan Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu 'anha.
Riwayat-riwayat tersebut menyebutkan tentang awal mula perkenalan keduanya melalui pekerjaan Nabi ﷺ dalam kafilah dagang milik Khadijah yang merupakan seorang wanita kaya di Makkah.
Disebutkan bahwa pembantu Khadijah yang bernama Maisarah menceritakan tentang akhlak dan adab Nabi ﷺ selama dalam perjalanan dagang tersebut. Kisah itu membuat Khadijah kagum. Singkatnya, Nabi ﷺ akhirnya melamar Khadijah kepada ayahnya, Khuwailid bin Asad yang kemudian menikahkan keduanya.
Ibnu Ishaq berpendapat bahwa Khadijah saat itu berumur 28 tahun. Sementara riwayat al-Waqidi mengatakan bahwa ia berumur 40 tahun.
Dari pernikahan ini Khadijah telah melahirkan dua putra dan empat orang putri yang bisa menguatkan riwayat Ibnu Ishaq. Umumnya wanita telah memasuki masa menopause sebelum usia 50 tahun.
Walaupun kisah-kisah ini tidak sah dari sisi hadits, namun sangat masyhur di kalangan sejarawan.
Nabi ﷺ tinggal di rumah Khadijah, beliau menikah di rumah tersebut dan Khadijah melahirkan semua anak-anaknya dalam rumah itu. Di rumah itu pula Khadijah wafat. Nabi tetap tinggal di rumah Khadijah hingga masa hijrah yang kemudian diambil alih oleh Aqil bin Abi Thalib.
Tidak ada riwayat-riwayat shahih yang menjelaskan peristiwa-peristiwa ini.
Yang shahih dalam riwayat-riwayat hadits adalah pernikahan beliau dengan Khadijah, pujian Nabi ﷺ terhadapnya setelah kematiannya dan sikap Khadijah yang menenangkan Nabi setelah turunnya wahyu dan imannya kepada suaminya. Dua hal terakhir adalah peristiwa besar yang menunjukkan agungnya kedudukan Khadijah radhiyallahu 'anha dalam Islam.
Para ulama bersepakat bahwa Khadijah adalah istri pertama Nabi ﷺ.
Khadijah telah melahirkan dari Nabi ﷺ dua orang putra yaitu al-Qasim dan Abdullah (yang digelari ath-Thayyib dan ath-Thahir), serta empat orang putri yaitu Zainab, Ummu Kultsum, kemudian Fathimah kemudian Ruqayyah. Al-Qasim dan Abdullah meninggal sebelum Islam, sementara seluruh anak-anak putri menjumpai masa Islam dan semuanya memeluk Islam.
Khadijah radhiyallahu 'anha wafat tiga tahun sebelum hijrah Nabi ﷺ, sebelum terjadinya peristiwa Isra' dan Mi'raj.
(Dengan ringkas dari as Sirah an Nabawiyyah ash Shahihah)
06 Maret 2015
Haramnya Sutra bagi Kaum Laki-laki
Haram bagi seorang laki-laki muslim mengenakan sutra murni.
Diantara dalil-dalil pengharamannya adalah,
1. Hadits Anas, bahwa Nabi ﷺ bersabda,
لا تلبسوا الحرير فإنه من لبسه فى الدنيا لم يلبسه فى الآخرة
“Janganlah kalian mengenakan sutra, karena siapa yang mengenakannya di dunia, dia tidak akan mengenakannya di akhirat.” (HR. Al-Bukhary dan Muslim).
2. Dari Umar bin Al-Khattab bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,
إنما يلبس الحرير فى الدنيا من لا خلاق له فى الآخرة
“Yang mengenakan sutra di dunia hanyalah orang yang tidak memiliki bagian di akhirat.” (HR. Al-Bukhary dan Muslim).
3. Dari Abu Musa Al-Asy’ari bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,
حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لإناثهم
“Diharamkan pakaian sutra dan emas untuk laki-laki dari umatku dan dihalalkan bagi wanita mereka.” (HR. Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa’i dan Ibnu Majah)
Dibolehkan mengenakan pakaian yang terdapat sutra padanya namun tidak melebihi lebar empat jari.
Dalam
hadits Abu Utsman ia berkata : Umar bin Al-Khattab menulis surat kepada
kami ketika kami berada di Azerbaijan bahwa “Nabi ﷺ melarang mengenakan
sutra kecuali seperti ini, dan Nabi ﷺ membariskan dua jarinya.” (HR.
Al-Bukhary dan Muslim)
Dalam
riwayat Muslim disebutkan bahwa “Beliau melarang mengenakan sutra
kecuali sekedar tempat selebar dua, tiga atau empat jari.”
Dibolehkan Sutra dalam Kondisi Darurat
Jumhur
ulama memandang bolehnya memakai kain sutra untuk sebuah kondisi yang
dikategorikan darurat, seperti untuk pengobatan penyakit.
Anas bin Malik radhiyallahu ‘anhu
berkata, “Nabi ﷺ memberi keringanan untuk Az-Zubair dan Abdurrahman
mengenakan sutra karena penyakit gatal yang ada pada keduanya.” (HR.
Al-Bukhary dan Muslim).
Tidak Boleh Menjadikan Sutra sebagai Alas Tempat Duduk
Dengan dalil hadits Abu Hudzaifah radhiyallahu ‘anhu,
ia berkata, “Nabi ﷺ melarang kami minum di wadah emas dan perak, makan
padanya, mengenakan sutra dan duduk diatasnya.” (HR. Al-Bukhary).
Wallahu a’lam.
04 Maret 2015
Etika dalam Menelepon
Diantara
adab yang perlu diperhatikan dalam menelepon agar tidak terjatuh dalam
perkara-perkara yang dilarang oleh Syari’at Islam adalah sebagai berikut
:
1. Memilih
waktu yang cocok, karena setiap orang memiliki kesibukannya
masing-masing, dan setiap orang juga memiliki waktu tidur dan istirahat.
2. Tidak
memperpanjang pembicaraan tanpa ada hajat yang penting karena
dikhawatirkan orang yang dihubungi memiliki kesibukan atau telah
memiliki janji.
3. Seorang
wanita tidak boleh secara sengaja merendahkan atau membagus-baguskan
suaranya ketika berbicara dengan seorang laki-laki untuk sebuah
kepentingan atau memperpanjang pembicaraan dengannya. Allah Ta’ala
berfirman,
فَلاَ تَخْضَعْنَ بِالقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فىِ قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلاً مَعْرُوفًا
“Maka
janganlah kamu tunduk dalam berbicara sehingga berkeinginanlah orang
yang ada penyakit dalam hatinya, dan ucapkanlah perkataan yang baik.” (QS. Al-Ahzab ayat 32).
4. Yang
menelpon memulai pembicaraan dengan salam, karena dia yang “datang”
kepada orang yang diajak berbicara. Demikian pula, ia menutup
pembicaraan teleponnya dengan salam.
5. Tidak boleh menggunakan telepon orang lain kecuali setelah meminta izin, walaupun ada hajat untuk hal tersebut.
6. Tidak
boleh merekam pembicaraan orang lain tanpa izin atau tanpa
sepengetahuannya, apapun isi pembicaraannya, karena hal itu termasuk
dalam pengkhianatan dan membuka rahasia. Jika pembicaraan itu tersebar,
maka hal itu menambah dosa pengkhianatan dan merusak amanah. Masuk dalam
perkara ini, penyadapan terhadap pembicaraan manusia dan apa yang
terjadi diantara mereka. Yang seperti ini haram dan tidak boleh
dilakukan.
7. Tidak
boleh menggunakan telepon/handphone dalam hubungan haram antara dua
lawan jenis. Telepon adalah anugerah Allah yang Dia berikan untuk
keperluan kita, dan bukanlah termasuk dalam etika menjadikannya sebagai
sarana untuk mencari-cari aib kaum muslimin, merusak kehormatan mereka
dan menjerumuskan wanita-wanita mereka kepada kehinaan. Yang seperti ini
hukumnya haram dan pelakunya layak untuk mendapatkan sanksi.
(Sumber : Muntaqâ al Âdâb asy Syar’iyyah)
01 Maret 2015
Hukum Air Najis yang Telah Disterilkan
Keputusan Hai-ah Kibar Al ‘Ulama no. 64 pada tanggal 25 Syawwal 1398 H.
Setelah melalui pembahasan dan diskusi, Majelis menetapkan sebagai berikut :
Dengan
berlandaskan atas apa yang disebutkan oleh para ulama bahwa air banyak
yang telah bercampur najis dapat berubah menjadi suci jika hilang
perubahan tersebut dengan sendirinya, atau jika ditambahkan air suci
lainnya, atau hilang perubahannya tersebut dikarenakan air yang telah
lama mengendap atau pengaruh sinar matahari atau karena tiupan angin dan
yang semacamnya; karena (kaedah mengatakan) “hilangnya suatu hukum
dikarenakan hilangnya sebabnya”;
Dan
(dengan melihat) bahwa air najis mungkin dibersihkan dari najisnya
dengan beberapa metode, dan teknik penyulingan dan sterilisasi dari
najis yang mengenai air dengan metode penyulingan modern adalah sarana
terbaik dalam membersihkan air dengan menggunakan banyak sarana/sebab
untuk membersihkan air tersebut dari najis sebagaimana yang
dipersaksikan dan diakui oleh para ahli dalam masalah ini, yang tidak
diragukan tentang pekerjaan, keahlian dan pengalaman mereka; maka
Majelis memandang bahwa air tersebut adalah suci setelah disterilkan
dengan metode sterilisasi yang sempurna dimana air itu kembali kepada
bentuk aslinya, tidak nampak padanya perubahan yang disebabkan oleh
najis dalam rasa, warna dan bau. Air tersebut boleh digunakan untuk
menghilangkan hadats dan kotoran, dan kesucian (thaharah) bisa terwujud
dengannya. Demikian juga air itu boleh diminum kecuali jika terdapat
hal-hal yang bisa membahayakan kesehatan dalam penggunaannya, maka saat
itu air tersebut tidak boleh diminum untuk menjaga keselamatan jiwa,
semata-mata karena bahayanya (bagi kesehatan jika diminum) bukan karena
najisnya.
Majelis
menetapkan keputusan ini dengan tetap memandang baik jika tidak
menggunakan air tersebut untuk keperluan minum selama hal itu
memungkinkan, sebagai bentuk kehati-hatian untuk menjaga kesehatan,
melindungi dari bahaya dan menghindarkan sesuatu yang menjijikkan dalam
pandangan jiwa dan naluri manusia.
Wallahul muwaffiq.
(Sumber : Taudhîh Al Ahkâm min Bulûgh Al Marâm)