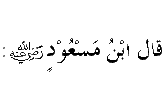28 Juni 2015
Islam Tidak Mengajarkan Kekerasan
Berkata Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin rahimahullahu dalam penjelasannya terhadap Ushul Tasir dalam firman Allah,
لأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ
“Supaya dengannya (Al-Quran) aku memberi peringatan kepadamu dan kepada orang-orang yang sampai Al-Quran (kepadanya).” (QS. Al-An’am ayat 19);
“Ketika muncul persoalan Ikhwan
(Al-Muslimin) yang bergerak (dalam pergerakan mereka) tanpa hikmah,
bertambah buruklah nama Islam dalam pandangan orang-orang Barat dan yang
selain mereka. Yang saya maksudkan adalah orang-orang yang menaruh
bahan peledak di tempat-tempat umum dengan dakwaan bahwa perbuatan itu
adalah termasuk jihad di jalan Allah.
Akan tetapi hakikatnya, mereka
sesungguhnya telah merusak nama Islam dan kaum muslimin lebih besar
daripada memperbaiki.
Apa yang mereka telah hasilkan?
Saya bertanya
kepada kalian, apakah orang-orang kafir akhirnya masuk ke dalam Islam?
Atau justru bertambah jauh darinya?… Mereka justru bertambah jauh
darinya!
Sementara para pemeluk Islam,
hampir-hampir seorang manusia akan menutup wajahnya agar tidak
dikait-kaitkan dengan kelompok yang membuat ketakutan dan teror tersebut.
Islam berlepas diri dari mereka… Islam berlepas diri dari mereka…
Bahkan setelah diwajibkannya jihad, para Shahabat radhiyallahu ‘anhum
tidak pernah pergi ke sebuah komunitas kafir untuk membunuhi mereka.
Tidak sama sekali!… Kecuali jihad yang memiliki bendera dari seorang
pemimpin yang memiliki kemampuan untuk berjihad…
Adapun bentuk terorisme seperti ini,
demi Allah, aib untuk kaum muslimin. Saya bersumpah atas nama Allah!
Kita tidak pernah mendapatkan hasilnya. Tidak ada hasilnya sama sekali!
Bahkan sebaliknya, hal itu semakin merusak citra (Islam).
Andai kita mau menempuh jalan hikmah,
bertakwa kepada Allah terhadap diri-diri kita, memperbaiki diri kita
terlebih dahulu, kemudian kita berusaha memperbaiki orang lain dengan
cara-cara yang syar’i, niscaya hasilnya adalah hasil yang baik.”
21 Juni 2015
Lansia & Orang Sakit yang Tidak Mampu Berpuasa
Ayat yang pertama turun berkenaan dengan puasa Ramadhan adalah firman Allah Ta’ala,
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ
“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu puasa.”; sampai pada firmanNya,
وَعَلَى
الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ
خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ
تَعْلَمُونَ
“Dan
wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak
berpuasa) membayar fidyah, (yaitu) memberi makan seorang miskin.
Barangsiapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah
yang lebih baik baginya. Dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu
mengetahui.” (QS. Al-Baqarah ayat 184).
Maka pada
permulaannya, kaum muslimin memiliki pilihan di bulan Ramadhan untuk
berpuasa atau berbuka (tidak berpuasa) dengan membayar fidyah, yaitu
memberi makan satu orang miskin untuk setiap satu hari yang ditinggalkan
puasanya.
Dari Salamah bin al-Akwa’ radhiyallahu ‘anhu ia berkata, “Ketika turun firman Allah, ‘Dan
wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak
berpuasa) membayar fidyah, (yaitu) memberi makan seorang miskin’, siapa yang ingin berbuka maka ia membayar fidyah. Hingga turunlah ayat yang setelahnya,
فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ
‘Barangsiapa diantara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu’; dan menghapus (nasakh) ayat tadi.” (HR. Al-Bukhary).
Hukum nasakh ayat tersebut berlaku untuk orang sehat yang sedang bermukim di negerinya.
Adapun orang tua yang telah lanjut usia dan tidak mampu lagi berpuasa, maka hukum nasakh
itu tidak berlaku atas mereka. Mereka tetap boleh berbuka tanpa harus
mengqadha’ puasanya di hari lain, dan wajib membayar fidyah. Inilah yang
diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu ‘anhuma, “Diberikan
keringanan bagi orang tua yang telah lanjut usia untuk tetap berbuka dan
memberi makan satu orang miskin untuk setiap satu hari (yang
ditinggalkan puasanya), dan tidak ada kewajiban mengganti (qadha’) puasa atasnya.” (HR. Ad-Daruquthni dan al-Hakim).
Riwayat
ini diperkuat dengan riwayat lain oleh Imam Ahmad (21107), Abu Dawud
(507) dan lain-lain dari Mu’adz bin Jabal ia berkata, “Allah telah
menetapkan kewajiban puasa Ramadhan atas orang sehat yang bermukim, dan
memberikan keringanan bagi orang sakit dan musafir. Dan telah tetap
hukum memberi makan bagi orang lanjut usia yang tidak mampu berpuasa.”
Termasuk
dalam kategori orang tua yang telah lanjut usia yang tidak mampu
berpuasa adalah orang sakit yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya dan
ia tidak mungkin berpuasa. Orang seperti ini boleh berbuka dan membayar
fidyah.
Takaran makanan yang dibayarkan dalam fidyah adalah sebesar ½ shâ’ dari makanan pokok masing-masing negeri.
1 shâ’ nabawi setara dengan 4 mudd.
I mudd kurang lebih setara dengan 625 gram. Karenanya, I shâ’ nabawi kurang lebih setara dengan ukuran 2500 gram (2,5 kg).[1]
Untuk kehati-hatian, sebagian fatwa dari para ulama menggenapkan jumlah 1 shâ’ kurang lebih setara dengan 3000 gram (3 kg). [2]
Kesimpulannya, fidyah yang wajib dibayarkan dalam bentuk bahan mentah adalah beras seberat ½ shâ’ atau setara dengan 1 ½ kg.
Sangat baik kalau fidyah beras tersebut disertakan dengan lauk-pauk.
Adapun
jika dibayarkan dalam bentuk makanan siap santap, maka boleh dengan
mengundang orang miskin sejumlah hari yang ditinggalkan puasanya,
kemudian menjamu mereka dalam sebuah jamuan makan siang atau malam.
Atau makanan tersebut diantarkan kepada orang-orang miskin untuk disantap di tempat mereka masing-masing.
Sementara
memberi makan satu orang miskin untuk tiga puluh hari, kebanyakan ulama
memperbolehkannya, dan ini adalah madzhab Syafi’iyah, Hanabilah dan
sebagian dari Malikiyah. Dalam al-Inshâf (III/291) disebutkan: “Diperbolehkan memberikan (makanan) kepada satu orang miskin sekaligus.” [3]
Hukum fidyah ini berlaku juga untuk wanita hamil dan wanita menyusui yang tidak mampu berpuasa di bulan Ramadhan. (silahkan baca artikelnya di : Wanita hamil & menyusui yang tidak berpuasa di bulan Ramadhan)
Wallahu a’lam
Wallahu a’lam
————————
[1] Mudd
adalah takaran penuh dua telapak tangan normal orang dewasa. Adapun dengan
timbangan, ukurannya akan berbeda-beda sesuai dengan perbedaan jenis
makanan yang ditakar. Karenanya, berbeda pula hitungan shâ’ dalam timbangan
kilogram yang disebutkan oleh para ulama karena perbedaan ukuran mudd. Yang kami sebutkan adalah
ukuran yang disebutkan Syaikh Abdullah al-Bassam dalam Syarh Bulugh
al-Maram. Ulama lain menyebutkan bahwa 1 shâ’ sama dengan 2040 gram,
atau 2176 gram, atau 2751 gram. (lihat jawaban fatwa dalam Islamweb)
[2] Majmû’ Fatâwâ wa Maqâlât Mutanawwi’ah oleh Syaikh Bin Baz, XIV/200, Fatwa al-Lajnah ad-Dâimah Kerajaan Saudi, IX/371, fatwa no. 12572 dan pendapat yang dipilih oleh Markaz Fatwa Islamweb-Qatar
[3] Dikutip dari Tanya-Jawab tentang Islam
19 Juni 2015
Sunnah dan Adab Berbuka Puasa
Jika matahari telah dipastikan terbenam, disunnahkan bagi orang yang berpuasa untuk segera berbuka dan membatalkan puasanya.
Dalam hadits Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu ‘anhu, Rasulullah ﷺ bersabda,
إذا رأيتم الليل قد أقبل من هاهنا فقد أفطر الصائم
“Jika kalian melihat malam telah datang dari arah ini, maka (tiba saatnya) orang berpuasa berbuka.” (HR. Al-Bukhary dan Muslim).
Dari Sahl bin Sa’ad radhiyallahu ‘anhu bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,
لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر
“Senantiasa manusia dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka.” (HR. Al-Bukhary dan Muslim).
Kebaikan yang dimaksud dalam hadits tersebut adalah ittibâ’ (mengikuti) sunnah Nabi ﷺ yang merupakan sebab kebaikan dunia dan akhirat.
Diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu dari Nabi ﷺ beliau bersabda,
لا يزال الدين ظاهرًا ما عجل الناس الفطر، لأن اليهود والنصارى يؤخرون الإفطار إلى اشتباك النجوم
“Agama
ini akan senantiasa tegak jika manusia menyegerakan berbuka. Karena
orang-orang Yahudi dan Nasrani menunda waktu berbuka hingga bermunculan
bintang-bintang.” (HR. Abu Dawud, Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban, dishahihkan al-Albani).
Disunnahkan saat berbuka untuk berbuka dengan kurma.
Dari Anas radhiyallahu ‘anhu ia berkata,
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم تكن رطبات فعلى تمرات، فإن لم تكن حسا حسوات من الماء
“Rasulullah ﷺ berbuka dengan beberapa ruthab sebelum shalat, jika tidak ada ruthab, beliau berbuka dengan beberapa tamr, jika tidak ada, beliau berbuka dengan air.” (HR. Abu Dawud dan at-Tirmidzi, hadits hasan).
Ruthab, yaitu kurma yang masih basah, tamr adalah kurma yang telah mengering.
Dan Rasulullah ﷺ jika telah berbuka beliau akan membaca,
ذهب الظمأ و ابتلت العروق و ثبت الأجر إن شاء الله
Dzahaba_dzh-dzhoma-u wa_btallati_l-‘urûq wa tsabata_l-ajru in syâ-a_Llâhu
“Telah hilang dahaga, telah basah tenggorokan, dan telah tetap pahala insyaallah.” (HR. Abu Dawud, an-Nasa’i dalam al-Kubrâ dan Ibnu as-Sunni, dishahihkan oleh al-Albani).
Para ulama
bersepakat bahwa puasa berakhir dan sempurna dengan tenggelamnya
matahari dan sunnah bagi orang yang berpuasa untuk segera berbuka jika
telah dipastikan tenggelamnya matahari dengan penglihatan langsung atau
berita yang disampaikan seorang yang tsiqah (terpercaya).
Mereka juga bersepakat bahwa orang yang berpuasa boleh berbuka dengan ghalabah adzh-dzhann (persangkaan yang dominan). Karena dzhann tersebut menggantikan kedudukan al-yaqîn (keyakinan yang mutlak).
Berkata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah rahimahullahu,
“Dengan adanya mendung yang menutupi, tidak mungkin terwujud sebuah
keyakinan kecuali jika telah berlalu waktu yang panjang dari malam
hingga luputlah keutamaan menyegerakan berbuka. Karenanya tidak
dianjurkan segera berbuka dengan adanya mendung hingga diyakini
tenggelamnya matahari. Dimakruhkan berbuka dengan landasan keraguan
tentang terbenamnya matahari, dan tidak dimakruhkan sahur dengan adanya
keraguan telah terbitnya fakar kecuali dalam persoalan jima’
(bersetubuh).”
Perkataan beliau berlandaskan sebuah kaedah syar’i bahwa,
الأصل بقاء ما كان على ما كان
“Hukum asalnya adalah tetapnya sesuatu sebagaimana keadaannya”.
Maka dalam
sahur, hukum asalnya tetapnya malam hingga diyakini terbitnya fajar,
sementara dalam berbuka hukum asalnya adalah tetapnya siang hingga
diyakini tenggelamnya matahari.
Wallahu a’lam.
———————
Sumber bacaan :
[1] Taudhîh al Ahkâm min Bulûgh al Marâm
[2] Shahîh Fiqh as Sunnah
[2] Shahîh Fiqh as Sunnah
18 Juni 2015
Hukum Puasa bagi Seorang Musafir
Pertanyaan,
“Manakah yang lebih utama bagi musafir, berbuka atau puasa? Khususnya
safar yang tidak ada keberatan adanya seperti safar dengan pesawat atau
alat-alat transportasi modern lainnya.”
Dijawab oleh Syaikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullâhu :
Yang
paling utama bagi orang yang berpuasa adalah berbuka dalam safar secara
mutlak. Dan siapa yang berpuasa, tidak ada dosa atasnya. Karena telah
sah riwayat dari Nabi ﷺ dalam perkara yang ini dan itu. Demikian pula
(perbuatan) para sahabat radhiyallahu ‘anhum.
Akan
tetapi, jika cuaca sangat panas dan beban semakin berat, berbuka lebih
ditekankan dan dibenci berpuasa bagi musafir. Karena Nabi ﷺ saat melihat
seorang laki-laki telah dipayungi dalam sebuah safar karena cuaca yang
sangat panas sementara dia dalam keadaan berpuasa, beliau ﷺ bersabda,
ليس من البرّ الصوم فى السفر
“Bukanlah termasuk kebajikan berpuasa dalam safar.” (HR. Al-Bukhary dan Muslim).
Dan juga dengan apa yang telah sah dari beliau ﷺ dalam sabdanya,
إن الله يحب أن تُؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته
“Sesungguhnya
Allah suka jika dikerjakan keringanan-keringanan (yang diberikan)-Nya,
sebagaimana Dia benci dikerjakan maksiat (terhadap)-Nya.”
Dalam redaksi lain,
كما يحب أن تؤتى عزائمه
“Sebagaimana Dia suka dikerjakan perintah-perintah-Nya.” (HR. Ahmad dan ath-Thabrani, dishahihkan oleh al-Albani).
Tidak ada
perbedaan dalam masalah ini antara orang yang mengadakan perjalanan
dengan menggunakan mobil, onta, dan kapal laut atau orang yang
mengadakan perjalanan dengan menggunakan pesawat. Karena istilah “safar”
telah mencakupi mereka semuanya, dan mereka boleh mengambil
keringanan-keringanannya.
Allah subhânahu
telah menetapkan bagi para hamba hukum-hukum safar dan mukim di masa
Nabi ﷺ dan (berlaku) bagi orang yang datang sesudahnya sampai hari
Kiamat. Dia subhânahu mengetahui apa yang bakal terjadi dari
perubahan keadaan dan berbagai macam bentuk sarana transportasi. Kalau
seandainya hukum tersebut berbeda, niscaya Dia akan menyebutkan tentang
hal itu sebagaimana Dia ‘azza wa jalla berfirman dalam surat an-Nahl,
وَنَزَّلنَا عَلَيكَ الكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْئٍ وَهُدىً وَرَحْمَةً وَبُشْرىَ لِلمُسلِمِينَ
“Dan
Kami turunkan kepadamu al-Kitab untuk menjelaskan segala sesuatu dan
petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah
diri.” (QS. 16 : 89).
Dan Dia subhânahu juga berfirman dalam surat an-Nahl,
وَالخَيلَ وَالبِغَالَ وَالحَمِيْرَ لِتَركَبُوهَا وَزِيْنَةً وَيَخْلُقُ مَالا تَعْلَمُونَ
“Dan (Dia
telah menciptakan) kuda, bighal dan keledai, agar kamu menungganginya
dan (menjadikannya) perhiasan. Dan Allah menciptakan apa yang kamu tidak
mengetahuinya.” (QS. 16 : 8)
—————
Sumber : As-ilah Muhimmah Tata’allaq bi ash Shiyâm, hal. 12-14
17 Juni 2015
Hukum-hukum yang Berkait dengan Sahur
Makan sahur adalah sunnah yang sangat ditekankan dalam Islam, walaupun seseorang puasanya dianggap sah tanpa sahur.
Dalam hadits-hadits shahih, Rasulullah ﷺ menganjurkan makan sahur dan memberikan teladan yang dalam amalan tersebut.
Dari Anas bin Malik radhiyallahu ‘anhu bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,
تسحروا فإن فى السحور بركة
“Bersahurlah kalian, karena dalam sahur ada keberkahan.” (HR. Al-Bukhary dan Muslim).
Rasulullah ﷺ juga bersabda,
فصل ما بين صيامنا و صيام أهل الكتاب أكلة السحور
“Pembeda antara puasa kita dan puasa Ahli Kitab adalah makan sahur.” (HR. Muslim).
Bahkan saking pentingnya persoalan sahur tersebut, beliau memerintahkan sahur walaupun hanya dengan seteguk air.
Dari Abdullah bin ‘Amr radhiyallahu ‘anhuma bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,
تسحروا ولو بجرعة ماء
“Bersahurlah kalian walaupun hanya dengan seteguk air.” (Hadits hasan riwayat Imam Ibnu Hibban).
Dan termasuk dalam sunnah sahur adalah mengakhirkan waktu sahur.
Dalam hadits Anas dari Zaid bin Tsabit radhiyallahu ‘anhu ia berkata,
تسحرنا مع النبي صلى الله عليه و سلم ثم قام إلى الصلاة، قلت : كم بين الأذان و السحور؟ قال : قدر خمسين آية
“Kami
bersahur bersama Rasulullah ﷺ kemudian beliau pergi menunaikan shalat.”
Aku bertanya: “Berapa jarak antara adzan dan (permulaan) sahur
tersebut?” Ia menjawab: “Kurang lebih (bacaan) 50 ayat.” (HR. Al-Bukhary
dan Muslim).
Dari Unaisah bintu Habib radhiyallahu ‘anha ia berkata : Bersabda Rasulullah ﷺ,
إذا أذن ابن أم مكتومٍ فكلوا واشربوا، وإذا أذن بلال فلا تأكلوا ولا تشربوا
“Jika
Ibnu Ummi Maktum mengumandangkan adzan, makan dan minumlah kalian. Dan
jika Bila mengumandangkan adzan, berhentilah makan dan minum.”
(Berkata
Unaisah) : Jika salah seorang dari kami masih tersisa sesuatu dari
sahurnya, ia akan berkata kepada Bilal, “Tangguhkan (adzan) hingga aku
selesai dari sahurku.” (HR. an-Nasa’i, Ahmad dan Ibnu Hibban dengan
sanad yang shahih).
Hadits ini
memberi pelajaran kepada kita bahwa imsak untuk memulai puasa dimulai
dengan masuknya waktu subuh, tidak diundurkan beberapa saat sebelumnya.
Bahkan jika seseorang mendengarkan adzan sementara makanan dan
minumannya ada di tangannya, maka ia boleh menyelesaikannya. Riwayat
tersebut diperkuat dengan hadits Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu ia berkata : Bersabda Rasulullah ﷺ,
إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه
“Jika
salah seorang kalian mendengarkan adzan sementara makanan ada di
tangannya, janganlah ia meletakkannya hingga ia menyelesaikan hajatnya.” (HR. Abu Dawud).
Sahur adalah istilah yang menunjukkan kepada waktu tertentu, yaitu waktu menjelang terbitnya fajar atau menjelang subuh. Sayangnya sebagian orang justru makan sahur beberapa jam sebelum masuknya waktu hingga akhirnya terjatuh pada kesalahan. Ia telah berpuasa sebelum masuk waktu syar’inya dan tidak mendapatkan keberkahan makan sahur yang dijanjikan.
Orang yang
akan berpuasa diharuskan telah berniat puasa di malam hari sebelum
terbitnya fajar. Jika dia telah berniat dan tidak terbangun saat sahur,
maka dia wajib menahan diri dari makan dan minum, dan puasanya tetap
sah.
Demikian sebagian pembahasan yang berkait dengan adab-adab puasa dalam persoalan sahur. Selayaknya seorang muslim mempelajari sunnah Rasulullah ﷺ dalam sahurnya dan dalam semua amalan-amalan ibadahnya, agar ia bisa mengamalkannya sesuai dengan petunjuk syari'at dan diterima di sisi Allah Ta'ala.
Wanita Hamil & Menyusui yang Tidak Berpuasa di Bulan Ramadhan
Pada asalnya, seorang wanita hamil dan wanita yang sedang menyusui bayinya tetap wajib berpuasa di bulan Ramadhan.
Jika
wanita hamil tersebut khawatir terhadap janinnya, dan wanita yang sedang
menyusui khawatir akan bayi susuannya yang jika berpuasa air susunya
akan berkurang dan sebagainya disebabkan oleh puasa –dengan
pengalamannya atau rekomendasi seorang dokter yang terpercaya-, maka
tidak ada perselisihan diantara ulama tentang bolehnya bagi kedua wanita
tersebut untuk berbuka.
Saat kedua wanita tersebut berbuka di bulan Ramadhan dengan alasan syar’i, apa yang wajib atas keduanya?
Para ulama berselisih tentang kewajiban yang mesti dilakukan keduanya karena meninggalkan puasa Ramadhan.
Diriwayatkan dengan sanad yang shahih dari Ibnu Abbas dan Ibnu Umar radhiyallahu ‘anhum
bahwa keduanya menyuruh wanita hamil dan wanita menyusui yang berbuka
puasa di bulan Ramadhan untuk membayar fidyah tanpa harus mengqadha’
puasa yang ditinggalkan. Pendapat ini juga adalah pendapat Sa’id bin
Jubair.
Ibnu Abbas memasukkan kedua jenis wanita tersebut ke dalam apa yang Allah maksudkan pada firmanNya,
وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ
“Dan
wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak
berpuasa) membayar fidyah (yaitu) memberi makan seorang miskin.” (QS. Al-Baqarah ayat 184)
Sisi
pendalilannya memasukkan kedua wanita tersebut dalam golongan orang
sakit yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya lagi adalah karena akan
selalu berulangnya kehamilan dan penyusuan pada umumnya kaum wanita.
Ibnu Abbas berkata, “Ayat ini adalah keringanan (rukhshah)
bagi laki-laki yang telah lanjut usia dan perempuan yang telah lanjut
usia, sementara mereka tidak mampu berpuasa, maka keduanya berbuka dan
memberi makan satu orang miskin untuk setiap satu hari yang
ditinggalkan. Demikian pula wanita hamil dan wanita menyusui jika
khawatir terhadap anaknya, keduanya berbuka dan memberi makan.” (Riwayat
Abu Dawud)
Pendapat ini diriwayatkan juga dari Ibnu Umar dan tidak ada yang menyelisihinya dari para Shahabat.
Jumhur ulama, termasuk para imam yang empat berpendapat wajibnya qadha’ atas kedua wanita tersebut dengan dalil firman Allah Ta’ala,
فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ
“Maka
barangsiapa diantara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia
berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang
ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain.” (QS. Al-Baqarah ayat 184)
Mereka
berkata : Wanita tersebut lebih mirip dengan orang sakit yang masih bisa
diharapkan kesembuhannya, maka ia wajib mengqadha’ jika ia mampu
melakukannya.
Imam
asy-Syafi’i dan Imam Ahmad menambahkan kewajiban mengqadha’ tersebut
dengan kewajiban memberi makan satu orang miskin (kaffarah/fidyah) untuk
setiap satu hari yang ditinggalkan jika berbukanya itu karena kekhawatiran terhadap keselamatan janin atau anak yang disusui.
Adapun
atsar dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas, jumhur memandang bahwa hal itu
adalah tambahan dari kewajiban wanita itu untuk mengqadha’ puasa yang
ditinggalkan.
Sementara
al-Laits dan satu riwayat dari Imam Malik berpendapat bahwa kaffarah
(fidyah) hanya berlaku untuk wanita menyusui, bukan untuk wanita hamil,
karena wanita menyusui memungkinkan baginya untuk menyusukan anaknya
pada wanita lain, tidak seperti wanita hamil. Dikarenakan juga karena
kehamilan berkait langsung dengan wanita hamil, sehingga kekhawatiran
terhadap janin yang ada dalam perutnya sama seperti kekhawatiran
terhadap anggota tubuhnya sendiri yang sakit, sehingga dia dihukumi
seperti orang sakit yang wajib mengqadha’ puasanya di hari yang lain.
Sementara
Atha’ bin Abi Rabah, az-Zuhri, al-Hasan, Sa’id bin al-Musayyib,
an-Nakha’i, al-Auza’i dan Abu Hanifah memandang tidak ada kewajiban
kaffarah atas keduanya, dan hanya wajib mengqadha’ saja.
Mereka berdalil dengan sabda Nabi ﷺ,
إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة وعن الحامل والمرضع الصوم
“Sesungguhnya Allah telah memberi keringanan separuh shalat bagi musafir dan (keringanan) puasa bagi wanita hamil dan menyusui.” (HR. At-Tirmidzi dan an-Nasa’i).
Mereka
berkata : Beliau tidak menyuruh untuk membayar
kaffarah (fidyah), dan juga dikarenakan hal itu adalah berbuka yang
diizinkan karena uzur, maka tidak wajib atasnya kaffarah sebagaimana
berbukanya orang sakit.
Dari
sekian pendapat ulama ini, pendapat pertama lebih dekat kepada atsar
karena diriwayatkan dari pendapat dua orang shahabat yang mulia,
kemudian pendapat terkuat setelahnya adalah pendapat Imam Abu Hanifah
yang hanya mewajibkan qadha’, dan itulah pendapat yang difatwakan oleh al-Lajnah ad-Da’imah
yang diketuai oleh Syaikh Abdul Aziz bin Baz pada saat itu, dan juga
fatwa yang dipilih oleh Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin. Wallahu a’lam.
Untuk lebih rinci tentang pendapat para ulama silahkan dibaca artikel : Apa yang wajib bagi wanita hamil dan menyusui ketika berbuka di bulan Ramadhan?
Inilah pendapat yang kami pilih dan cenderung padanya. Kami sangat menghargai pendapat yang berbeda dalam persoalan ini.
Tapi yang
perlu diketahui, bahwa seorang muslim harus memilih salah satu dari
pendapat-pendapat tersebut dengan dalilnya dan mengamalkannya tanpa ada
keraguan atau kebimbangan. Jangan sampai ada seseorang yang sesuka
hatinya memilih dan mengamalkan pendapat yang berbeda-beda setiap tahunnya sesuai dengan
hawa nafsu dan kepentingan dirinya tanpa meyakini kebenaran salah satu
dari pendapat tersebut untuk diamalkan.
(Ust. Taufiq Rahman)
————————
Bahan rujukan :
[1] Al-Majmû’, an-Nawawi (VI/178)
[2] Shahîh Fiqh as-Sunnah, Abu Malik (II/125-127)
[3] Fatâwâ fî Ahkâm ash-Shiyâm, al-Utsaimin (hal. 159-164)
[4] Fatwa-fatwa al-Lajnah ad-Dâ’imah, Kerajaan Saudi (X/220, fatwa no. 1453)
[5] Fatwa-fatwa situs islamweb.net
14 Juni 2015
Mengamalkan Ru’yah dalam Penetapan Hilal Ramadhan
Majelis
al-Majma’ al-Fiqhi al-Islami* dalam simposiumnya yang ke IV bertempat di
Kantor Pusat Rabithah al-Alam al-Islami di Makkah al-Mukarramah pada
7-17 Rabi’ul Akhir 1401 H telah menelaah surat Lembaga Dakwah Islam di
Singapura yang bertanggal 16 Syawwal 1399 bertepatan dengan 8 Agustus
1979 yang ditujukan kepada Pelaksana tugas Kedutaan Besar Kerajaan Saudi
Arabia di sana yang isinya menyebutkan tentang perselisihan antara
Lembaga tersebut dengan Majelis Islam Singapura tentang penentuan
permulaan dan akhir Ramadhan pada tahun 1399 H bertepatan dengan tahun
1979 M, dimana Lembaga memandang bahwa permulaan dan akhir Ramadhan
ditetapkan berdasarkan ru’yah syar’i yang selaras dengan keumuman
dalil-dalil syar’i, sementara Majelis Islam Singapura memandang bahwa
hal itu ditetapkan dengan perhitungan hisab astronomi. Mereka beralasan
dengan perkataannya : “berkait dengan negara-negara di wilayah Asia,
dimana langitnya selalu tertutup awan –dan secara khusus Singapura-,
maka tempat-tempat untuk melihat hilal sebagian besarnya akan terhalang
dari ru’yah tersebut. Yang seperti ini tergolong sebagai uzur yang mesti
terjadi, dan karenanya wajib untuk memperkirakannya dengan jalan
hisab”.
Setelah
para anggota Majelis al-Fiqhi al-Islami mempelajari persoalan ini diatas
landasan dalil-dalil syar’i, maka Majelis al-Majma’ al-Fiqhi al-Islami
mendukung pendapat Lembaga Dakwah Islam karena jelasnya dalil-dalil
syar’i dalam pendapat tersebut.
Majelis
juga menetapkan bahwa untuk kondisi yang ada di tempat-tempat seperti
Singapura dan sebagian wilayah Asia dan yang lainnya, dimana langitnya
tertutup mendung yang menghalangi dari ru’yah, maka kaum muslimin di
daerah-daerah tersebut dan yang semacamnya hendaknya mengambil perkataan
orang yang mereka percayai dari negeri-negeri Islam yang bertumpu pada
ru’yah hilal dengan pandangan mata dan tidak menggunakan hisab dalam
bentuk apapun, demi untuk mengamalkan sabdanya ﷺ,
صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين
“Berpuasalah
dengan melihatnya (hilal) dan berbukalah (menyelesaikan Ramadhan)
dengan melihatnya. Jika (penglihatan) kalian tertutupi oleh awan,
sempurnakanlah hitungan menjadi tigapuluh.”
Dan sabdanya ﷺ,
لا تصوموا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة، ولا تفطروا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة
“Jangan
berpuasa hingga kalian melihat hilal atau kalian menyempurnakan
hitungan (Sya’ban menjadi tigapuluh). Dan janganlah kalian berbuka
(menyelesaikan puasa Ramadhan) hingga kalian melihat hilal atau kalian
menyempurnakan hitungan (Ramadhan menjadi tigapuluh).”;
Dan hadits-hadits lain yang semakna dengan keduanya.
(Sumber : Taudhîh al-Ahkâm min Bulûgh al-Marâm, II/650-651)
————————
*
Al-Majma’ al-Fiqhi al-Islami adalah sebuah lembaga fiqh Islam internasional di
bawah naungan Rabithah al-‘Alam al-Islami (Liga Muslim se-Dunia) yang
berkantor pusat di Kota Makkah, Saudi Arabia
07 Juni 2015
Adab Buang Hajat dalam Islam
Agama kita
adalah agama yang sempurna. Tidaklah dia meninggalkan sesuatu yang
dibutuhkan manusia dalam urusan agama atau dunianya melainkan telah
dijelaskan. Diantaranya adalah adab-adab dalam buang hajat, yang
dengannya Allah memuliakan manusia dari hewan.
Diantara adab-adab buang hajat adalah sebagai berikut :
- Jika seorang muslim akan memasuki kamar kecil maka disunnahkan baginya untuk mengucapkan :
بسم الله، أعوذ بالله من الخبث والخبائث
Bismi_Llâh, a’ûdzu bi_Llâhi min_alkhubutsi wa_lkhabâ-its
(Dengan menyebut nama Allah, aku berlindung kepada Allah dari setan laki-laki maupun setan perempuan).
Saat masuk, dia mendahulukan kaki kiri, dan saat keluar mendahulukan kaki kanan sambil mengucapkan :
غفرانك
Ghufrânaka
(Aku memohon ampunan-Mu ya Allah).
Jika
seorang muslim buang hajat di tempat terbuka (bukan di tempat yang
disediakan khusus untuk kamar kecil), maka dia harus menjauhi
orang-orang untuk berada di tempat yang sepi dan menutup dirinya dari
pandangan manusia baik dengan tembok, pohon dan lain-lain. Tidak
dibolehkan baginya menghadap kiblat atau membelakanginya karena Nabi ﷺ melarang hal tersebut[1].
Wajib juga baginya menjaga diri, badan dan pakaiannya dari percikan air
kencing agar dipastikan bahwa muslim tersebut melaksanakan shalat dalam
keadaan suci dan bebas dari najis. Tidak menjaga diri dari dari najis
air kencing ini merupakan salah satu dari sebab-sebab terjadinya azab
kubur.[2]
Tidak
dibolehkan juga menyentuh kemaluannya dengan tangan kanannya, dan juga
tidak boleh buang air di jalan-jalan manusia, tempat bernaung mereka dan
tempat-tempat sumber air dan penampungan air mereka. Nabi ﷺ melarang keras hal tersebut[3] karena akan menyakiti dan membahayakan kesehatan manusia.
Tidak
selayaknya pula seorang muslim masuk kamar kecil dengan membawa sesuatu
yang berisi tulisan al-Quran atau dzikir. Jika dia khawatir barang itu
akan hilang, boleh membawanya masuk dan ditutupi dengan sesuatu
(dimasukkan dalam kantongan, tas dan sebagainya).
Demikian
pula tidak boleh bercakap-cakap saat buang hajat. Disebutkan dalam
hadits bahwa Allah sangat murka dengan perbuatan itu[4]. Begitu juga haram membaca al-Quran dalam kamar kecil.
- Jika telah telah menyelesaikan hajatnya, maka dia wajib membersihkan tempat keluarnya kotoran dengan air (istinja’) atau batu dan yang semacamnya (istijmar).
Istijmar
adalah bersuci dengan menggunakan batu atau yang semacamnya seperti
tisu, kain kasar dan lain-lain yang bisa membersihkan tempat keluarnya
kotoran tersebut. Disyaratkan tiga kali usapan dalam istijmar atau lebih
dari itu jika diperlukan. Tidak boleh beristijmar dengan tulang atau
kotoran binatang ternak (yang telah mengering) karena Nabi ﷺ melarangnya.[5]
Demikianlah
beberapa perkara yang mesti diperhatikan berkait dengan adab dalam
buang hajat. Segala puji bagi Allah atas karunia agama yang sempurna
ini. Semoga Allah berkenan menguatkan kita diatas agama ini
menganugerahkan kesabaran dalam mempelajari hukum-hukumnya dan
mengamalkan syari’atnya. Amin!
----------------------------------------
Footnotes :
[1] Hadits muttafaq ‘alaihi
[2] Hadits muttafaq ‘alaihi
[3] HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah
[4] HR. Ahmad, Abu Dawud dan Ibnu Majah
[5] HR. Muslim
[2] Hadits muttafaq ‘alaihi
[3] HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah
[4] HR. Ahmad, Abu Dawud dan Ibnu Majah
[5] HR. Muslim
Sumber : al-Mulakhkhash al-Fiqhi, Syaikh Dr. Shalih al-Fauzan
04 Juni 2015
Definisi Iman menurut Aqidah Ahlussunnah wal Jama'ah
Iman
menurut Aqidah para Salaf, Ahlussunnah wal Jama’ah adalah pembenaran dengan hati, ucapan
dengan lisan dan perbuatan dengan anggota tubuh, yang bertambah dengan
ketaatan dan berkurang dengan maksiat.
Iman adalah ucapan dan perbuatan. Yaitu ucapan hati dan lisan, serta perbuatan hati, lisan dan anggota tubuh.
Ucapan hati adalah pembenaran, pengakuan dan keyakinannya.
Ucapan lisan adalah pengakuan dalam bentuk amalan, yaitu dengan mengucapkan syahadatain dan mengamalkan segala konsekuensinya.
Perbuatan hati adalah niat, kepasrahan, keikhlasan, ketundukan, cinta dan kehendaknya untuk beramal shalih.
Sementara perbuatan lisan dan anggota tubuh adalah dengan mengerjakan segala perintah dan meninggalkan larangan-larangan.
Tidak ada
iman tanpa amalan. Tidak ada ucapan dan perbuatan tanpa niat. Dan tidak
ada ucapan, perbuatan dan niat tanpa kesesuaian dengan Sunnah.
Allah
telah menyebutkan sifat orang mukmin yang hak adalah untuk orang-orang
yang beriman dan mengamalkan konsekuensi dari iman mereka terhadap
prinsip-prinsip agama dan cabang-cabangnya, yang lahir maupun yang
batin. Konsekuensi dari iman itu akan nampak pada keyakinan-keyakinan
mereka, ucapan-ucapan mereka dan perbuatan-perbuatan mereka yang lahir
maupun yang batin.Allah Ta’ala berfirman,
إنَّمَا
المؤْمِنُونَ الذِيْنَ إذَا ذُكِرَ اللهُ وَجِلَتْ قلوبُهُم وَإذا
تُلِيَتْ عَلَيْهِم آيَاتُهُ زَادَتْهُم إيْمَانًا وعَلىَ رَبِّهِم
يَتَوَكَّلونَ، الذِيْنَ يُقِيمونَ الصَلاَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهم
يُنْفِقُونَ، أولَئِكَ هُمُ المُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُم دَرَجَاتٌ عِنْدَ
رَبِّهِم وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيْمٌ
“Sesungguhnya
orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama
Allah gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan kepada mereka
ayat-ayatNya bertambahlah iman mereka (karenanya) dan kepada Rabb-nya
mereka bertawakkal. (Yaitu) orang-orang yang mendirikan shalat dan
menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka. Itulah
orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Mereka akan memperoleh
beberapa derajat ketinggian di sisi Rabb-nya dan ampunan serta rezki
yang mulia.” (QS. Al-Anfal ayat 2-4).
Allah telah menggandengkan antara iman dengan amalan dalam banyak ayat al-Quran. Diantaranya adalah firmanNya,
إنَّ الَّذِيْنَ آمنُوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتِ كانَتْ لَهُم جَنَّاتُ الفِرْدَوسَ نُزُلاً
“Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan bermamal shalih, bagi mereka Surga Firdaus yang menjadi tempat tinggal.” (QS. Al-Kahf ayat 107).
Dan firmanNya,
وَتِلْكَ الجَنَّةُ أوْرِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُم تَعْمَلُونَ
“Dan itulah Surga yang diwariskan kepada kamu disebabkan amal-amal yang dahulu kamu kerjakan.” (QS. Az-Zukhruf ayat 72).
Dan Nabi ﷺ bersabda,
الإيمان بضعٌ وسبعون شعبةً فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبةٌ من الإيمان
“Iman
itu tujuh puluh sekian cabang. Yang paling utamanya adalah ucapan La
ilaha illa_Llahu. Yang paling rendahnya menyingkirkan duri dari jalan.
Dan sifat malu adalah cabang dari keimanan.” (HR. Al-Bukhary).
Telah
disebutkan dalam dalil-dalil yang banyak bahwa iman itu memiliki derajat
dan cabang, yang bisa bertambah dan berkurang, dan bahwa pemiliknya
bertingkat-tingkat. Diantaranya adalah firman Allah Ta’ala,
إنَّمَا
المؤْمِنُونَ الذِيْنَ إذَا ذُكِرَ اللهُ وَجِلَتْ قلوبُهُم وَإذا
تُلِيَتْ عَلَيْهِم آيَاتُهُ زَادَتْهُم إيْمَانًا وعَلىَ رَبِّهِم
يَتَوَكَّلونَ
“Sesungguhnya
orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama
Allah gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan kepada mereka
ayat-ayatNya bertambahlah iman mereka (karenanya) dan kepada Rabb-nya
mereka bertawakkal.” (QS. Al-Anfal ayat 2).
Dan sabda Nabi ﷺ,
من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان
“Siapa
diantara kamu yang melihat kemungkaran maka ubahlah dengan tangannya.
Jika tidak mampu, ubahlah dengan lisannya. Jika tidak mampu, ubahlah
dengan hatinya. Dan itulah selemah-lemah iman.” (HR. Muslim).
Demikianlah apa yang dipelajari dan dipahami oleh para Shahabat dari Rasulullah ﷺ, bahwa iman itu adalah keyakinan, ucapan dan perbuatan, yang bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan maksiat.
Berkata Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ‘anhu, “Kesabaran dalam keimanan ibarat kepala bagi tubuh. Siapa yang tidak memiliki kesabaran, tidak iman baginya.”
Berkata Abdullah bin Mas’ud radhiyallahu ‘anhu, “Ya Allah, tambahkan untuk kami keimanan, keyakinan dan fiqh.”
Berkata Abdullah bin Abbas, Abu Hurairah dan Abu ad-Darda’ radhiyallahu ‘anhum, “Iman itu bertambah dan berkurang.”
Berkata Waki’ bin al-Jarrah rahimahullahu, “Ahlussunnah mengatakan : Iman adalah ucapan dan perbuatan.”
Dan berkata Imam Ahlussunnah wal Jama’ah, Ahmad bin Hanbal rahimahullahu, “Iman itu bertambah dan berkurang. Bertambahnya itu dengan amalan, dan berkurangnya dengan meninggalkan amal.”[1]
Berkata al-Hasan al-Bashri rahimahullahu, “Bukanlah iman itu hiasan dan angan-angan semata, akan tetapi apa yang bersemayam dalam hati dan dibenarkan oleh amalan.”[2]
Ahlussunnah
juga mengatakan : Siapa yang mengeluarkan amalan dari keimanan maka dia
adalah seorang Murji’ah, ahli bid’ah yang sesat.
Dan siapa
yang menetapkan syahadatain dengan lisannya serta meyakini keesaan Allah
dengan hatinya, akan tetapi dia memiliki kelalaian dalam mengamalkan
sebagian dari rukun-rukun Islam dengan anggota tubuhnya, maka imannya
tidak sempurna. Siapa yang tidak pernah menetapkan syahadatain, tidak
akan pernah ada padanya nama iman dan islam.
——————————
[1] Seluruh atsar yang disebutkan diriwayatkan dengan jalan-jalan periwayatan yang shahih oleh Imam al-Lâlikâ’i rahimahullahu dalam bukunya Syarh Ushûl I’tiqâd Ahl as Sunnah wa al Jamâ’ah.
[2] Kitâb al Îmân, oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu.
01 Juni 2015
Tabarruk dengan Tempat, Masa atau Sesuatu yang Tidak Disyari’atkan
Diantara
bentuk tabarruk terlarang yang bid’ah dan banyak dilakukan oleh kalangan
awam dari kaum muslimin adalah bertabarruk dengan tempat-tempat,
zaman/masa atau sesuatu yang tidak pernah disebutkan dalil tentang
disyari’atkannya perkara tersebut.
Diantara contoh-contoh tabarruk bid’ah tersebut adalah hal-hal berikut ini :
1. Tempat-tempat yang kebetulan pernah dilalui Nabi ﷺ
atau beliau pernah beribadah kepada Allah di tempat tersebut tanpa
sengaja memaksudkannya. Hanya kebetulan beliau berada di tempat itu saat
datangnya waktu untuk beribadah, dan tidak ada dalil syar’i yang
menunjukkan akan keutamaannya.
Diantara
tempat-tempat tersebut yang diagungkan orang-orang awam dan dituju untuk
melakukan ibadah padanya atau meyakini keutamaannya adalah bukit Tsaur,
gua Hira’, bukit Arafah, tempat-tempat yang pernah dilewati Nabi ﷺ
dalam perjalannya, tujuh masjid yang dekat khandaq (bekas parit saat
perang Khandaq), tempat yang diklaim oleh sebagian orang bahwa Nabi ﷺ
dilahirkan di tempat itu, padahal hal seperti ini banyak
diperselisihkan, dan juga tempat-tempat yang diklaim sebagai tempat
lahirnya atau hidupnya seorang nabi atau wali, tanpa ada yang bisa
memastikan tentang kebenarannya.
Karenanya,
tidak boleh seorang muslim sengaja mengunjungi tempat-tempat tersebut
untuk beribadah kepada Allah padanya dengan memanjatkan doa,
melaksanakan shalat dan yang semacamnya, sebagaimana tidak boleh juga
mengusap-usap tempat-tempat itu untuk mencari keberkahan. Tidak
disyari’atkan pula untuk memanjat naik ke bukit-bukit pada hari Arafah,
bahkan tidak juga untuk mendaki bukit Arafah pada hari Arafah atau yang
selainnya. Tidak juga disyari’atkan mengusap batu yang berada di puncak
bukit tersebut. Yang disyari’atkan hanyalah wuquf di batu-batu yang
dekat darinya jika memungkinkan. Jika tidak, seorang yang berhaji boleh
wukuf di mana saja dari tanah Arafah.
Tidak
pernah dinukil dari seorang Shahabat pun bahwa mereka sengaja datang ke
tempat-tempat itu untuk bertabarruk dengan menciumnya atau mengusapnya
atau sengaja untuk beribadah padanya.
Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah (II/84) bahwa Umar bin al-Khaththab radhiyallahu ‘anhu
saat kembali dari berhaji, ia melihat orang-orang berbondong-bondong
mendatangi dan shalat di sebuah masjid. Ia bertanya tentang hal
tersebut, maka mereka menjelaskan, “(Itu adalah) masjid yang dahulu Nabi ﷺ
pernah shalat di tempat itu.” Maka
Umar berkata, “Sungguh, yang membinasakan orang-orang sebelum kalian
karena mereka menjadikan bekas-bekas peninggalan nabi-nabi mereka
sebagai tempat ibadah. Siapa yang menjumpai salah satu dari
masjid-masjid ini dan tiba waktu shalat, maka ia boleh shalat. Jika
tidak, hendaknya ia lanjutkan (perjalanannya).”
2.
Tabarruk dengan sebagian pohon, batu, pilar, sumur dan mata air yang
disangka oleh sebagian orang awam bahwa benda itu memiliki keutamaan,
entah dengan keyakinan mereka bahwa seorang nabi atau wali pernah
berdiam di batu tersebut, atau keyakinan mereka bahwa seorang nabi
pernah tidur di bawah pohon itu, atau salah seorang dari orang-orang
awam itu melihat mimpi bahwa pohon itu atau batu itu memiliki
keberkahan, atau keyakinan bahwa seorang nabi pernah mandi di sebuah
sumur atau mata air, atau seseorang pernah mandi padanya dan sembuh dari
penyakitnya, dan yang semacamnya. Mereka pun akhirnya mendatanginya dan
mencari keberkahan padanya dengan mengusap-usap batu atau pohon, dan
mandi dengan air dari sumur atau mata air tersebut dan menggantungkan
kertas, paku atau kain di pohon-pohon itu. Terkadang, perbuatan ini
membawa sebagian mereka pada peribadatan kepada benda-benda itu, dengan
meyakini bahwa benda-benda itu dapat memberi manfaat atau menolak
keburukan.
Tidak diragukan bahwa semua bentuk tabarruk yang seperti ini adalah haram dengan ijma’
(kesepakatan) para ulama dan hal itu tidak dilakukan kecuali oleh
orang-orang jahil. Yang demikian itu adalah termasuk mengada-adakan
ibadah yang tidak memiliki landasan dalam Syari’at, dan merupakan sebab
terbesar bagi bagi jatuhnya umat ini dalam syirik akbar.
Diriwayatkan oleh Imam al Bukhary dan Imam Muslim dari Abu Waqid al Laitsi radhiyallahu ‘anhu, ia berkata : Kami pergi bersama Rasulullah ﷺ menuju Hunain, sementara kami belum lama lepas dari kekufuran. Orang-orang musyrik memiliki sebuah sidrah
(pohon bidara) yang mereka beri’tikaf di sekelilingnya dan
menggantungkan padanya senjata-senjata dan barang-barangnya, yang
dinamakan Dzât Anwâth. Kami pun melewati pohon tersebut. Kami berkata :
“Wahai Rasullullah, buatkan untuk kami Dzât Anwâth sebagaimana mereka
memiliki Dzât Anwâth.”
Beliau ﷺ bersabda :
الله أكبر!! هذا كما قالت بنو إسرائيل : { اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون } لتركبن سنن من كان قبلكم
“Allâhu akbar!! Perkataan ini sebagaimana yang dikatakan oleh Bani Israil: ‘Buatkan
untuk kami sebuah tuhan (berhala) sebagaimana mereka mempunyai beberapa
tuhan!’. Musa berkata: ‘Sesungguhnya kamu ini adalah kaum yang bodoh!’.
Sesungguhnya kalian pasti akan mengikuti kebiasaan orang-orang sebelum
kalian.”
Termasuk
perkara yang mesti diketahui oleh setiap muslim dalam Islam ini bahwa
tidak ada batu dan yang semacamnya yang disyari’atkan untuk diusap atau
dicium demi untuk mendapatkan keberkahan. Bahkan, Maqam Ibrahim ‘alaihissalam tidak disyari’atkan untuk dicium walaupun beliau pernah berdiri diatasnya dan bekas kedua kakinya ada diatasnya.
Adapun
mengusap dan mencium Hajar Aswad atau mengusap Rukun Yamani saat thawaf,
maka perbuatan ini semata-mata bentuk ibadah kepada Allah dan mengikuti
sunnah Nabi ﷺ. Karenanya, saat mencium Hajar Aswad, Umar radhiyallahu ‘anhu
pernah berkata, “Sungguh, aku mengetahui bahwa engkau hanya sebuah batu
yang tidak memberi keburukan atau memberi manfaat. Kalau bukan karena
aku melihat Rasulullah ﷺ menciummu, niscaya aku tidak akan menciummu.” (HR. al-Bukhary dan Muslim).
Wajib bagi pemerintah dan orang-orang yang memiliki wewenang dan
kemampuan untuk menebang setiap pohon, menghancurkan setiap sumur dan
mata air, serta menyingkirkan setiap batu yang dituju orang-orang awam
untuk bertabarruk dengannnya sebagaimana yang dilakukan Umar radhiyallahu ‘anhu ketika ia menebang pohon Bai’atur Ridhwan.
3.
Tabarruk dengan sebagian malam atau hari yang dikatakan bahwa pada malam
atau hari itu terjadi sebuah peristiwa besar dan luar biasa. Seperti
malam yang dikatakan padanya terjadi peristiwa Isra’ & Mi’raj, atau
hari yang diklaim sebagai hari kelahiran Nabi ﷺ.
Semua ini tidak memiliki landasan sejarah yang kuat karena
diperselisihkan oleh para ulama dan bahkan tidak memiliki riwayat yang
sah dari Nabi ﷺ tentang penetapan hari
kejadiannya. Perkara-perkara seperti ini adalah buatan manusia yang
tidak pernah disebutkan dalam dalil syar’i akan keutamaannya atau
keutamaan beribadah padanya.
Sumber : Tahdzîb Tashîl al Aqîdah al Islâmiyyah